Aceh, dengan berbagai kewenangan sebagai daerah otonomi khusus, kiranya dapat memacu ketertinggalan dari berbagai aspek pembangunan.
Oleh Mirza Fanzikri*
Tepat 15 Agustus lalu, masyarakat Aceh memperingati hari Damai Aceh. Pelbagai tokoh nasional dan dunia berkumpul di Banda Aceh. Mereka hadir di berbagai even, konferensi, seminar, dan podcast, untuk merayakan dan merefleksikan 20 tahun berakhirnya konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI).
Meskipun rangkaian kegiatan tersebut telah usai, namun beberapa penggalan bait diskusi masih terus bergulir dan kerap menjadi topik yang dibahas di kalangan masyarakat luas, terutama di media sosial.
Salah satu isu yang menarik adalah pernyataan seorang juru runding RI-GAM, Juha Christensen. Ia mengatakan bahwa Aceh tidak akan pernah merdeka karena letak geostrategis nya di Selat Malaka, yang dikenal sebagai jalur maritim penting perdagangan internasional.
Memang, argumen tersebut terkesan skeptis bagi Masyarakat Aceh. Di satu sisi, alasan itu cenderung menafikan sejarah entitas Aceh yang pernah menjadi sebagai sebuah bangsa berdaulat. Pun, mengabaikan kegigihan semangat perjuangan Aceh di era kolonial Belanda dan pasca kemerdekaan Indonesia. Karena itu, wajar jika sebagian masyarakat Aceh memandang pendapat tersebut sebagai narasi pesimistik.
Namun, dalam paradigma hubungan internasional, pernyataan mediator perdamaian asal Finlandia tersebut memiliki alasan yang dapat diuraikan secara akademis.
Aceh dan Dunia Internasional
Di era pra-kemerdekaan Indonesia, Aceh memiliki peran yang luas di panggung global. Sekitar abad ke-17’an, Aceh berada di puncak keemasannya. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh bahkan mampu memperluas wilayah kekuasaannya di sebagian besar Sumatera hingga ke semenanjung Malaya.
Aceh juga terkenal dengan diplomasi global dengan beragam bangsa dan negara, termasuk Turki, Arab, China, India, Eropa, hingga Amerika Serikat (AS). Singkatnya, pra-kemerdekaan, dunia mengenal Aceh sebagai hub perdagangan global, kemajuan maritim, dan pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara.
Namun, pasca kemerdekaan Indonesia, posisi Aceh mengalami subordinasi. Dinamika politik dan konflik panjang dengan pemerintah pusat menempatkan Aceh di sudut yang terisolasi.
Sebagai provinsi, Aceh telah melewatkan perannya sebagai ‘pemain’ di pelbagai peristiwa transformasi ekonomi politik di kancah internasional. Aceh kehilangan peran di panggung global, termasuk di Badan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) and peristiwa perang dingin.
Singkat kata, memori masyarakat Internasional terhadap Aceh pasca kemerdekaan terkonsentrasi dalam dua isu besar: konflik pusat-daerah (1953 – 2005) dan Tsunami (2004-2008). Dua peristiwa akbar tersebut menempatkan entitas Aceh dalam pusat perhatian dunia, di saat lembaga-lembaga internasional sedang gencarnya melaksanakan agenda kampanye hak asasi manusia (HAM) dan bantuan kemanusiaan.
Di waktu yang bersamaan, sejak kemerdekaan, Indonesia sangat dekat dengan AS; yang merupakan representatif dominasi global. Secara politik, Indonesia memainkan peran penting dalam percaturan politik dunia yang cenderung dianggap sebagai pendukung setia AS dan sekutunya (Barat) dalam menjalankan agenda global di kawasan Asia Tenggara.
Perspektif Politik Global
Dalam perspektif konstruktivisme, realitas sejarah eksistensial Aceh sebagai entitas lokal menjadi modal penting (necessary) dalam meyakinkan dunia internasional. Isu tentang identitas, hak, dan pelanggaran HAM menjadi kosa kata kunci untuk menarik perhatian lembaga internasional. Namun, alasan-alasan ini tentu tidak cukup (insufficient) untuk memperoleh dukungan para elit global. Tentunya, ada pelbagai kalkulasi kepentingan yang patut dipertimbangkan. Termasuk geopolitik, ekonomi dan keamanan global.
Benar, secara geopolitik, bahwa posisi Aceh di Selat Malaka dapat menjadi alasan utama ‘Aceh tidak akan merdeka,’ sebagaimana disampaikan Juha dalam sebuah Podcast yang dirilis Sagoe TV. Menerjemahkan argument tersebut, setidaknya punya dua dasar yang menempatkan Aceh ‘tidak menguntungkan’ elit global secara politik dan ekonomi: identitas Islam dan formasi pemerintahan.
Tentu saja, persepsi global tersebut berkaitan erat dengan rentetan peristiwa politik internasional. Misalnya, berakhirnya perang dingin dan terjadinya Revolusi Republik Islam di Iran pada 1979, kekhawatiran Barat terhadap hegemoni Islam mulai menguat.
Apalagi, menjelang perjanjian damai antara RI dan GAM, tren Islamophobia global tersebut sedang sangat masif dan meningkat. Terutama pasca terjadinya peristiwa 9/11 dan dideklarasikannya perlawanan terhadap terorisme global (Global War on Terror) pada tahun 2001.
Dengan demikian, Aceh, sebagai daerah yang identik dengan Islam yang mengakar secara sejarah dan di masyarakat, dapat dipandang sebagai ‘ancaman’ secara ideologi dan politik yang berpotensi mengganggu kepentingan Barat di Kawasan Asia Tenggara.
Dalam kacamata realisme, tentu saja Barat tidak mungkin menyetujui kemunculan entitas baru yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan regional dan kepentingan elit global. Barat belajar banyak dari kontestasi di terusan Suez; jalur maritim paling strategis di Timur Tengah.
Belum lagi, Aceh punya legasi sejarah kepemipinan yang berbentuk kerajaan dan berpotensi mewarisi sistem monarki. Tentu saja, hal ini tidak sejalan dengan agenda liberalisme dan demokratisasi global saat itu.
Geostrategis Selat Malaka
Oleh karena itu, keberadaan Aceh di pintu gerbang Selat Malaka adalah suatu faktor yang krusial. Ia dapat menjadi faktor strategis sekaligus ancaman.
Secara ekonomi politik, jalur maritim yang menghubungkan Samudra Hindia, Pasifik, dan Laut Cina Selatan tersebut merupakan poin vital sebagai rute perdagangan lintas negara, sekaligus hub ekonomi Asia Tenggara. Maka, bagi global, memastikan keamanan rute tersibuk kedua di dunia tersebut adalah jauh lebih penting demi kelangsungan kepentingan elit global.
Karena itu, tidak heran, jika ‘dilema Selat Malaka’ menempatkan Aceh berada dalam persimpangan geopolitik global.
Memacu Pembangunan
Terlepas dari itu, kini, perdamaian Aceh adalah realitas dan rahmat Allah. Aceh, dengan berbagai kewenangan sebagai daerah otonomi khusus, kiranya dapat memacu ketertinggalan dari berbagai aspek pembangunan.
Memang, Selat Malaka sangat strategis. Baik secara keamanan, politik, maupun ekonomi. Tidak hanya bagi global, terutama bagi kepentingan nasional. Namun, tanpa kolaborasi pemerintah pusat dan berbagai stakeholder di daerah, potensi geostrategis ini sulit mencapai kejayaannya.
Karena itu, geostrategis Aceh di pintu masuk rute perdagangan global perlu diperhatikan dan dioptimalkan dengan serius. Diantaranya, peran Badan Kawasan Pengusahaan Sabang (BPKS) perlu didukung dan didorong lebih kuat, agar kinerjanya dapat memberikan dampak bagi kebangkitan industri dan kemajuan konomi lokal. Kiranya perdamaian Aceh dapat membawa keberkahan bagi masyarakat Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabatnya di mata dunia. []
*Mahasiswa S3 Ilmu Politik di Universitas Islam Internasional Indonesia, Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

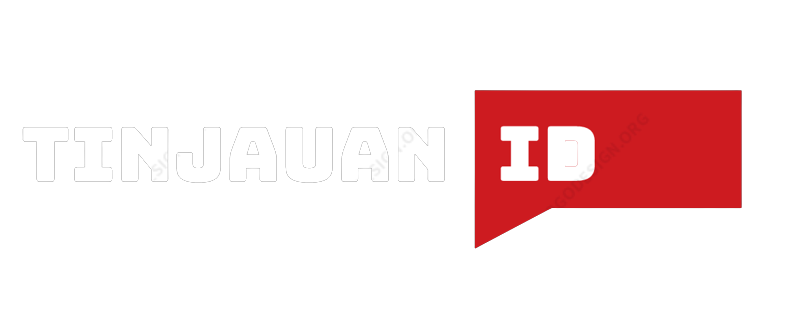














Discussion about this post