Para penyintas bencana banjir bandang Aceh di Pidie Jaya tak hanya kehilangan rumah, tetapi juga merasakan runtuhnya rasa aman. Para penyintas kini hidup dalam ketidakpastian.
Pidie Jaya – Malam itu, Rabu (26/12/2025) Nursiah tak pernah menyangka air akan datang secepat dan seganas itu. Hujan yang sejak sore mengguyur Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, tiba-tiba berubah menjadi teror.
Menjelang tengah malam, suara gemuruh memecah sunyi. Dalam hitungan menit, banjir bandang menerjang kampungnya.
“Air masuk deras sekali. Saya cuma sempat bangunkan anak-anak. Tidak ada yang bisa diselamatkan,” ujar Nursiah (45), matanya berkaca-kaca saat ditemui, Rabu (24/12/2025).
Rumah sederhana yang selama ini ia tempati bersama suami dan dua anaknya kini nyaris tenggelam. Lumpur dan material banjir menimbun bangunan hingga ketinggian hampir dua meter.
Dinding rumah tak lagi terlihat utuh, hanya atap yang masih menyembul, seolah menjadi saksi bisu kehidupan yang tertinggal di bawahnya.
Malam itu, Nursiah berlari dalam gelap. Ia menggandeng anak-anaknya, menembus air yang terus meninggi. Tak ada perabot, tak ada dokumen, tak ada pakaian yang sempat dibawa. Hanya tubuh yang basah, pakaian yang melekat di badan, dan doa agar anak-anaknya selamat.
Kini, sebulan pascabanjir bandang, Nursiah masih hidup berpindah-pindah. Ia menumpang di rumah saudara. Namun tempat itu bukan pengungsian yang layak. Ruang sempit, keterbatasan air bersih, dan rasa sungkan menumpang terlalu lama menjadi beban tersendiri.
“Data sudah diminta, katanya mau dibangun hunian sementara. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” katanya lirih.

Harapan Nursiah sederhana. Ia ingin segera dipindahkan ke hunian sementara agar anak-anaknya bisa hidup lebih layak. Ia juga berharap rumahnya yang kini terkubur lumpur dapat dibangun kembali.
“Kalau pun tidak bisa dibongkar semua, rumah itu ditinggikan saja. Saya bangun di atasnya. Yang penting ada tempat pulang,” ucapnya.
Krisis Air Bersih
Persoalan lain yang tak kalah mendesak adalah krisis air bersih. Sejak banjir bandang melanda, sumber air rusak, sumur tercemar lumpur, dan distribusi air bersih terbatas.
“Air bersih sangat susah. Untuk masak, mandi, apalagi anak-anak, susah sekali,” katanya.
Kondisi serupa juga dirasakan para penyintas lain yang kini bertahan di pengungsian Gedung Serbaguna Tgk Chik Pante Geulima, Kabupaten Pidie Jaya, kawasan kompleks perkantoran Bupati Pidie Jaya.
Di salah satu sudut gedung, Roslina Gampong Manyangcut, Kecamatan Meureudu, duduk memeluk kedua anaknya.
Sudah hampir sebulan ia tinggal di sana. Kepastian tentang masa depan masih menggantung.
“Kami menunggu. Sampai kapan di pengungsian, belum tahu,” ucap Roslina pelan.
Bantuan logistik memang datang. Beras, mie instan, dan kebutuhan dasar relatif tersedia. Namun persoalan air bersih tak kunjung teratasi sepenuhnya. Bagi perempuan dan anak-anak, krisis ini terasa berlipat ganda.
“Air sering tidak cukup. Anak-anak butuh mandi, butuh bersih. Perempuan juga punya kebutuhan sendiri,” katanya.
Di pengungsian, air bersih bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan soal kesehatan dan martabat. Anak-anak mulai mengalami keluhan kulit.
Rumahnya masih tenggelam lumpur tebal. Untuk membersihkannya, ia harus menyewa jasa alat dan tenaga. Biayanya tak main-main, mencapai hampir Rp10 juta. Jumlah yang mustahil ia penuhi dalam kondisi serba kehilangan.
“Katanya kalau mau bersihkan lumpur harus pakai alat, biayanya mahal. Bisa sampai sepuluh juta,” ujarnya.
Banjir bandang di Pidie Jaya tak hanya menenggelamkan rumah, tetapi juga meruntuhkan rasa aman. Para penyintas kini hidup dalam ketidakpastian, menunggu keputusan yang belum jelas arahnya.
Hunian sementara yang dijanjikan belum terwujud. Krisis air bersih masih membayangi hari-hari di pengungsian. Sementara perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan menanggung dampaknya. [*]

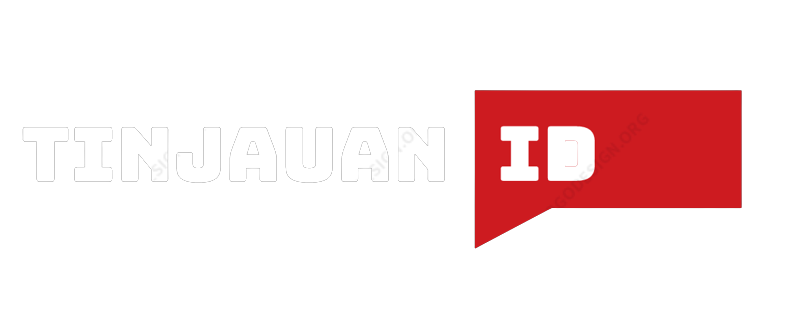














Discussion about this post