Di negara kita, mitigasi bencana sering dianggap tidak penting dan tidak menjadi prioritas. Kita hanya fokus pada bantuan di saat krisis, bukan sistem sebelum krisis.
“Halah, buat apa bikin kesiapsiagaan sebelum bencana. Hidup mati di tangan Tuhan.” Kalimat ini sering terdengar paling keras justru saat peringatan bencana datang bertubi-tubi. Seolah perencanaan, mengidentifikasi, memitigasi, kesiapsiagaan, pembentukan relawan, hingga penyusunan rencana aksi berbasis risiko untuk mengurangi dampak bencana adalah bentuk ketakutan dan tanda iman yang goyah.
Padahal, sejarah justru berkata sebaliknya. Dalam kisah klasik peradaban, ketika krisis besar akan datang, yang dilakukan bukan pasrah (tawakkal) hanya berserah diri pada Tuhan. Konsep tawakkal dalam Islam harus didahului dengan perbuatan atau upaya pencegahan yang kita kenal dengan ikhtiar atau berusaha maksimal.
Persiapan Sistemik Mitigasi Bencana
Pemerintah seringkali gagap dalam penanganan bencana karena kerap melewatkan perencanaan memitigasi bencana. Ironinya, dalih religius–menyalahkan Tuhan dan alam dengan menyebut ‘bencana alam’ kerap dipakai untuk membenarkan ketiadaan desain kebijakan yang matang.
Padahal, alam hanya salah satu faktor bencana disamping faktor-faktor lain; seperti pembangunan, faktor sosial dan politik melalui kebijakan, terutama terkait hutan, lahan, dan tambang, serta lingkungan.
Kisah Nabi Yusuf AS terlalu sering dipersempit jadi cerita mimpi dan penjara, padahal intinya adalah manajemen krisis bencana paling modern pada masanya. Saat mengetahui akan ada tujuh tahun masa subur diikuti tujuh tahun masa paceklik, Nabi Yusuf tidak berhenti berdoa. Di samping itu ia merancang mitigasi besar-besaran. Gandum disimpan, konsumsi diatur, akumulasi dilakukan, lalu kekayaan dikelola agar bisa didistribusikan saat krisis datang.
Hal itu bukan tindakan spontan, tetapi kebijakan jangka panjang berbasis proyeksi. Dalam bahasa hari ini, hal tersebut adalah penyimpanan sumberdaya (wealth preservation) level tertinggi. Menjaga sumber daya agar masyarakat tidak runtuh saat sistem pangan kolaps. Kita tetap berdoa, tetapi doa tidak menggantikan perencanaan dan persiapan.
Mitigasi Bencana Lintas Budaya
Begitu juga dalam tradisi kebudayaan Aceh, mitigasi bencana dimulai dari desain rumah panggung dengan tinggi tiang hingga 3 meter, hingga persiapan logistik misalnya umbung gabah, menyimpan garam, minyak kelapa, asam sunti, ikan olahan yang disebut ikan kayu (keumamah), hingga dendeng sapi dan makanan yang diawetkan. Masyarakat juga menanam sagu, ubi, pisang, ketela sebagai makanan sekunder pengganti beras.
Bayangkan dalam bencana baniir Sumatera kali ini, betapa susahnya orang Bener Meriah dan Aceh Tengah yang tinggal di dataran tinggi harus jalan kaki berjam-jam hanya untuk mencari beras, sementara Aceh Utara sebagai lumbung padi, sawahnya telah hancur menjelang panen.
Masalahnya, banyak negara modern justru mundur dari pelajaran mitigasi bencana ini. Ketika risiko bencana meningkat, yang dibangun sering kali hanya narasi. Data iklim tersedia, peta risiko ada, sejarah bencana tercatat rapi, tapi mitigasi tetap setengah hati.
Menurut laporan berbagai lembaga nasional dan internasional, biaya penanganan pascabencana selalu lebih besar dibanding biaya pencegahan. Namun anggaran sering habis untuk respons darurat, bukan persiapan jangka panjang. Polanya berulang. Setelah bencana, negara hadir. Sebelum bencana, negara absen. Seolah krisis baru sah ditangani setelah korban jatuh.
Di negara lain, pendekatannya lebih dingin dan tidak emosional. Jepang misalnya menjadikan mitigasi bencana sebagai bagian dari budaya dan kebijakan publik. Pendidikan, infrastruktur, dan simulasi dilakukan jauh sebelum gempa datang.
Di Belanda, manajemen air dibangun berabad-abad karena negara itu sadar hidupnya berada di bawah permukaan laut. Mereka tidak menunggu banjir untuk bertobat. Mereka menganggap mitigasi sebagai bentuk tanggung jawab, bukan perlawanan terhadap takdir. Bahkan di sektor keuangan, banyak negara mendorong warganya memahami instrumen lindung nilai sebagai bagian dari ketahanan ekonomi rumah tangga.
Sementara di negara kita, mitigasi bencana sering dianggap tidak penting dan tidak menjadi prioritas. Kita hanya fokus pada bantuan di saat krisis, bukan sistem sebelum krisis.
Padahal yang dilakukan Nabi Yusuf dalam memitigasi bencana justru sebaliknya. Ia membangun lumbung saat semua orang merasa aman. Hari ini, lumbung itu bentuknya berbeda. Bukan lagi gudang gandum, tapi instrumen keuangan dan aset lindung nilai. SBN, emas, saham produktif, bahkan aset digital seperti Bitcoin, dianggap sebagai lumbung modern. Bukan untuk spekulasi, tapi untuk menjaga nilai di tengah inflasi, krisis, dan ketidakpastian.
Dampaknya terasa langsung ke kehidupan masyarakat. Ketika krisis datang, tabungan menipis, harga melonjak, dan negara kembali sibuk memadamkan api. Martabat masyarakat diuji bukan karena kurang iman, tapi karena sistem tidak memberi ruang aman. Keadilan sosial sulit dicapai jika hanya mereka yang paham mitigasi bisa bertahan. Kualitas hidup menurun karena kebijakan selalu reaktif. Keberlanjutan sosial terganggu karena perencanaan dianggap wacana elit. Padahal kenyataan lapangan menunjukkan satu hal. Yang selamat dari krisis bukan yang paling keras menolak persiapan, tapi yang paling disiplin membangun upaya mitigasi sejak awal.
Pada akhirnya, iman dan mitigasi tidak pernah bertentangan. Yang bertentangan adalah kemalasan sistem yang pasrah terhadap takdir. Nabi Yusuf tidak memilih antara doa atau perencanaan. Ia melakukan keduanya. Negara dan masyarakat hari ini seharusnya belajar dari situ.
Bencana boleh datang kapan saja, tapi kebijakan yang matang seharusnya sudah ada sebelum itu. Karena pasrah tanpa persiapan bukan kebijaksanaan. Itu hanya cara lain untuk menunda tanggung jawab.
Oleh: Zulfadli Kawom, penulis adalah budayawan.

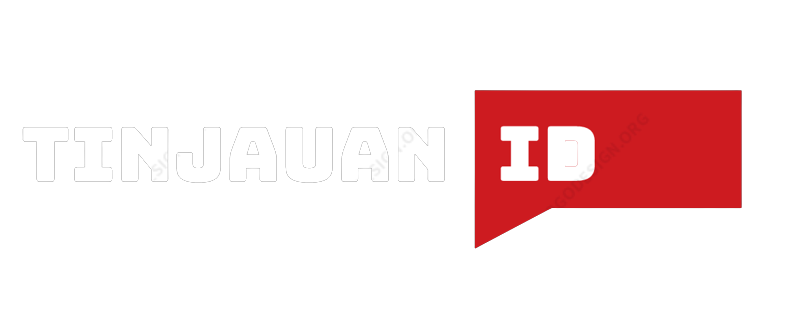














Discussion about this post