Oleh: Bung Alkaf*
Baru-baru ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menjamu ulama-ulama dayah yang tergabung di dalam MUNA. Tampak dalam pertemuan itu Abu Paya Pasi dan Abon Arongan. Saya tertarik untuk menerjemahkan keterlibatan ulama dayah dalam politik Aceh kontemporer.
Selama dua puluh tahun perdamaian, ulama dayah memanfaatkan ruang politik yang terbentuk melalui beberapa hal:
Pertama, aliansi dengan mantan Gerakan Aceh Merdeka yang telah terintegrasi dalam tubuh politik nasional.
Kedua, melalui mobilisasi sumber daya yang dayah miliki secara internal, terutama jaringan lembaga pendidikan dayah yang tersebar di seluruh pelosok Aceh.
Ketiga, wacana keagamaan yang mereka kuasai melalui tagline aswaja.
Keempat, keberhasilan alumni dayah melakukan mobilisasi vertikal dalam dunia birokrasi, yang ditunjukkan dengan dikuasainya pos-pos yang dahulunya ditempati oleh muslim modernis Aceh.

Keempat faktor ini dapat dijelaskan dengan lebih rinci karena tidak ada dayah yang tunggal seperti yang dibayangkan oleh banyak studi. Walaupun secara genealogi terhubung sampai ke Labuhan Haji, namun dalam praktik berikutnya terdapat perbedaan, terutama secara politis dan orientasi agama.
Secara politis, mobilisasi kelompok dayah pertama kali dalam bentuk organisasi paguyuban HUDA, Himpunan Ulama Seluruh Aceh. Organisasi dayah ini berperan di masa-masa kritis konflik Aceh pascareformasi.
Setelah perjanjian damai, organisasi ini semakin solid. Melalui jaringan dayah Al Aziziyah Samalanga, HUDA menjelma menjadi organisasi strategis tempat berkumpulnya para ulama tua dan muda dari kalangan dayah.
Evolusi muktahir dari keberadaan HUDA adalah dengan membentuk partai lokal, PAS. Di sisi lain, ulama dayah juga berada dalam organisasi MUNA, Majelis Ulama Nanggroe Aceh. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari aliansi ulama dayah di bagian timur Aceh dengan organisasi GAM di masa konflik.
Dalam era perdamaian, para ulama tersebut menjadi bagian dari proyek etnonasionalisme GAM dalam postur besar Lembaga Wali Nanggroe. Sebelum Mualem menjadi Gubernur Aceh, MUNA praksis terabaikan dalam sirkualsi elit.
Kini, setelah Mualem memegang tampuk kekuasaan, perlahan MUNA mendapatkan tempat. Diawali dengan menempatkan ketua MUNA, Abu Paya Pasi, sebagai Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman, Mualem pun dengan terbuka menunjukkan dukungannya kepada MUNA.
Naik daunnya MUNA juga bentuk residu dari dukungan ulama jaringan Al Aziziyah kepada kompetitor Mualem, Bustami Hamzah, pada Pilkada lalu.
Terakhir, ada varian lain dalam tubuh ulama Aceh, yaitu Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf (MPTT). Kelompok ini, yang awalnya, memiliki basis di bagian selatan Aceh, karena keberadaan patron Amran Wali, kini mulai merambah ke wilayah timur dan utara Aceh, yang selama ini dikuasai oleh ulama berhaluan fiqah ortodoksi.
Berkebalikan dengan itu, MPTT merupakan corak gerakan keulamaan dayah yang berorientasi heterodoksi. Di masa lalu, kedua varian ini saling bersiteru untuk memperebutkan otoritasisasi keagamaan di Aceh. Menariknya, Mualem, melalui wakilnya, Darwis Jeunieb, melantik Amran Wali sebagai Wali Agama Aceh di Masjid Raya Baiturrahman.
Di tangan Mualem, dua varian keulamaan diajaknya dalam satu nafas, MUNA dan MPTT. Sekarang, kita sedang menunggu, apakah HUDA akan dijak dalam satu gerbong atau akan menjadi oposannya Mualem, bahkan lawan politik GAM di masa depan secara terbuka? Atau, kita akan melihat bentuk komunikasi politik baru antara HUDA dengan Mualem?
*Penulis adalah esais.

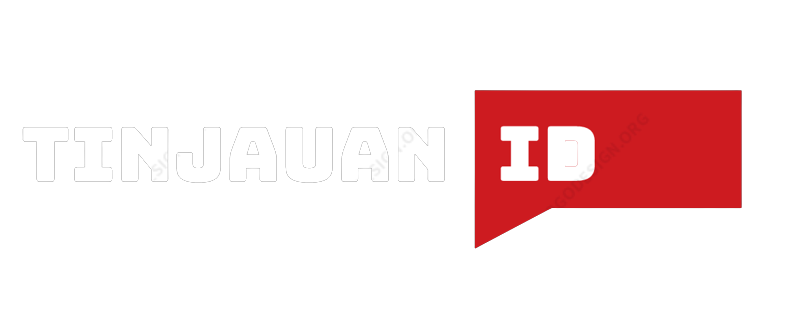














Discussion about this post