Tulisan “Masih Adakah Ulama Alumni Dayah?” sebenarnya bisa menjadi sangat bagus jika ditulis dengan semangat memperkuat, bukan merendahkan. Sayangnya, tulisan tersebut justru mencerminkan kebingungan arah berpikir dan kegagalan memahami kedalaman makna ulama dalam tradisi keilmuan Islam.
Oleh: Tgk. Abdul Muhaimin, S.Sos., M.H
Sebuah tulisan opini berjudul “Masih Adakah Ulama Alumni Dayah?” yang ditayangkan oleh sebuah media pada tanggal 31 Juli 2025 cukup menarik perhatian saya, tapi bukan karena kualitas isinya yang mencerahkan, melainkan karena kekaburan arah dan kecenderungan menyudutkan lembaga keulamaan di Aceh, dayah, secara tidak proporsional.
Jujur saya katakan, membaca tulisan tersebut justru membuat saya bertanya-tanya: apakah penulisnya memang tidak tahu apa yang ingin ia sampaikan, sehingga akhirnya menulis sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditulis? Tulisan tersebut nyaris tidak memiliki pijakan data yang kuat, tidak jelas batasan istilahnya, dan pada beberapa bagian justru menyesatkan pembaca dalam memahami realitas eksistensi ulama di tengah masyarakat kita.
Salah satu pernyataan yang sangat perlu diluruskan adalah klaim bahwa ulama alumni dayah semakin sedikit atau tidak dikenal lagi oleh publik. Narasi ini terasa terburu-buru, bahkan sembrono, karena tidak disertai pembacaan objektif terhadap dinamika pendidikan dayah dan kontribusi alumni-nya dalam berbagai bidang kehidupan.
Padahal faktanya, Aceh hari ini memiliki lebih dari 1.300 dayah aktif, termasuk Ma’had Aly, yang menjadi simbol pengakuan negara terhadap keilmuan dayah. Lulusannya kini bisa menjadi dosen, ASN, bahkan pemimpin institusi.
Tak sedikit dari mereka yang menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral, baik di dalam maupun luar negeri. Ini membuktikan bahwa tafaqquh fiddin tidak lagi terkungkung di satu ruang sempit, tetapi telah bersinergi dengan dunia akademik modern.
Jika publik tidak mengenal satu dua nama ulama, itu bukan berarti para ulama tidak ada. Bisa jadi, kita sendiri yang gagal memperkenalkan mereka. Namun menyimpulkan bahwa ulama alumni dayah semakin hilang hanya karena tidak populer di media sosial atau dunia politik, adalah kesimpulan yang terlalu gegabah.
Kita perlu membedakan antara popularitas dan integritas. Ulama sejati seringkali menjauh dari hiruk-pikuk panggung kekuasaan. Mereka sibuk mengajar, membina akhlak generasi muda, menjaga khazanah kitab kuning, dan menjadi penopang moral di tengah derasnya arus materialisme.
Tidak semua ulama aktif memburu panggung. Bahkan, dalam tradisi keilmuan kita, menjauhi sorotan dunia adalah bentuk kerendahan hati seorang alim.
Sebaliknya, mempertanyakan eksistensi ulama hanya karena tidak tampil di ruang politik atau publikasi mainstream, sama saja kita menilai ikan berdasarkan kemampuannya memanjat pohon.
Saya menyayangkan gaya penulisan opini tersebut yang cenderung spekulatif dan tidak akademis. Istilah “ulama alumni dayah makin hilang” atau “tak lagi dikenali masyarakat” dipakai tanpa landasan riset.
Bahkan, dalam beberapa bagian, tulisan itu terkesan memaksakan logika sendiri, seolah ingin menciptakan kegelisahan publik terhadap institusi dayah, namun tidak menawarkan solusi yang bernas.
Ironisnya, tulisan ini muncul di tengah gelora kebangkitan kembali peran dayah di Aceh. Beberapa tokoh alumni dayah kini duduk di posisi strategis, baik di legislatif maupun eksekutif. Banyak pula yang menggerakkan sektor pendidikan dan ekonomi berbasis pesantren. Apakah itu tidak cukup menjadi bukti?
Jika penulis ingin menawarkan kritik konstruktif terhadap sistem pendidikan dayah, tentu akan lebih baik jika dimulai dengan data, dialog, dan pemahaman yang benar. Bukan malah menyudutkan secara insinuatif.
Lebih bijak lagi, jika tulisan seperti ini mampu membangkitkan motivasi dan semangat generasi muda untuk belajar di dayah, bukan malah meragukan masa depannya.
Sebagai guru dayah dan bagian dari keluarga besar alumni dayah, saya tidak anti terhadap kritik. Bahkan saya sangat terbuka terhadap evaluasi dan masukan untuk kemajuan institusi keilmuan kita.
Namun kritik yang baik seharusnya disampaikan dengan niat yang benar, metode yang sahih, dan narasi yang memuliakan ilmu, bukan justru menanamkan benih pesimisme terhadap lembaga yang telah menjadi pelita keilmuan umat selama berabad-abad.
Penulis opini haruslah bijak, berpengetahuan, dan bertanggung jawab. Jangan menulis hanya karena ingin menulis. Jangan memancing kontroversi hanya demi engagement. Apalagi dengan mengorbankan martabat ulama dan institusi warisan peradaban Islam seperti dayah.
Tulisan “Masih Adakah Ulama Alumni Dayah?” sebenarnya bisa menjadi sangat bagus jika ditulis dengan semangat memperkuat, bukan merendahkan. Sayangnya, tulisan tersebut justru mencerminkan kebingungan arah berpikir dan kegagalan memahami kedalaman makna ulama dalam tradisi keilmuan Islam.
Maka, jika kita bertanya “masih adakah ulama alumni dayah?”, barangkali lebih tepat kita balikkan: “masih adakah penulis yang bijak dan memahami nilai-nilai luhur keulamaan hari ini?”
*Guru Dayah dan Alumni Program Magister Hukum.

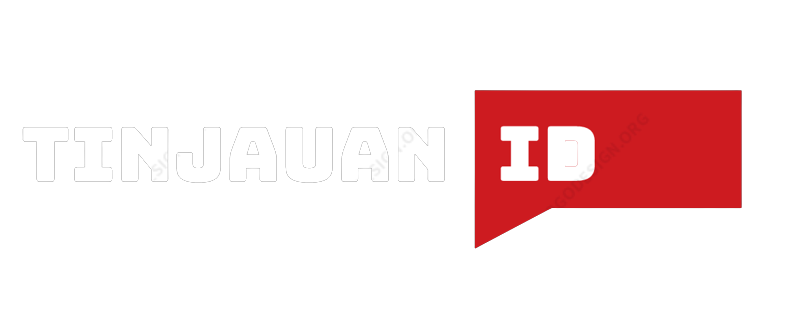














Discussion about this post