Bagi Antonio Gramsci, seseorang dianggap intelektual bukan karena kecerdasan akademis semata, intelektual lebih kepada fungsi dan peran menyuarakan kebenaran yang dijalankan dalam masyarakat. Di saat kampus mati suri, influencer mengambil alih peran intelektual kampus.
Oleh: Jabal Ali Husin Sab
Antonio Gramsci pernah mengatakan bahwa, setiap orang adalah intelektual, tetapi tidak semua menjalankan fungsi intelektual dalam masyarakat.
Perkataan Antonio Gramsci ini menyadarkan kita bahwa seseorang dianggap sebagai intelektual bukan karena kecerdasan akademis semata, intelektual lebih kepada fungsi dan peran seseorang yang ia jalankan dalam masyarakat.
Bagi Gramsci, penabalan gelar intelektual adalah sebuah peran dengan tanggung jawab. Intelektual memiliki tugas untuk menyuarakan aspirasi kelas yang tertindas dan membongkar hegemoni pemikiran yang mengekalkan ketidakadilan.
Menjadi cerdas, berilmu, terdidik, tidak lantas menjadikan seseorang intelektual. Kecerdasan dan posisi akademis tanpa dibarengi oleh keberanian untuk mengatakan yang benar di hadapan kekuasaan dan membela kaum lemah, belum layak disebut sebagai intelektual.
Dari apa yang dinyatakan Gramsci, intelektual lebih identik dengan sikap politik dalam struktur dan konfigurasi sosio-politik, ketimbang hanya sebatas otoritas akademik. Intelektual ibarat martir yang siap dihantam oleh palu godam penguasa tiran, demi mewakili suara sumbang rakyat banyak yang tak terdengar di lingkaran utama kekuasaan.
Sejak era modern, intelektual lazimnya lahir di universitas atau kampus, sebagaimana Simmone de Beauvoir dan Michael Foucault muncul dari Sorbonne Université di Prancis. Atau Theodor Adorno dan Jurgen Habermas yang lahir dari Goethe-Universität Frankfurt am Main di Jerman. Filsuf kenamaan Amerika Serikat semisal Noam Chomsky yang dikenal dengan kritik kerasnya atas hegemoni global Amerika Serikat juga dikenal sebagai professor di Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Di era reformasi, Amien Rais menjadi salah satu sosok intelektual utama — dari Universitas Gadjah Mada (UGM) — yang menjadi motor pergerakan menggulingkan rezim Orde Baru. Ia dikenal sebagai sosok berpendidikan, doktor ilmu politik lulusan AS yang orasinya berapi-api, mampu mengorganisir sebuah gerakan massa di momen krusial dalam peristiwa sejarah Indonesia kala itu.
Praktis di generasi berikutnya, hingga sekarang, sulit rasanya bagi kita menemukan akademisi yang benar-benar memainkan fungsi intelektual di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud Gramsci.
Kampus tak lagi menjadi ladang penghasil intelektual. Institusi pendidikan itu hanya menghasilkan pekerja terampil berpendidikan dan kalangan teknokrat yang — boleh dibilang — pragmatis dan lebih memilih melayani kekuasaan.
Kampus yang Dikontrol
Sebenarnya ada satu faktor utama yang membuat kampus di Indonesia gagal menjadi lahan subur bagi suburnya perkembangan kaum intelektual di masa ini, yakni otonomi kampus.
Kampus di Indonesia seolah dijalankan dengan kontrol kuat pemerintah. Kampus tidak menjadi lembaga pendidikan yang otonom, yang terpisah dari pemerintah, sebagaimana di beberapa negara.
Kampus negeri di Indonesia berada di bawah supervisi oleh seorang menteri. Meski kini universitas negeri berstatus badan hukum sendiri, bisa mengelola aset, usaha dan keuangan sendiri, namun kampus negeri belum sepenuhnya otonom. Bahkan pemilihan rektor masih cenderung bisa “diatur” oleh pemerintah, baik melalui regulasi, maupun operasi politik yang tidak resmi.
Sepertinya banyak pihak yang tidak bisa menafikan rahasia umum yang beredar bahwa diduga kuat ada upaya pelemahan kampus — yang menguat di masa pemerintahan sebelumnya — melalui semacam operasi yang bisa kita sebut “depolitisasi kampus”, meminjam istilah masa Orde Baru yang dilakukan oleh Daoed Joesoef untuk meredam pergerakan mahasiswa pasca peristiwa Malari tahun 1974.
“Gerakan mahasiswa dilemahkan, BEM digiring untuk tujuan politik pihak tertentu, mereka dibayar,” terang mantan pengurus di BEM salah satu universitas negeri yang saya ajak bicara. Pelemahan pergerakan politik di kampus memang terjadi, bukan hanya di kalangan gerakan mahasiswa, tapi juga ada dugaan kuat untuk “mendepolitisasi” para dosen melalui kontrol terhadap rektorat.
Lalu dengan melemahnya kampus, baik dengan ketiadaan kritik para akademisi, maupun gerakan mahasiswa yang mati suri, apakah kemudian tidak ada sama sekali yang mengambil peran sebagai intelektual untuk mengkritik penguasa dan menyuarakan keadilan?
Kelompok Intelektual Baru
Menariknya, fenomena baru di Indonesia telah menghadirkan sejumlah sosok yang bersuara di media sosial mengkritik pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Mereka tidak bisa dikatakan kaum terdidik yang paripurna — meski mereka juga bukan orang awam, kritik mereka menunjukkan bahwa mereka punya nalar intelektualitas yang memadai.
Tanpa membawa embel-embel akademis, mereka melontarkan kritik tajam dan konsisten mengamati dan menyuarakan aspirasi di platform media sosial. Mereka bisa disebut influencer, tapi dengan gaya, pendekatan, dan narasi politik yang sama sekali baru.
Ferry Irwandi dan Pandji Pragiwaksono adalah dua nama di antara sejumlah nama yang muncul.
Ferry punya pengetahuan dan analisis dari disiplin ilmu ekonomi yang memadai. Ia tak kalah dengan dosen atau ekonom konvensional.
Pandji yang tak dikenal sebagai ahli dalam disiplin ilmu tertentu, namun punya wawasan umum yang cukup luas dan kesadaran tentang liberalisme dan demokrasi yang cukup baik.
Jika Ferry mampu membahasakan penjelasan ekonomi dengan bahasa sehari-sehari yang apik, Pandji yang berlatar belakang komika, mampu mengkritik pemerintah lewat stand-up comedy dengan gaya bahasa satire yang menarik perhatian publik. Baru-baru ini acaranya yang bertajuk Mens-Rea viral dan menjadi bahan perbincangan publik.
Panggung gerakan mereka berdua adalah jagat digital. Mereka bisa menyuarakan aspirasi tanpa harus turun ke jalan — meski demikian Ferry Irwandi dan sejumlah publik figur ikut turun ke jalan di aksi demonstrasi Agustus lalu. Dengan kehadiran genre kelompok intelektual baru ini, platform media sosial di jagat maya menjadi ruang publik baru yang menjadi wadah diskursus disuarakan.
Jurgen Habermas menyebut bahwa ruang publik memainkan peranan penting dalam iklim demokrasi. Demokrasi dirawat melalui wacana diskursif yang dibincangkan dan diperdebatkan. Sosok semisal Ferry dan Pandji menjadi pemantik sekaligus patron baru dalam wacana politik diskursif di jagat maya.
Meski demikian, tak semua influencer punya kejernihan analisis dan punya argumen rasional yang tajam, sehingga layak disebut intelektual. Namun dengan kekosongan fungsi dan peran yang ditinggalkan intelektual kampus, merujuk apa yang dikatakan oleh Gramsci diatas, influencer sudah menjadi perwakilan dari kewajiban kolektif (fardhu kifaiyah) yang harusnya dilakukan oleh intelektual kampus.
Suka atau tidak suka, influencer adalah intelektual baru di era informasi sekarang ini.

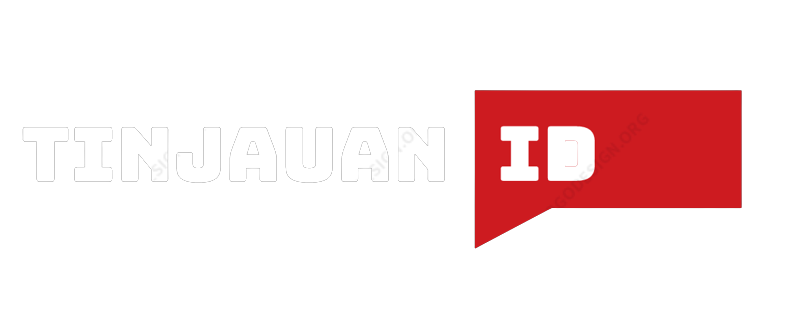














Discussion about this post