Reza Idria menegaskan bahwa cinta pada perdamaian Aceh saja tidak cukup, harus ada rasionalitas, data, dan program nyata untuk menjaganya.
BANDA ACEH – Dua puluh tahun lalu, tepat 15 Agustus 2005, dunia menyaksikan lahirnya MoU Helsinki yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh. Sejak itu, dentum senjata berganti riuh pasar, aroma darah digantikan wangi kopi di warung-warung.
Bagi Dr. Reza Idria, Direktur International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), capaian ini adalah sesuatu yang luar biasa.
“Pertama sekali kita wajib bersyukur,” ujarnya membuka percakapan.
“Perjanjian damai Aceh ini sudah berusia 20 tahun sesuatu yang jarang terjadi di dunia. Banyak negara lain gagal menjaga perdamaian selama itu,” ungkapnya.
Bagi Reza, perdamaian adalah pintu menuju pemulihan. Tanpanya, Aceh tak mungkin membicarakan pembangunan ekonomi atau kesejahteraan. Namun rasa syukur itu, katanya, harus dibarengi refleksi.
“Kita harus jujur. Angka kemiskinan Aceh masih tinggi. Keistimewaan yang kita miliki belum dipahami secara inklusif. Banyak yang hanya hafal kata ‘khusus’ dan ‘istimewa’, tapi tidak tahu apa substansinya,” tuturnya.
Ia menyoroti bahwa pengetahuan soal status istimewa Aceh sering kali hanya dimiliki kalangan pakar hukum, sementara masyarakat luas termasuk generasi muda tidak benar-benar memahaminya.
Tata Kelola dan Kepedulian Publik
Reza menilai lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi salah satu akar masalah stagnasi pembangunan. Meski dana khusus terus mengalir, perbaikan signifikan di bidang kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan belum terlihat.
“Ada masalah akuntabilitas, transparansi, dan prioritas penggunaan anggaran serta rasa kepemilikan publik. Publik kita jarang mengawal dana itu. Mereka baru ribut kalau tidak kebagian proyek, tapi jarang bertanya apakah penggunaannya benar,” katanya, memberi perbandingan dengan negara-negara seperti Amerika, Singapura, atau Belanda, di mana dana publik menjadi perhatian serius warga.
Rasa Percaya yang Rapuh
Bagi Reza, perdamaian ibarat hubungan rumah tangga yang terikat secara formal, tapi rapuh jika rasa percaya hilang.
“Rasa percaya itu fragile (mudah pecah). Dan cara paling aman menjaganya adalah lewat kesejahteraan. Masalah ekonomi bisa memicu keretakan, sama seperti dalam hubungan pribadi,” jelasnya.
Reza Idria menegaskan bahwa cinta pada perdamaian Aceh saja tidak cukup, harus ada rasionalitas, data, dan program nyata untuk menjaganya.
Tantangan Pasca Dana Otsus
Salah satu kekhawatiran terbesarnya adalah masa depan Aceh setelah berakhirnya dana Otonomi Khusus. Tanpa strategi keluar yang jelas, ketiadaan dana itu bisa memicu masalah baru yang mengancam perdamaian.
“Dengan sisa modal yang kita punya, pemerintah harus serius memperbaiki tata kelola dan membangun kembali rasa percaya masyarakat,” ujarnya.
Reza menaruh harapan pada anak muda yang tak mengalami langsung konflik, tetapi bisa memaknainya lewat pendidikan. Ia mendorong lahirnya kurikulum perdamaian di sekolah dan kampus sesuatu yang sudah dibicarakan sejak 10 tahun lalu, namun tak kunjung terealisasi.
“Sekarang giliran generasi muda yang mendesak itu,” tegasnya.
Buah dari Perdamaian
Meski tantangan masih banyak, Reza mengakui ada capaian penting selama dua dekade ini. Aceh memiliki lembaga-lembaga istimewa seperti Baitul Mal dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), memiliki himne daerah, bahkan aturan-aturan lokal yang tak dimiliki provinsi lain.
“Itu semua buah dari perdamaian,” katanya.
Reza mengakhiri percakapan dengan pesan sederhana namun mendalam.
“Perdamaian bukan sekadar tidak ada perang. Ia adalah tentang bagaimana kita membangun masa depan bersama dengan rasa percaya, kesejahteraan, dan kepedulian publik yang nyata,” tutupnya.

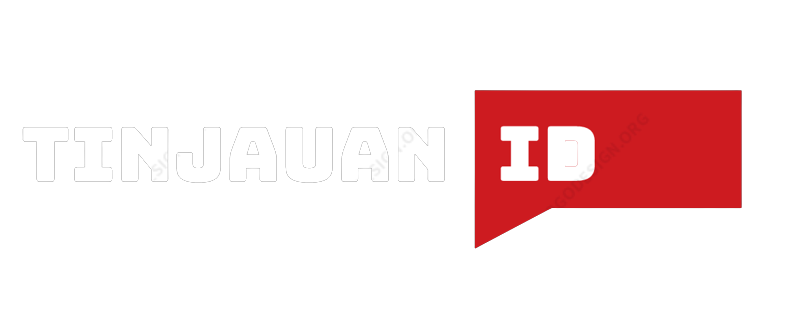














Discussion about this post