Bahkan acara konten bertema agama pun sering lebih menonjolkan citra dan hiburan daripada kedalaman pesan spiritual.
Di zaman sekarang, batas antara agama dan gaya hidup makin sulit dibedakan. Dahulu, agama adalah sesuatu yang suci, mendalam, dan penuh makna batin. Sementara gaya hidup identik dengan hal-hal duniawi, kesenangan, dan tampilan luar. Tapi kini keduanya sering bertemu di satu titik: ruang publik.
Agama bukan lagi sekadar praktik spiritual, melainkan juga bagian dari cara seseorang menampilkan diri di hadapan dunia. Dari pakaian, gaya busana, retorika personal, simbol, sampai kebiasaan sehari-hari—semuanya bisa menjadi ekspresi “beragama” sekaligus “bergaya”.
Namun di balik itu, muncul paradoks yang menarik. Agama yang sejatinya mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman batin, kini kerap hadir dalam bentuk yang serba visual, konsumtif, dan trendi.
Spiritualitas menjadi konten, ibadah jadi ajang eksistensi. Kita bisa melihatnya di mana-mana: unggahan vidio, doa harian di media sosial, video kajian dengan pencahayaan sinematik, hingga ritual keagamaan yang dikemas seperti acara hiburan. Tak salah memang, tapi ketika semua hal suci mulai dikurung dalam logika citra, kedalaman makna perlahan memudar, tergantikan oleh keindahan tampilan.
Fenomena ini disebut sebagai imajinasi materialis atau dengan sederhananya disebut sebagai cara beragama yang lebih menonjolkan bentuk luar dibanding isi spiritual.
Ritual-ritual yang dulu bermakna penyucian jiwa kini lebih sering menjadi ruang pencitraan diri. Puasa, doa, berkabung, bahkan ziarah bisa berubah menjadi simbol status, ajang gengsi, atau bukti kesalehan yang harus terlihat. Kita hidup di era hiper-ritualitas, di mana tanda-tanda religius diproduksi, disebar, dan dikonsumsi seperti barang dagangan. Agama perlahan menjadi bagian dari industri budaya; dijual dalam bentuk yang indah, tapi sering kehilangan ruhnya.
Contohnya bisa kita lihat di sekitar kita. Paket umrah “eksekutif”, busana muslim premium, atau acara buka puasa di hotel berbintang, arisan hedon dibalud dengan busana agamis, kelompok ibadah yang bermewah-mewah, semua dikemas dengan narasi religius namun sarat unsur komersial.
Bahkan acara konten bertema agama pun sering lebih menonjolkan citra dan hiburan daripada kedalaman pesan spiritual.
Orang bisa memilih “gaya beragama” seperti memilih merek fashion—ada versi elegan, sederhana, atau mewah, tergantung selera dan kelas sosial. Akibatnya, makna ibadah bergeser dari ruang batin menuju ruang citra, dari pengalaman spiritual menuju tontonan sosial.
Pada akhirnya, esai ini ingin mengingatkan bahwa agama dan gaya hidup memang tak bisa sepenuhnya dipisahkan. Namun, ketika agama terjebak dalam pusaran konsumsi dan pencitraan, yang hilang adalah jantungnya sendiri: ketulusan, refleksi, dan keheningan.
Di tengah dunia yang serba visual dan cepat ini, mungkin tugas kita bukan menolak perubahan, tapi menjaga agar makna spiritual tetap hidup di balik segala kemasan dan tren yang membungkusnya. Karena sejatinya, agama bukan tentang bagaimana kita tampak—melainkan tentang bagaimana kita mengenal dan memperbaiki diri di hadapan yang Maha Melihat.
Oleh: Mulyadi, pemerhati sosial keagamaan.

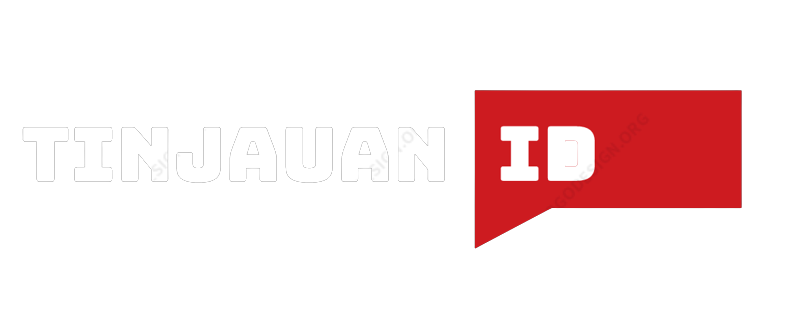














Discussion about this post