Pesantren bukanlah benteng feodalisme, melainkan laboratorium spiritual dan moral yang telah menjadi pilar pendidikan keindonesiaan selama berabad-abad.
Oleh: Tgk. Abdul Muhaimin*
Beberapa waktu lalu, sebuah narasi di media nasional menyoroti tradisi di pondok pesantren dengan lensa yang problematis. Adegan santri yang mencium tangan kiai, duduk bersimpuh, dan ketaatan yang mendalam, diinterpretasikan sebagai “budaya tunduk” yang identik dengan sistem feodalisme.
Tuduhan ini, yang menyamakan relasi suci antara guru dan murid dengan hubungan tuan dan hamba, adalah sebuah kekeliruan fatal yang gagal membaca ruh sejati dunia pesantren.
Pesantren bukanlah benteng feodalisme, melainkan laboratorium spiritual dan moral yang telah menjadi pilar pendidikan keindonesiaan selama berabad-abad. Untuk memahami relasi antara kiai dan santri, kita harus keluar dari kacamata sekuler-rasionalistik modern dan menyelami konsep agung yang menjadi pondasi pesantren: Adab dan Barokah.
1. Adab di Atas Ilmu: Bukan Kepatuhan Buta, melainkan Resepsi Spiritual
Inti dari pendidikan pesantren adalah ajaran “Al-adabu fauqal ‘ilm” (Adab di atas ilmu). Ketaatan dan penghormatan santri kepada kiai bukanlah bentuk kepatuhan buta seperti dalam sistem feodal yang ditentukan oleh garis keturunan atau kelas sosial. Sebaliknya, ia adalah etika keilmuan (ta’dhim)—sebuah pra-syarat spiritual untuk mendapatkan keberkahan ilmu.
Dalam pandangan ulama klasik seperti Syekh al-Zarnuji, ilmu adalah cahaya (nur). Hati yang dipenuhi kesombongan intelektual dan ketidak-hormatan tidak akan mampu menampung cahaya itu. Oleh karena itu, kiai ditempatkan bukan hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai pewaris nabi (waratsatul anbiya’), pembimbing moral, dan teladan hidup.
Gestur mencium tangan, menunduk, dan melayani kiai adalah simbol. Simbol dari kerendahan hati seorang pencari ilmu di hadapan sumber ilmu. Ini adalah upaya membersihkan batin dari arogansi, bukan paksaan untuk meniadakan daya kritis.
2. Memutus Rantai Feodalisme, Membangun Kesetaraan Ilmu
Secara definitif, feodalisme adalah sistem politik-sosial yang berbasis pada kepemilikan tanah, di mana status sosial seseorang ditentukan sejak lahir dan hampir mustahil diubah.
Pesantren sama sekali tidak mencerminkan hal tersebut:
Mobilitas Sosial Terbuka: Pesantren adalah salah satu institusi paling egaliter di Indonesia. Anak petani bisa menjadi kiai besar, dan anak kiai bisa menjadi santri biasa. Yang menentukan status di pesantren adalah kedalaman ilmu dan kemuliaan adab, bukan garis keturunan atau kekayaan materi.
Kepemimpinan Berbasis Kharisma dan Ilmu: Otoritas kiai bukan warisan paksa, melainkan otoritas kharismatik yang didasarkan pada pengakuan kolektif atas kedalaman spiritual dan keilmuan mereka. Jika seorang kiai kehilangan keduanya, ia akan kehilangan pengaruh di mata santri dan masyarakat.
Pengabdian sebagai Pendidikan Karakter: Beberapa praktik seperti membantu kiai (khidmah) sering disalahartikan sebagai kerja rodi. Padahal, bagi santri, khidmah adalah bagian dari kurikulum non-formal yang mendidik kemandirian, gotong royong, keikhlasan, dan menanggalkan ego. Banyak tokoh besar lahir dari tradisi khidmah ini.
3. Kritis yang Beradab: Pesantren Bukan Pengekang Akal
Tuduhan bahwa ketaatan di pesantren menghilangkan daya kritis juga tidak berdasar. Justru, pesantren mendidik santri untuk berpikir kritis secara metodologis dengan menguasai kitab-kitab kuning yang berisi beragam perbedaan pendapat (khilafiyah) dan perdebatan mendalam.
Kritis di pesantren tidak berarti harus memberontak atau tidak sopan. Ia berarti kritis yang beradab—kemampuan untuk memahami esensi ilmu, bukan sekadar menolak karena didorong oleh ego.
Kesimpulan: Mengembalikan Narasi Positif
Ketika media modern menyoroti pesantren, mereka harus berhati-hati agar tidak menyelewengkan nilai-nilai luhur dengan terminologi yang salah kaprah. Menyandingkan adab santri dengan feodalisme adalah bukti ketidakpahaman mendalam terhadap tradisi keilmuan Islam.
Pesantren adalah sekolah kehidupan yang mencetak pemimpin-pemimpin bangsa, aktivis sosial, dan ulama yang berpegang teguh pada moralitas. Mereka dididik untuk memiliki ilmu yang tinggi dan adab yang mulia. Dunia pesantren layak dibela, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia adalah mata air kearifan lokal yang telah membuktikan diri sebagai benteng penjaga karakter bangsa di tengah gempuran modernitas.
Kritik terhadap pesantren haruslah proporsional, berdasarkan fakta, dan yang paling penting, mengakui substansi adab yang menjadi pembeda utamanya dari feodalisme yang menindas. Pesantren tidak menciptakan hamba, melainkan melahirkan manusia berilmu yang mampu memimpin dengan hati yang bersih.
*Dosen Universitas Islam Al-Aziziyah (UNISAI Samalanga).

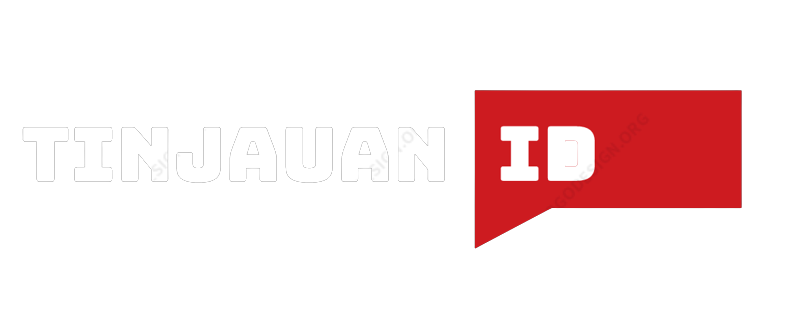














Discussion about this post