Menteri Negara Urusan Pangan Ibrahim Hasan menyatakan bahwa mulai tahun 1994, Bulog mencanangkan untuk mengekspor beras guna merangsang pendapatan petani. Aceh dipilih sebagai salah satu daerah pilar untuk rencana ini. Mengapa rencana ini gagal?
Pada pemberitaan Majalah Tempo, Sabtu, 1 Januari 1994, Menteri Negara Urusan Pangan yang juga merangkap Kepala Bulog Ibrahim Hasan mencanangkan bahwa Aceh akan mengekspor beras sebesar 500.000 ton ke Malaysia.
“Malaysia berminat membeli beras Aceh, minimal 500.000 ton per tahun,” ujarnya, seperti dikutip Antara.
Ibrahim Hasan menyatakan bahwa mulai tahun 1994, Bulog mencanangkan untuk mengekspor beras guna merangsang pendapatan petani. Aceh dipilih sebagai salah satu daerah pilar untuk rencana ini karena memiliki surplus produksi yang stabil pada masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Aceh sebelumnya (1986–1993).
Menteri Ibrahim Hasan mengaku bahwa Malaysia sudah berkali-kali meminta beras Aceh, khususnya beras pulut hitam, tetapi baru sekitar 100 kg yang dikirim sebagai contoh.
Produksi beras Aceh pada musim panen tahun 1992 dan 1993 tercatat sekitar 90.000 ton per tahun. Sedangkan kebutuhan beras untuk pegawai negeri dan sipil di Aceh rata-rata 46.000 ton per tahun. Ini berarti ada kelebihan atau surplus beras sebesar 44.000 ton per tahun.
Menurut kepala Depot Logistik (Dolog) Aceh Teuku Muhiddtudin, surplus gabah ini terjadi karena lahan sawah di Aceh semakin luas dan kesadaran petani untuk meningkatkan mutu panen mereka bertambah.
Gambaran Produksi Beras Indonesia
Tahun 1992, Indonesia melakukan impor beras. Pada tahun ini, produksi domestik mengalami sedikit penurunan sementara kebutuhan konsumsi terus meningkat, sehingga pemerintah (melalui BULOG) mendatangkan beras dari luar negeri untuk menjaga cadangan nasional.
Di tahun 1993, ini adalah tahun yang cukup unik. Beberapa sumber mencatat bahwa pada tahun 1993 Indonesia nyaris tidak mengimpor beras atau jumlahnya sangat kecil karena produksi dalam negeri sedang meningkat hingga melebihi kebutuhan pasar saat itu.
Sementara di tahun 1994, Indonesia kembali melakukan impor beras dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan oleh fenomena El Nino yang memicu kekeringan panjang, sehingga produksi padi nasional merosot tajam. Impor dilakukan untuk menstabilkan harga dan mengamankan stok pangan nasional.
Secara domestik, tahun 1994 adalah salah satu tahun dengan kekeringan terburuk dalam sejarah Indonesia akibat fenomena El Nino.
Kondisi di lapangan, produksi padi nasional anjlok drastis karena kegagalan panen di berbagai lumbung padi.
Karena stok di gudang BULOG menipis sementara konsumsi warga tetap tinggi, pemerintah tidak punya pilihan lain selain impor untuk mencegah kelaparan dan gejolak harga (inflasi). Pada tahun 1994, Indonesia mengimpor sekitar 600.000 hingga 1 juta ton beras untuk menambal kekurangan tersebut.
Tahun 1994 adalah titik balik yang sangat krusial bagi kedaulatan pangan Indonesia. Pada tahun inilah Indonesia secara resmi terjebak dalam dilema antara kondisi alam yang buruk dan tekanan hukum internasional.
Tata Kelola Perdagangan Beras dan Regulasi Internasional
Selama sepuluh tahun belakangan (dari 1994), Indonesia mengimpor 1,262 juta ton beras, sedangkan ekspor beras Indonesia di periode itu berjumlah 1,489 juta ton, masih surplus 227 ribu ton. Pada periode yang sama (jangka waktu sepuluh tahun), produksi beras dalam negeri telah naik dari 6 juta ton menjadi 31 juta ton pada tahun 1993.
Di masa itu, Indonesia juga mengimpor 140 ribu ton gula dan 426 ribu ton kedelai. Indonesia juga mengimpor 100 persen gandum.
Pada tahun 1994, Indonesia mengesahkan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dengan menandatangani ini, Indonesia resmi terikat pada Agreement on Agriculture (AoA).
Akibatnya, Indonesia tidak boleh lagi menutup pasar beras secara absolut. Jika sebelumnya pemerintah bisa melarang impor demi melindungi petani, aturan WTO mewajibkan Indonesia mengubah larangan tersebut menjadi tarif (bea masuk) dan memberikan akses pasar bagi beras asing.
Dampaknya, kebijakan swasembada yang sangat proteksionis ala Orde Baru mulai dicegah secara hukum internasional sejak tahun ini.
Salah satu aturan WTO yang mulai menghantui di tahun 1994 adalah prinsip Minimum Access Opportunity. Berdasarkan aturan ini, negara berkembang pengimpor beras, termasuk Indonesia, harus berkomitmen untuk membuka peluang impor setidaknya 3 persen dari konsumsi domestik.
Meskipun pada tahun 1994 alasan utamanya adalah kekurangan stok, namun aturan WTO memastikan bahwa jalur masuk beras asing tetap terbuka secara legal dan tidak boleh dihambat oleh birokrasi yang dianggap mendistorsi perdagangan bebas ala WTO.
Seperti diberitakan Majalah Tempo 1 Januari 1994, Indonesia sebagai negara penandatangan GATT (Perjanjian Internasional tentang Tarif dan Perdagangan) masuk dalam Uruguay Round membahas skema perdagangan internasional. Salah satu poin yang diperdebatkan adalah setiap negara harus melakukan impor minimal 3 persen dari total konsumsinya. Secara bertahap, jumlah ini harus dinaikkan hingga 5 persen.
Jika hal ini disetujui, tentu akan memberatkan Indonesia. Karena jumlah 3 persen dari konsumsi beras total Indonesia yang sejumlah 25 juta ton berarti berada di angka 750 ribu ton. Ini berarti, Indonesia harus menyediakan cadangan devisa lebih dari 100 juta dollar AS untuk impor beras.
Untunglah usul itu dibendung, Indonesia terbebas dari keharusan mengimpor sebesar 3 persen dari total jumlah konsumsi beras.
Meski begitu, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 AoA, setiap negara anggota dilarang menggunakan hambatan non-tarif untuk melindungi produk pertaniannya.
Negara tidak boleh lagi melarang impor secara mutlak melalui kuota, lisensi impor yang membatasi, atau monopoli negara yang tertutup.
Dampaknya bagi Indonesia, sebelum 1994, Indonesia bisa menutup keran impor rapat-rapat jika merasa stok nasional cukup. Setelah meratifikasi GATT 1994, semua hambatan tersebut harus diubah menjadi Tarif (Bea Masuk). Artinya, Indonesia tidak boleh melarang beras luar negeri masuk. Indonesia hanya boleh mengenakan pajak/bea terhadap beras tersebut.
Kebijakan lain, Indonesia harus menetapkan batas atas bea masuk (tarif) untuk beras dan tidak boleh menaikkannya sesuka hati di atas batas yang telah disepakati (Bound Tariff).
Dampaknya, hal ini membuat pemerintah kesulitan menggunakan instrumen pajak tinggi untuk menghalangi masuknya beras impor yang harganya jauh lebih murah (seperti dari Vietnam atau Thailand), sehingga beras luar negeri lebih mudah membanjiri pasar lokal.
Realita Tahun 1994: Gagal Ekspor
Meskipun direncanakan untuk ekspor di awal tahun, kenyataannya pada tahun 1994 Indonesia justru mengalami krisis beras nasional. Penyebabnya, fenomena El Nino yang sangat kuat menyebabkan kekeringan panjang di seluruh Indonesia, termasuk daerah lumbung pangan.
Hasilnya, Indonesia alih-alih mengekspor, termasuk stok dari Aceh yang seharusnya diekspor, harus ditarik untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah bahkan terpaksa mengimpor beras dalam jumlah besar, sekitar 600 ribu hingga 1 juta ton, untuk menutupi defisit produksi akibat gagal panen nasional.
Pada tahun 1995 dan 1996, rencana ekspor beras secara masif dari Aceh juga tidak terwujud secara signifikan sebagai komoditas ekspor luar negeri. Fokus pemerintah saat itu beralih sepenuhnya untuk memulihkan stok nasional pasca-kekeringan 1994.
Selain itu, tekanan dari perjanjian WTO (GATT) yang diratifikasi tahun 1994 membuat pasar Indonesia lebih terbuka bagi beras impor yang harganya jauh lebih murah, sehingga beras lokal, termasuk beras dari Aceh, sulit bersaing di pasar internasional.
Secara administratif dan politis, Aceh siap mengekspor beras sesuai pernyataan Ibrahim Hasan di awal 1994. Namun faktanya, ekspor tersebut tidak terjadi karena faktor alam akibat kekeringan hebat El Nino 1994 yang memaksa stok beras Aceh digunakan untuk konsumsi dalam negeri.
Hal lain juga disebabkan oleh kebijakan global. Ratifikasi WTO pada tahun yang sama, yakni tahun 1994, mengubah peta perdagangan beras Indonesia dari semangat ekspor menjadi ketergantungan pada impor.
Oleh: Jabal Sab

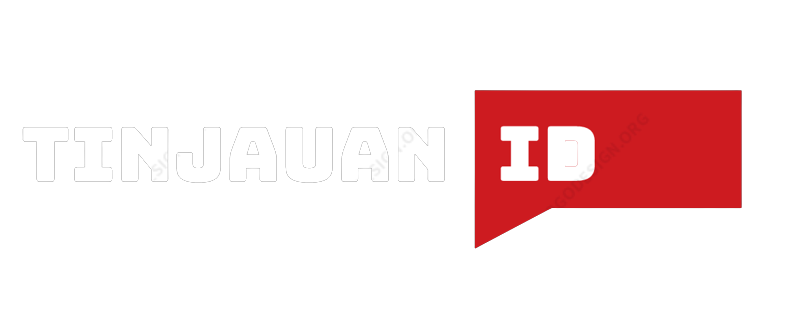














Discussion about this post