Sebagian generasi muda mulai menjauh dari agama bukan karena menolak ajarannya, tetapi karena merasa terlukai oleh cara penyampaiannya.
Oleh: Darwis Situmorang*
Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial kita dipenuhi cerita anak muda yang merasa “religious burn-out” atau mengalami apa yang disebut “religious trauma.” Istilah ini biasanya merujuk pada pengalaman negatif saat berinteraksi dengan ajaran agama yang disampaikan secara keras, penuh tekanan, atau menakutkan.
Banyak yang bercerita bagaimana kewajiban ibadah justru menimbulkan kecemasan, bukan kedamaian. Fenomena ini menunjukkan realitas sosial bahwa sebagian generasi muda mulai menjauh dari agama bukan karena menolak ajarannya, tetapi karena merasa terlukai oleh cara penyampaiannya. Padahal, jika kita melihat hakikat agama, semestinya yang muncul adalah rasa damai, bukan rasa takut yang melukai.
Agama pada esensinya hadir untuk menenangkan hati dan memberi arah hidup. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman: “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 28).
Di dalam Tafsir Al-Maraghi memberi gambaran bahwasanya ayat ini menunjukkan sifat iman yang sesungguhnya: keimanan yang melahirkan ketenangan, bukan kerisauan. Artinya, jika praktik keagamaan justru membuat seseorang cemas dan tertekan, ada yang keliru dalam pemahaman atau pendekatannya. Ayat ini menjadi pengingat bahwa orientasi agama adalah ketenteraman batin, bukan sekadar formalitas atau ancaman hukuman.
Sayangnya, cara kita memahami dan mensyiarkan agama sering jauh dari semangat ini. Salah satu penyebabnya adalah pola dakwah yang lebih menekankan hukuman daripada kasih sayang.
Dalam banyak kesempatan, neraka dan dosa besar lebih sering disinggung ketimbang rahmat Allah dan peluang taubat. Padahal Al-Qur’an sendiri membuka setiap surat (kecuali at-Taubah) dengan “Bismillahirrahmanirrahim”. Hal ini menandakan bahwa kasih sayang Allah adalah pintu pertama. Ketika pendekatan dakwah yang dominan dengan ancaman dan ketakutan, wajar bila yang tumbuh bukanlah rasa cinta kepada Allah, melainkan rasa cemas dan tertekan.
Faktor lain adalah rendahnya literasi agama. Banyak orang berhenti pada level simbolik, hanya tahu hukum lahiriah tanpa memahami alasan dan tujuan di balik itu.
Padahal, tanpa pengetahuan yang memadai, praktik agama mudah terjebak pada formalitas kaku. Sebagian pengajar pun belum membekali diri dengan pendekatan psikologis sehingga pesan agama disampaikan secara otoriter. Akibatnya, agama dipersepsi sebagai beban, bukan anugerah.
Untuk mengatasi persoalan ini, tidak cukup hanya mengganti cara ceramah atau materi dakwah; kita perlu memulai sejak dari pendidikan agama sejak dini. Anak-anak sebaiknya tidak hanya diajari apa yang wajib atau haram, tapi juga diberikan pemahaman tentang mengapa aturan itu ada. Dengan begitu, mereka memahami nilai dan tujuan di balik ajaran, bukan hanya takut melanggar.
Guru agama, dai, dan orang tua juga perlu dilatih cara berbicara yang empatik dan memahami psikologi anak, agar ajaran bisa disampaikan dengan bahasa yang menenangkan.
Selain itu, masyarakat perlu lebih mudah mendapatkan penjelasan Al-Qur’an yang menekankan rahmat dan tujuan syariat, agar agama dipahami sebagai sistem nilai yang hidup, bukan sekadar aturan kaku.
Langkah lain yang tidak kalah penting adalah menciptakan lingkungan yang mendukung keberagamaan yang sehat. masjid, kampus, dan media sosial perlu menyediakan ruang diskusi yang aman bagi anak muda untuk bertanya dan berdialog tanpa stigma.
Nilai-nilai spiritual juga perlu dimasukkan ke berbagai aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan, supaya agama tidak cuma dilihat sebagai kewajiban ritual, tapi menjadi sumber inspirasi moral dan spiritual yang menyeluruh.
Jika langkah-langkah ini dilakukan oleh keluarga, lembaga pendidikan, pendakwah, media, dan negara, kita tidak hanya mengobati gejala, tetapi juga menghapus akar kecemasan dalam keberagamaan.
Pada akhirnya, agama bukan sumber kecemasan. Ia adalah panduan hidup yang membebaskan manusia dari kebingungan, memberikan arah dan kedamaian. Jika kita merasa sebaliknya, mungkin cara kita memahaminya yang perlu diperbaiki.
Saatnya semua pihak berbenah: para pengajar memperbaiki metode, masyarakat meningkatkan literasi, dan individu merefleksi ulang motivasi keberagamaannya. Dengan begitu, kita bisa kembali menemukan wajah asli agama; sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan sumber kecemasan. Dan di situlah letak keindahan agama—bukan pada ketakutannya, tetapi pada kedamaian yang ia tawarkan.
*Penulis adalah pegiat dakwah.

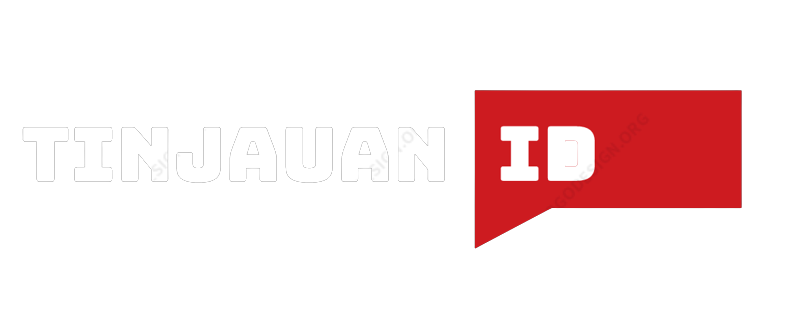














Discussion about this post