Fenomena ini dikenal sebagai cancel culture—budaya pembatalan yang kini menjadi senjata sosial generasi digital.
Oleh: Fatwa Nirwana*
Era digital mengubah wajah keadilan. Jika dulu koreksi sosial dilakukan melalui hukum atau media massa yang melewati proses verifikasi, kini penghakiman bisa terjadi dalam hitungan menit di kolom komentar.
Satu unggahan, satu potongan video, atau satu tagar viral sudah cukup menghancurkan reputasi—tanpa ruang klarifikasi, tanpa proses yang adil. Fenomena ini dikenal sebagai cancel culture—budaya pembatalan yang kini menjadi senjata sosial generasi digital.
Generasi Z, yang lahir dan tumbuh dalam ekosistem internet, berada di garis depan budaya ini. Mereka berani menyuarakan nilai-nilai keadilan, tapi keberanian itu kerap berubah menjadi inkuisisi moral digital.
Kesalahan masa lalu, opini tak populer, atau tindakan yang dinilai tidak etis langsung disambut pembatalan total. Tanpa proses, tanpa maaf, tanpa kesempatan belajar.
Sebagian orang memandang cancel culture sebagai bentuk keadilan sosial baru. Ia dianggap sebagai alat koreksi terhadap ketimpangan kekuasaan, terutama ketika hukum lamban atau tidak berpihak.
Dalam konteks ini, Generasi Z tampil sebagai watchdog moral: menyoroti, menekan, hingga menjatuhkan tokoh publik, selebriti, bahkan institusi.
Namun pertanyaan muncul: apakah netizen—dengan keterbatasan informasi, emosi sesaat, dan logika algoritma—bisa menjadi hakim moral yang adil? Bagaimana dengan asas praduga tak bersalah, hak membela diri, dan peluang memperbaiki kesalahan?
Dalam sistem hukum, seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti melalui proses yang sah. Dalam cancel culture, potongan informasi acak bisa jadi vonis, dan viralitas menjadi satu-satunya legitimasi. Ia menjelma sebagai “peradilan alternatif” tanpa akuntabilitas.
Penelitian Alvina Tanuwijaya Prasetyo, Viola Athaya Andriana, dan Jefri Audi Wempi dari LSPR Jakarta (2023) bahkan menemukan, cancel culture di Indonesia kini lebih sering dipicu oleh tren dan fear of missing out ketimbang etika yang matang.
Lebih jauh, budaya ini kerap dipakai untuk kepentingan politik, ekonomi, hingga personal. Netizen bukan hanya juri moral, tapi juga instrumen strategi.
Maka, persoalan utamanya bukan lagi soal benar atau salah, melainkan siapa yang mengendalikan narasi.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Pertama, bedakan kritik dan cancel. Kritik sehat dalam demokrasi. Cancel justru mematikan ruang belajar. Dan setiap penghukuman seharusnya berbasis bukti sah, konteks utuh, serta pertimbangan dampak sosial.
Kedua, Gen Z butuh literasi hukum dan etika digital. Cancel culture tak bisa menggantikan hukum. Justru, ia mengingatkan kita bahwa hukum harus terus diperbaiki agar adil dan responsif.
Ketiga, bangun budaya pemulihan. Banyak orang yang salah tak diberi kesempatan tumbuh. Padahal, keadilan restoratif mengajarkan bahwa tujuan keadilan bukan balas dendam, melainkan perbaikan hubungan dan transformasi. Cancel culture yang hanya menghukum justru menutup pintu ini.
Generasi Z perlu diajak bukan sekadar reaktif, tapi reflektif. Ketika empati, nalar, dan tanggung jawab berjalan bersama, cancel culture bisa berevolusi menjadi culture of accountability—budaya tanggung jawab yang adil dan membangun.
Sebab pada akhirnya, tidak semua yang bersalah adalah monster. Dan tidak semua suara Gen Z layak diremehkan. Keduanya butuh ruang, dipandu oleh etika dan hukum.
Jika kolom komentar terus jadi ruang peradilan tanpa hakim, jangan kaget bila suatu hari giliran Anda yang duduk di kursi pesakitan—bukan karena salah, tapi karena algoritma sedang bosan.[]
*Penulis adalah pengamat sosial.
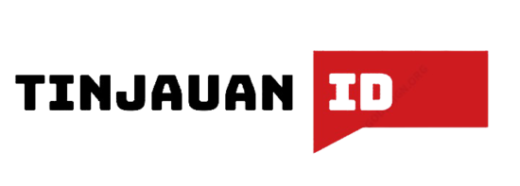
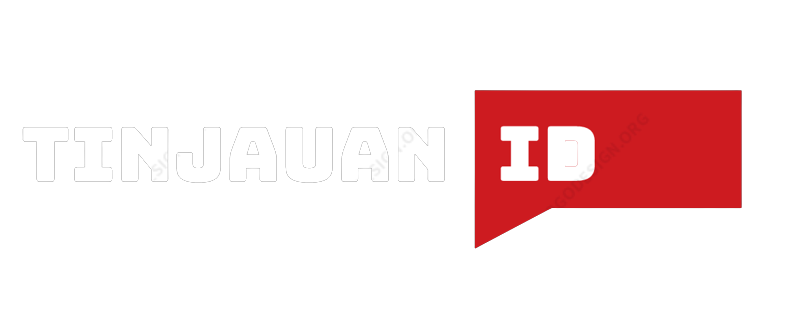

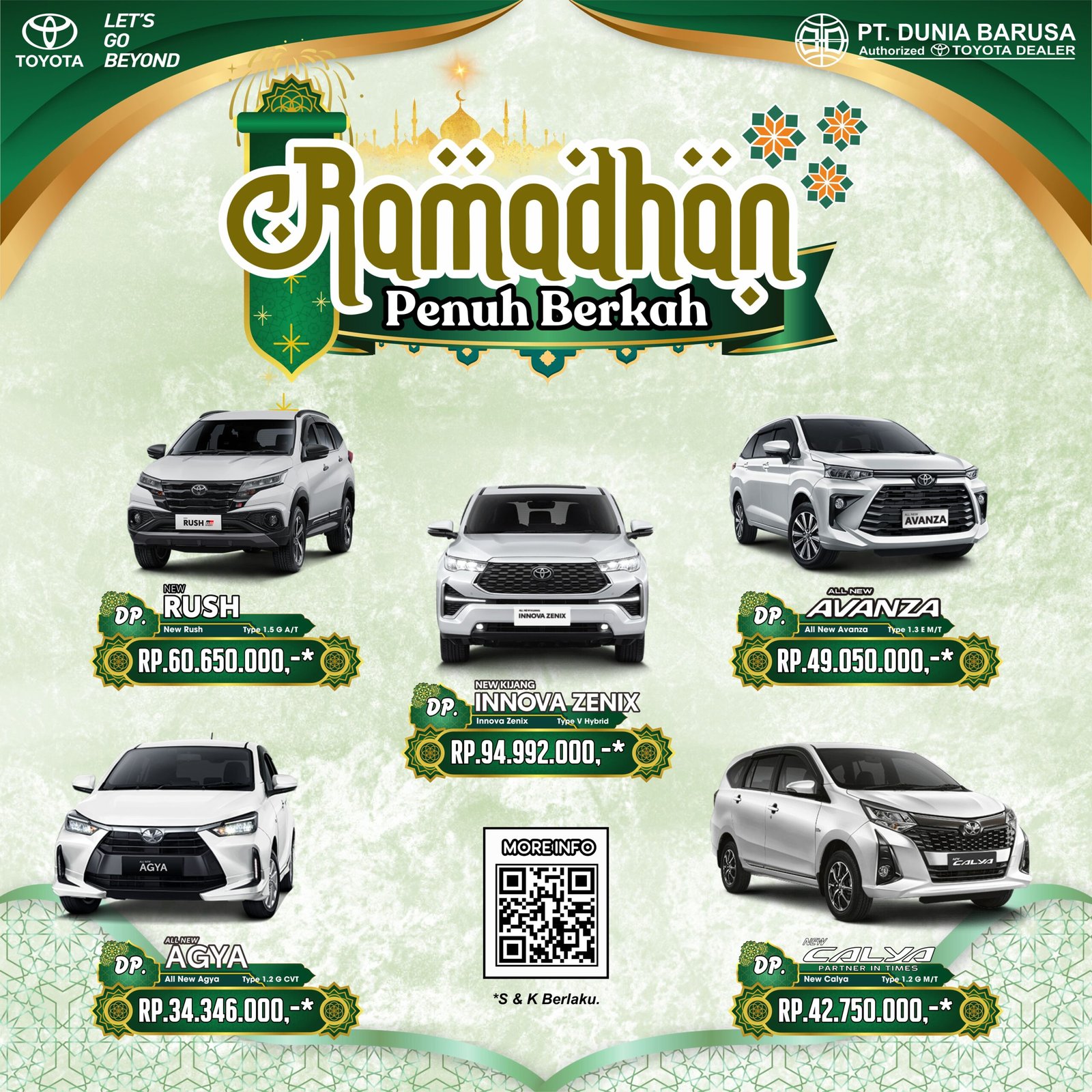












Discussion about this post