Ateisme modern bukan sekadar penolakan vulgar terhadap Tuhan, melainkan sebuah konfigurasi kompleks dari pengalaman historis, pergeseran epistemologis, dan perubahan cara manusia memahami dirinya sendiri. Ateisme perlu dibaca sebagai gejala intelektual dan kultural yang lahir dari perubahan lanskap makna dunia modern.
Oleh: Ahmad Ilham Zamzami, penulis adalah alumni Pondok Pesantren Sidogiri dan alumni Universitas Al-Azhar, Mesir.
TINJAUAN.ID – Tulisan ini merupakan bagian pembuka dari sebuah upaya membaca ateisme secara lebih jernih dan bertanggung jawab di tengah lanskap modern yang ditandai oleh pluralitas makna, krisis otoritas, dan perubahan cara manusia memahami dirinya sendiri.
Alih-alih memulai dari penilaian normatif—membenarkan atau menyalahkan—tulisan ini berangkat dari kebutuhan intelektual yang lebih mendasar. Dimulai dengan memetakan persoalan, memahami ragam wajah ateisme beserta akar historis dan filosofisnya, serta menelaah asumsi-asumsi yang bekerja di balik bahasa skeptisisme kontemporer.
Dengan demikian, ateisme tidak diperlakukan sebagai musuh iman yang harus segera disangkal, tetapi sebagai fenomena pemikiran yang perlu dibaca dengan ketelitian konseptual, agar diskursus tentang Tuhan, manusia, dan makna hidup tidak jatuh ke dalam simplifikasi, baik atas nama agama maupun rasionalitas modern.
Di ruang publik hari ini, ateisme sering hadir sebagai terma yang segera memicu reaksi emosional. Ia disangkal, dicurigai, bahkan dikutuk, sering kali tanpa terlebih dahulu dipahami.
Padahal, ateisme modern bukan sekadar penolakan vulgar terhadap Tuhan, melainkan sebuah konfigurasi kompleks dari pengalaman historis, pergeseran epistemologis, dan perubahan cara manusia memahami dirinya sendiri. Karena itu, ateisme tidak cukup dihadapi dengan bantahan apologetik semata, tetapi perlu dibaca sebagai gejala intelektual dan kultural yang lahir dari perubahan lanskap makna dunia modern.
Charles Taylor dalam A Secular Age menunjukkan bahwa modernitas tidak sekadar menghasilkan masyarakat yang kurang religius, melainkan membentuk kondisi di mana iman kepada Tuhan menjadi salah satu opsi di antara banyak kemungkinan makna hidup, bukan lagi horizon tak-terbayangkan (unthinkable) sebagaimana pada dunia pra-modern (Taylor, A Secular Age, 2007, 3–5).
Dalam kerangka ini, ateisme bukan anomali moral, tetapi konsekuensi logis dari sebuah dunia yang telah mengalami apa yang Taylor sebut sebagai the immanent frame, yakni bingkai pemaknaan yang mencukupkan penafsiran realitas hanya dari dalam dunia itu sendiri tanpa harus merujuk ke transendensi.
Di titik ini, memahami ateisme berarti memahami perubahan cara manusia bertanya. Jika pada dunia klasik pertanyaan utama adalah “bagaimana mengenal Tuhan dengan benar?”, maka di dunia modern pertanyaannya bergeser menjadi “apakah Tuhan masih diperlukan untuk menjelaskan makna hidup?”. Pergeseran ini bukan semata hasil kemajuan sains, tetapi buah dari transformasi filosofis yang lebih dalam, khususnya pergeseran pusat makna dari Tuhan ke manusia.
Jean-Paul Sartre, dalam Being and Nothingness, mengekspresikan bentuk ateisme eksistensial yang radikal dengan menyatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas (condemned to be free). Dalam paradigma Sartre, ketiadaan Tuhan bukanlah kekosongan metafisis yang perlu diisi, tetapi justru prasyarat bagi kebebasan manusia untuk menciptakan maknanya sendiri (Sartre, Being and Nothingness, 1957, 553–556).
Tuhan, dalam perspektif ini, dipandang sebagai ancaman terhadap otonomi eksistensial manusia. Maka ateisme Sartrean bukan sekadar negasi teologis, melainkan afirmasi antropologis bahwa manusia sebagai pusat makna.
Namun, reduksi ateisme pada satu wajah seperti Sartre kurang tepat. Sebab ateisme modern hadir dalam banyak varian, dengan latar motivasi dan horizon filosofis yang berbeda. Sebagian ateisme lahir dari skeptisisme epistemologis terhadap klaim metafisika, sebagian dari kritik moral terhadap institusi agama, dan sebagian lagi dari pencarian spiritual alternatif yang justru tetap mengakui kedalaman pengalaman makna tanpa Tuhan personal.
Don Cupitt, misalnya, dalam After God, tidak merayakan kematian Tuhan sebagai kemenangan rasionalitas yang kaku, melainkan sebagai transformasi bahasa iman. Cupitt berargumen bahwa Tuhan metafisis telah mati dalam kesadaran modern, tetapi nilai-nilai religius—makna, komitmen, kedalaman eksistensial—masih dapat hidup dalam bentuk non-realistis (Cupitt, After God, 1997, 1–12). Di sini, ateisme tidak identik dengan nihilisme, melainkan dengan upaya reconfiguration of meaning setelah runtuhnya metafisika klasik.
Varian inilah yang kemudian berkembang menjadi apa yang disebut sebagai spiritual atheism. Armand J. Boehme mencatat bahwa banyak ateis kontemporer tidak lagi puas dengan sekadar penolakan terhadap Tuhan, tetapi membangun praktik, etika, bahkan bentuk-bentuk spiritualitas non-teistik (Boehme, The Spirituality of Atheism, 2017, 106–110).
Fenomena ini menantang asumsi lama bahwa ateisme selalu berujung pada kekosongan makna. Justru, dalam beberapa kasus, ia melahirkan agama tanpa Tuhan atau iman tanpa transendensi.
Eric Steinhart dalam Believing in Dawkins bahkan mengembangkan ateisme spiritual berbasis naturalisme kosmik. Ia menafsirkan sains modern—evolusi, kompleksitas kosmos, hukum alam—sebagai sumber pengalaman awe dan nilai, yang sebelumnya hanya diasosiasikan dengan agama (Steinhart, Believing in Dawkins, 2020, 6–10). Tuhan digantikan oleh kosmos itu sendiri yang diyakini sebagai objek kontemplasi dan komitmen etis. Dalam horizon ini, ateisme bukan lawan spiritualitas, tetapi saingannya.
Namun, di balik keragaman ini, ada satu benang merah yang menyatukan hampir seluruh varian ateisme modern, yakni pergeseran pusat makna dari Tuhan ke manusia atau dunia.
Dalam ateisme modern, dunia tidak lagi dipahami sebagai tanda menuju Yang Transenden, melainkan sebagai realitas final yang harus cukup menjelaskan dirinya sendiri. Inilah yang oleh sebagian pemikir disebut sebagai immanentization of meaning.
Di sinilah problem filosofis ateisme muncul secara tajam. Ketika makna sepenuhnya diimankan kepada dunia dan manusia, pertanyaan ontologis tentang “mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan?” sering kali dianggap tidak relevan atau tidak produktif.
Bertrand Russell merumuskan sikap ini secara terkenal dengan pernyataannya bahwa alam semesta “just is, and that’s all” (Russell, Why I Am Not a Christian, 1957, 53). Pernyataan ini sering dipahami sebagai keberanian intelektual, tetapi dari sudut pandang filsafat, ia sesungguhnya adalah keputusan untuk berhenti bertanya pada titik tertentu.
Melihat Ateisme Modern dari Ilmu Kalam
Ilmu kalam klasik—khususnya dalam tradisi Asy‘ari–Maturidi—membaca sikap ini bukan sebagai netralitas rasional, melainkan sebagai komitmen metafisis terselubung.
Menyatakan bahwa realitas tidak memerlukan penjelasan ontologis di luar dirinya sendiri adalah sebuah klaim metafisis, bukan kesimpulan empiris. Fakhr al-Dīn al-Rāzī telah mengingatkan bahwa imkān (kontingensi) bukan kondisi epistemik, tetapi sifat ontologis: “al-imkān laysa jahl bi al-sabab bal ‘adam al-darūrah fī al-dhāt” (kemungkinan bukan ketidaktahuan akan sebab, melainkan ketiadaan keharusan pada zat itu sendiri) (al-Rāzī, al-Maṭālib al-‘Āliyah, jil. I, 101).
Dalam konteks modern, kritik kalam ini menemukan relevansinya kembali. Skeptisisme ateis sering menuntut agar setiap klaim tunduk pada verifikasi empiris, tetapi tidak pernah menjelaskan mengapa verifikasi empiris harus menjadi hakim tertinggi bagi semua jenis kebenaran.
David Hume sendiri—ikon skeptisisme modern—telah menunjukkan bahwa kausalitas, fondasi sains, tidak pernah ditangkap secara niscaya oleh akal, melainkan diasumsikan melalui kebiasaan mental (Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, 2007, 41).
Dengan demikian, ateisme modern tidak dapat dibaca sebagai posisi tanpa asumsi, melainkan sebagai konfigurasi asumsi yang berbeda dari teisme klasik. Masalahnya bukan sekadar apakah Tuhan ada atau tidak, tetapi asumsi apa yang kita terima tentang realitas, makna, dan batas rasionalitas manusia.
Konteks Indonesia
Dalam konteks Indonesia, problem ateisme tidak selalu lahir dari refleksi filosofis yang matang, melainkan kerap berkelindan dengan pengalaman sosial-keagamaan yang kompleks.
Sebagian ateisme muncul sebagai ekspresi kekecewaan terhadap praktik keberagamaan yang dirasakan kaku, legalistik, atau terjebak pada simbolisme kekuasaan. Namun membaca ateisme semata sebagai reaksi sosial juga tidak cukup, sebab di baliknya sering bekerja asumsi-asumsi filosofis yang tidak selalu disadari oleh para penganutnya sendiri.
Retorika ateisme kontemporer—terutama di ruang digital—kerap menyederhanakan persoalan metafisika menjadi slogan-slogan epistemik seperti cukup dengan sains atau beban pembuktian ada pada agama, tanpa terlebih dahulu menguji fondasi filosofis dari klaim-klaim tersebut. Di titik inilah ateisme tidak lagi sekadar posisi skeptis, melainkan berpotensi berubah menjadi dogma rasionalitas yang kebal dari kritik.
Karena itu, memahami ateisme secara serius tidak berarti menangguhkan kritik, melainkan justru membuka ruang kritik yang lebih tajam dan berimbang. Kritik filosofis diperlukan untuk menguji konsistensi logika ateisme, terutama ketika ia mengklaim netralitas metafisis atau menjadikan imanen sebagai horizon final makna.
Pada saat yang sama, ilmu kalam menyediakan perangkat konseptual untuk membaca keterbatasan argumen-argumen ateisme modern tersebut tanpa terjebak pada polemik defensif.
Namun Islam tidak berhenti pada kalam semata. Tradisi tasawuf menawarkan dimensi korektif yang penting. Bahwa menghadirkan Tuhan bukan sekadar sebagai objek perdebatan rasional, tetapi sebagai realitas makna yang dialami, dihayati, dan ditransformasikan dalam kehidupan etis.
Sementara itu, universalitas syariah—dalam kerangka maqāṣid—menjadi jembatan antara iman, rasionalitas, dan kemanusiaan. Dengan demikian, kritik terhadap ateisme tidak diarahkan untuk meniadakan keraguan, melainkan untuk menempatkannya dalam horizon pemahaman yang lebih utuh tentang manusia, makna, dan keterbatasan akal.
Seri tulisan ini akan bergerak dalam kerangka tersebut. Diawali dengan membaca ateisme secara historis dan filosofis, mengurai variasinya tanpa simplifikasi, sekaligus mengkritisi asumsi-asumsi yang bekerja di balik retorika ateisme kontemporer.
Bukan untuk menyeret pembaca pada perbandingan teologis yang prematur, melainkan untuk membantu mereka memahami peta persoalan secara jernih sebelum mengambil posisi. Sebab hanya dengan pemahaman yang utuh—bukan sekadar penyangkalan atau pembelaan—diskursus tentang Tuhan, manusia, dan makna dapat berlangsung secara dewasa, rasional, dan beradab.
Wallāh `a’lam bi haqīqatil hāl!

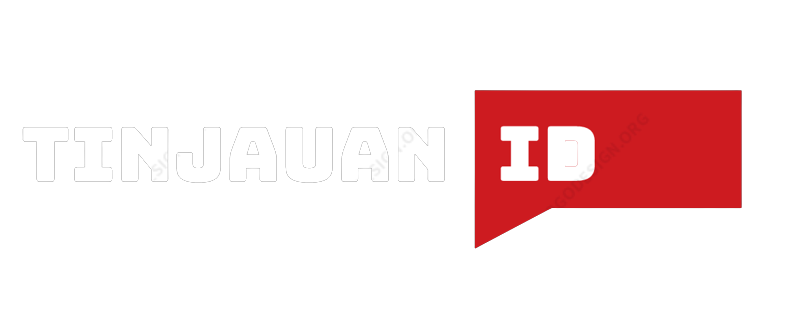














Discussion about this post