Apa makna musik itu sendiri bagi masyarakat Aceh hari ini. Apakah seni musik masih mempunyai spirit yang nyata dengan kehidupan sosial?
Perdebatan netizen Aceh, soal konser musik kembali mencuat di medsos, setelah rencana konser Slank (grup band pop-rock) asal Jakarta itu, dibatalkan. Alasan konser dibatalkan sudah bisa ditebak. Sudah menjadi gejala berulang dalam masyarakat Aceh yang taat. Setiap kali ada rencana menggelar pertunjukan musik, reaksi yang muncul hampir selalu sama: penolakan atas nama moral.
Seperti kebanyakan perdebatan moral, yang tersisa biasanya hanya dikotomi antara haram dan tidak. Konser dianggap membawa pengaruh buruk bagi kesalehan ruang publik. Memicu percampuran laki-laki dan perempuan, dan menjauhkan anak muda dari nilai-nilai Islam. Bahkan konser dianggap bisa berujung mendatangkan bala marabahaya. Dengan demikian, di ruang publik, argumen moral lebih sering terdengar daripada percakapan tentang seni itu sendiri.
Opini ini tidak dalam kapasitas membela pro konser musik atau yang kontra. Mungkin kita bisa membaca persoalan ini dari sisi lain. Masalahnya bukan sebatas boleh atau tidaknya konser, tapi mencari apa makna musik itu sendiri bagi masyarakat Aceh hari ini. Apakah seni musik masih mempunyai spirit yang nyata dengan kehidupan sosial?
Komodifikasi Hiburan
Sekarang, berdebat soal konser musik di Aceh, tak ubahnya plot sebuah drama, ada pihak yang antagonis dan protagonis. Pihak antagonis tentu kelompok menolak. Pihak protagonisnya adalah panitia konser (promotor) yang kerap bersembunyi atas nama korban penolakan. Padahal dibalik itu, mereka tidaklah juga “netral”.
Konser musik, itu tak lebih dari komoditas bagi segelintir orang guna kepentingan bisnisnya. Panitia musik (promotor), sebagai pemilik modal, pintar melihat potensi dengan mengeksploitasi kerentanan ruang publik di Aceh, yang selama ini haus hiburan ala ibukota. Penontonnya datang untuk menikmati hiburan yang dikonstruksi agar kiblat musiknya sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.
Seni musik sering tereduksi, hanya menjadi latar dari industri hiburan. Masyarakat haus hiburan namun acapkali yang disuguhkan tidak menyentuh realitas pengalaman sosial dan kesadaran kelas. Kalau melihat lebih kritis lagi, kenyataanya memang panggung konser yang didesain mewah, pengunjungnya ramai, tapi meninggalkan ruang kosong. Alhasil, hanya menjadi pergelaran dari kapitalisme hiburan dan promosi brand tertentu, bukan memantik ruang kebudayaan.
Bisa jadi alasan inilah relate dengan klaim beberapa pihak di jagad media sosial di Aceh, pembatalan konser Slank di Lhokseumawe bukan semata-mata karena diintimidasi oleh pihak tertentu namun karena konser musik yang digelar dengan menghadirkan artis nasional dengan tata panggung megah dan harga tiketnya fantastis, sehingga tidak terjangkau oleh kantong anak muda Aceh yang rata-rata pengangguran.
Selain itu, ketika konser digelar, jarang sekali ada ruang bagi musisi lokal untuk tampil sejajar. Mereka yang hidup dari musik yang menulis lirik lirih, bernafaskan kritik sosial tentang isu lingkungan, kemiskinan, atau pelanggaran HAM, tidak dianggap bagian dari panggung besar.
Dalam kacamata Mikhail Lifshitz, filsuf Marxis yang menulis The Philosophy of Art of Karl Marx, fenomena seni arus utama adalah bentuk “krisis seni”. Seni, katanya, kehilangan hubungannya dengan manusia dan berubah menjadi komoditas. Seni tunduk mengikuti logika pasar. Seni untuk seni, yang kemudian, bisa sangat cair dengan kehendak industri hiburan Yang laku, itulah yang dibuat.
Marx, sebagaimana dibaca Lifshitz, melihat kontradiksi mendasar di sini: di satu sisi, kapitalisme melahirkan kemajuan teknik, media, dan pertukaran kultural yang belum pernah ada sebelumnya. Disisi lain, menimbulkan keterasingan manusia dari karya dan dirinya sendiri.
Ruang seni kita sedang mengalami alienasi baru, hidup di antara algoritma, promosi iklan, dan izin pemerintah. Sedemikian diatur, dikontrol, dan dijual kembali. Padahal, tugas seni bukan menyesuaikan diri dengan kuasa industri ataupun kekuasaan, melainkan membantu manusia mengenali dirinya dalam dunia yang terus menindas.
Kembali ke Akar Sosial
Lifshitz melihat seni kebalikan dengan arus utama yang telah berkembang saat ini. Seni sebagai bentuk dari “realisme sosial”. Dalam pengertian itu, seni selalu punya akar komunitas. Bertumbuh dari pengalaman bersama umat manusia—kerja, penindasan, penderitaan, harapan. Ketika akar itu diputus oleh kepentingan modal, seni kehilangan daya reflektifnya.
Barangkali ada yang hilang dalam jantung kebudayaan Aceh, denyutnya berhenti karena pengaruh dominasi arus utama, seni kapitalistik. Ya fenomena yang perlahan-lahan menghilangkan identitas dan semangat kritisme orang Aceh yang anti penindasan.
Berbicara pelarangan konser itu, nyaris sama dengan isu bioskop di Aceh. Antara pro dan kontra. Bagi yang pro bioskop, beranggapan itu akan menghidupkan perfilman di Aceh, padahal yang hilang dari kebudayaan dan kesenian di Aceh bukan hanya berbicara seni bagaimana itu dipentaskan. Tetapi menata ulang makna seni lebih penting. Agar ia kembali menjadi cermin bagi masyarakat, yang berakar pada komunitas serta menjadi ruang bagi realisme sosial, tempat di mana suara musisi kecil jarang bisa terdengar namun terkadang lebih jujur.
Di masa lalu, lagu, hikayat, dan teater rakyat menjadi cara orang Aceh menafsirkan hidup. Saya dulu teringat di tahun 1999, kami anak-anak berhamburan ke lapangan di gampong Kota Mini, Beureunuen. Kami semua duduk bersila di atas rumput, hanya untuk menyaksikan Teungku Adnan PMTOH berhikayat—sosok legenda trobadur (pencerita keliling). Kami anak-anak tertawa terbahak-bahak mendengarkan jalan cerita yang disampaikannya, cerita yang disampaikan kerap kali dipenuhi nuansa satire tentang kondisi politik saat itu.
Kini, bentuk-bentuk kesenian seperti itu terpinggirkan oleh sistem kapitalistik hiburan yang menjual citra glamor. Sebenarnya Aceh tidak kekurangan seniman berbakat. Yang kurang adalah ruang yang memberi mereka kesempatan untuk berbicara tentang hal-hal yang penting bagi kehidupan bersama.
Saya masih teringat dikala satu siang yang cerah, di sebuah warung kopi di Banda Aceh, mungkin dua tahun lalu. Lagi asyik berbincang dengan kawan, di lorong antara meja-meja warkop, dari kejauhan saya melihat sosok ringkih dan bungkuk, berjalan agak pelan. Ketika hampir melewati tempat saya duduk, tanpa malu saya menyapa orang tua itu. Beliau merespon ramah, dan ikut duduk disebelah saya.
Nama beliau, mungkin bagi generasi baru Aceh tidak terlalu dikenal, tidak terkenal seperti seniman muda saat ini. Beliau adalah almarhum Hasbi Burman, seniman dan penyair Aceh, saya berani menyapa beliau, karena saya tahu beliau sebagai pencipta lirik Untong Kamoe Nyoe dari album Nyawoeng. Lagu itu dulu populer di radio-radio lokal. Kasetnya sempat dibredel oleh aparat.
Liriknya sederhana, tapi sarat sindiran terhadap situasi politik saat itu. Ia sempat bercerita, setelah lagu itu beredar, ia diwajibkan harus berkali-kali melapor ke kantor tentara. Bukan karena ia melanggar hukum, tapi karena suaranya dianggap mengganggu. Namun ia menjelaskan lirik itu tidak menuding satu pihak. Itu berlaku umum bagi siapa saja yang menindas.
Saya pikir, disitulah letak kekuatan seni, ketika berani menyuarakan kegelisahan masyarakat kecil lewat metafora lirih berdasarkan cerminan zaman. Lagu Untong Kamoe Nyoe, lirik dan iramanya itu adalah bentuk realisme sosial, kesaksian terhadap hidup kelam yang dirasakan rakyat Aceh ketika konflik yang melahap nyawa dan harta benda, dan asa.
Mungkin, seni yang seperti itu tidak akan mudah lahir kembali. Era berganti, orientasi musik sudah bergeser, generasi mempunyai segmen isu tersendiri hari ini. Tapi harapan musik harus lahir dari kesadaran kehidupan sosial, soal kemanusiaan bukan hiburan semata.
Oleh: Akhsanul Khalis, Dosen ilmu politik.
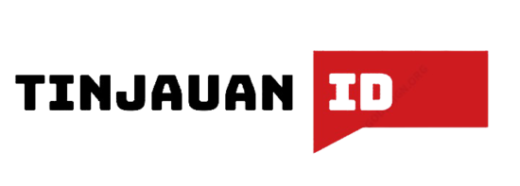
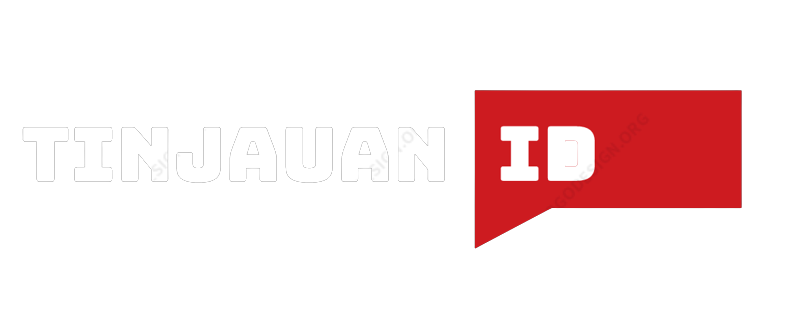

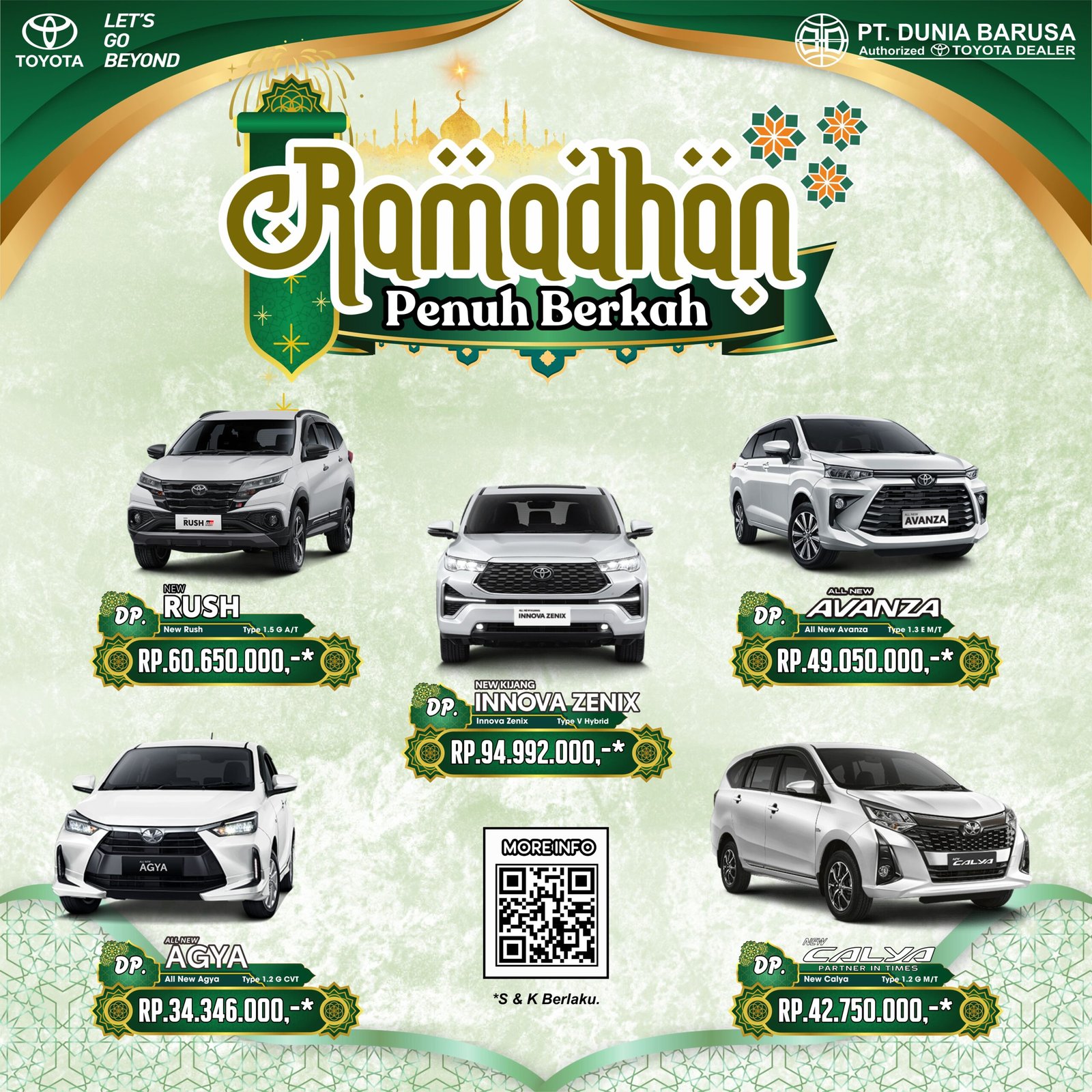












Discussion about this post