Gaza menjadi altar pengorbanan dari kemenangan kapitalisme global yang dipoles rapi dibalik kredo Hak Asasi Manusia dan demokrasi.
Oleh: Ahsanul Khalis*
Sejarah seolah berjalan memutar. Dulu di Abad 19 di Kekaisaran Rusia, komunitas Yahudi dipersekusi, dibantai, kemudian terkenal dengan nama pogrom. Selanjutnya pogrom jilid dua terjadi di Jerman yang dilakukan rezim Nazi Hitler, spesifiknya atas dalih pemurnian ras. Yahudi dianggap ras yang terkutuk, pengkhianat yang menyebabkan Jerman terpuruk setelah mengalami kekalahan di perang dunia pertama. Alhasil, konon menurut data sejarah: enam juta Yahudi dibantai di kamp-kamp konsentrasi.
Ironisnya, Israel, negara yang lahir dari trauma Holocaust, kini justru menjelma menjadi penindas baru di abad ini. Padahal, hasil ramalan sejarawan Israel Yuval Harari, umat manusia tengah berada di puncak ambisi menuju kebahagiaan absolut, setelah berhasil menaklukkan ancaman purba seperti penyakit, bencana, dan perang.
Puluhan tahun sejak berdiri, rezim zionis Israel lihai meniru sejarah yang dulu menimpa kaumnya. Jika Nazi Jerman menjalankan proyek “solusi akhir” bagi Yahudi dengan mendirikan kamp konsentrasi Auschwitz, Israel hari ini punya Gaza. meskipun tak ada kamar eksekusi memakai gas Zyklon B (jenis senyawa pestisida), tak ada barak pekerja paksa, tapi ada blokade kota yang membuat satu juta warga yang terdiri dari anak-anak, wanita, laki-laki dan lansia mati perlahan.
Setiap serangan pada rumah sakit, sekolah, tenda pengungsi, yang ditata rapi, dibungkus narasi melawan teroris, dijalankan sistematis adalah potongan dari satu cetak biru: solusi akhir versi zionisme. Sehingga kondisi Gaza lebih layak disebut demosida abad 21. Demosida, Istilah yang diperkenalkan Rudolph Rummel untuk menggambarkan pembantaian sistematis oleh suatu negara terhadap rakyat sipil, tanpa melihat identitas ras, etnis, agama, tetapi karena motif politik, ideologi dan kekuasaan.

“Dukha” tak Tertahan
Gaza dalam dua tahun ini adalah puncak tragedi. Apa yang kita saksikan, ibarat luka terbuka menganga, menyisakan kepedihan mendalam dengan skala nyerinya sudah tak tertahankan. Penderitaan yang sudah pada taraf kehilangan kata-kata. Dimana manusia dibantai dengan kejam. Tiap hari, nyawa melayang akibat kelaparan sistemik dan serangan senjata, bom yang berulang-ulang siang dan malam.
Reruntuhan bangunan rata dengan tanah terus bertambah, tenda pengungsi terbakar menjadi abu, dan potongan tubuh anak-anak ditarik dari puing-puing dengan tangan kosong. Pemandangan horor dengan gamblang disaksikan oleh mata warga dunia, yang hanya bisa berdoa pasrah. Dunia menyaksikan, tapi tak berdaya melawan.
Soal nyeri, Teuku Jacob, ahli antropologi biologi Indonesia, menyebutnya Dukha: bentuk pengalaman nyeri bukan hanya soal biologis, tetapi nyeri sebagai pengalaman manusia yang utuh. Nyeri sebagai penderitaan yang merasuk ke dalam tubuh, menjungkirbalikkan rasa aman, merobek relasi sosial, dan menghancurkan harga diri.
Di Gaza, rasa dukha menjadi kenyataan sehari-hari. Rasa dukha di Gaza adalah nyeri yang universal. Ia adalah penderitaan yang bisa menimpa siapa saja, kapan saja, jika sistem ini terus dibiarkan. Tak perlu sinematografi Hollywood, tak perlu aktor dengan air mata palsu. Cukup lihat satu video warga Gaza yang kelaparan, atau dengar jeritan yang direkam dari tempat pengungsian.
Seperti tulis Giorgio Agamben, filsuf Italia modern, sejarah kekuasaan seringkali meniadakan kemanusiaan, membiarkannya hidup sebagai Homo Sacer—manusia yang berhak dibunuh tanpa dihitung sebagai korban. Gaza adalah laboratorium dari model kekuasaan itu. Di Gaza, manusia dipertontonkan dalam wujud naked life (ketelanjangan hidup), ibarat manusia yang ditelanjangi, semut dan nyamuk pun bisa dengan leluasa menggigit. Kini, setiap warga Gaza tanpa perlindungan apapun di mata hukum internasional.
Duet maut Zionisme dan Kapitalisme
Apa yang terjadi di Gaza hari ini bukan hanya soal Israel dan Palestina yang terkesan konflik dua agama. Kalau bukan konflik agama, jadi apa yang disengketakan, seperti kita tahu Gaza tak membawa untung lewat sumber daya alam. Bukan kawasan kaya sumber energi fosil, bukan pusat keuangan. Sehingga menimbulkan pertanyaan, kenapa pembantaian terus berjalan?
Kengerian di Gaza adalah cermin dari masa depan dunia, dampak dari proyek kekuasaan yang lebih besar: gejala kapitalisme global yang gagal mengatur kembali etika dan batas moralnya. Gaza menjadi altar pengorbanan dari kemenangan kapitalisme global yang dipoles rapi dibalik kredo Hak Asasi Manusia dan demokrasi.
Negara-negara Barat jauh sebelumnya rajin mengulang sejarah traumatik Holocaust, bahkan mendramatisasi kekejaman Holocaust dengan epik lewat tangan sineas, melahirkan film box office Hollywood yang bertabur piala Oscar, seperti Schindler’s List. Kini justru memilih diam seribu bahasa.
David Harvey, teoritikus Marxist asal Inggris, sejak lama mengingatkan, kapitalisme tidak bekerja netral. Ia selalu butuh krisis, konflik, ketidakstabilan, sebagai cara mengakumulasi modal baru. Kapitalisme geopolitik sebagaimana Harvey tegaskan, bekerja seperti virus: ia menciptakan kekacauan, lalu menanamkan kepentingan modal diatas puing-puing kehancuran.
Kapitalisme hari ini ikut juga membentuk cara manusia menerjemahkan soal kekerasan dan perang. Perang bukan lagi soal kebenaran atau keadilan, melainkan soal siapa yang punya kuasa. Negara kuat bisa menjatuhkan bom, memblokade makanan, atau membantai warga sipil, dan semua itu bisa dianggap sah: asal didukung kepentingan pasar global, demi tujuan investasi senjata dan teknologi militer, pengamanan dan penguasaan geopolitik kawasan.
Demosida di Gaza menciptakan keuntungan bagi konglomerasi global secara langsung. Mereka, Amerika Serikat beserta sekutunya, menolak embargo senjata ke Israel, justru tetap memasok senjata, bom, investasi teknologi militer, dan alat berat. Bukan rahasia lagi, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah merilis puluhan nama-nama korporasi besar yang terlibat dalam pemusnahan massal warga Gaza: seperti Palantir, Microsoft, Amazon, Alphabet, Caterpillar dan Lockheed Martin, Elbit Systems, RTX (Raytheon).
Perusahaan-perusahaan itu menjadi tulang punggung, pemasok alutsista kampanye perang Israel, sehingga patut dinyatakan bagian tak terpisahkan dari industri kematian di Gaza. Mereka adalah arsitektur politik kekerasan yang menjadikan tubuh-tubuh warga Gaza sebagai collateral damage (kerugian tak disengaja) yang sah.
Inilah paradox kapitalisme modern: bom bisa dijual, kematian manusia bisa dipoles jadi statistik, dan penderitaan bisa dilupakan jika tak menguntungkan. Dalam logika pasar, nyawa bukan lagi sesuatu yang sakral, tapi angka dalam neraca: untung rugi. Setiap bom yang jatuh di Gaza adalah laba yang dicatat dalam bursa saham.
Kelak, sejarah akan mencatat: Israel adalah proyek kolonialisme baru, digerakkan oleh zionisme global yang dibalut teknologi, kekuatan militer, dan kekuasaan pasar. Agamanya bukan lagi Yahudi, selayaknya pengikut Yakub, Musa dan Ibrahim, melainkan zionisme plus kapitalisme. Kapitalisme yang memuja laba, yang tak lagi mengenal batas antara kemanusiaan dan kekuasaan.
*Penulis adalah Dosen, Direktur Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Lembaga ESGE Study Center.

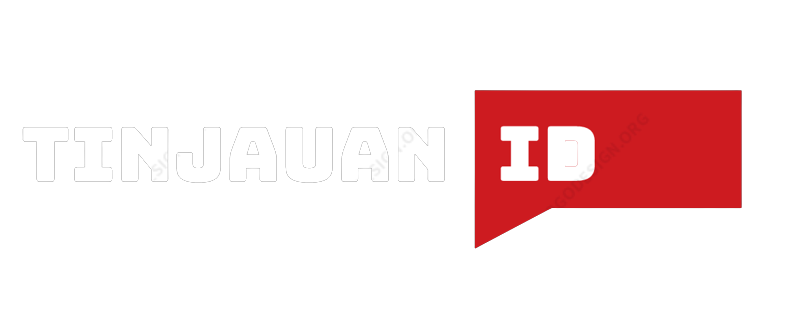














Discussion about this post