Oleh: Risman Rachman
Ada sebuah kata yang lama tertidur dalam kamus-kamus tua kita, lalu tiba-tiba terjaga di bawah lampu benderang aula Sentul. Corvée. Dalam bahasa Prancis kuno, ia bermula sebagai corrogata—sebuah seruan, sebuah tuntutan untuk kerja wajib. Di Eropa abad pertengahan, ia adalah beban bagi para petani untuk mengolah tanah tuan tanah atau memperbaiki jalan-jalan kerajaan tanpa upah. Ia mengandung aroma keringat, kepatuhan, dan terkadang, paksaan.
Namun, sejarah punya cara yang unik untuk membasuh makna. Di tangan seorang pemimpin, kata yang semula berbau feodal ini dipanggil pulang untuk menjadi sebuah etos. Presiden Prabowo, dalam Rakornas tempo hari di Sentul, tidak sedang meminta rakyat menjadi kuli bagi penguasa. Ia sedang meminta sebuah pengabdian kepada lingkungan yang kita tinggali bersama. Ia memanggil Corvée sebagai “perang” melawan kotoran (sampah) dan pengabaian.
Saya teringat sebuah fragmen cerita dari ujung barat nusantara. Di sana, seorang lelaki bernama Taqwallah, saat menjabat sebagai Sekda Aceh, sering melakukan perjalanan dinas yang panjang melintasi bentang alam Aceh yang megah. Namun, di antara hijau hutan dan biru pesisir, ada satu pemandangan yang selalu mengusik batinnya tiap kali ia melintas.
Ia kerap memperhatikan markas-markas TNI atau Polri di sepanjang jalan. Di sana, garis-garis halaman selalu tegas. Rumput terpangkas presisi. Tak ada cat yang mengelupas tanpa segera dipulas kembali. Semuanya tampak tunduk pada satu hukum: ketertiban.
Lalu ia menoleh ke arah kantor-kantor sipil. Di sana, ia sering menemukan wajah yang kontras—arsip yang berdebu, halaman yang ditumbuhi ilalang, dan aroma kelesuan birokrasi yang terjebak dalam rutinitas tanpa rasa memiliki.
“Kenapa mereka bisa mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, elok, rapi, estetik, dan hijau? Kenapa lingkungan kantor sipil tidak?” Pertanyaan Taqwallah itu bukan sekadar kritik estetika. Itu adalah sebuah gugatan eksistensial bagi para abdi negara. Apakah disiplin hanya milik mereka yang memanggul senjata?
Dari kegelisahan itulah semangat untuk menjalankan gerakan yang dikenal dengan akronim yang renyah di telinga orang Aceh: BEREH dijalankan dengan penuh dedikasi. Di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah—baik saat ia masih menjabat sebagai Plt hingga menjadi Gubernur definitif—BEREH menjadi sebuah “titah”: Bersih, Elok, Rapi, Estetis, dan Hijau. Sebelumnya disebut B.R.I Hijau (Bersih, Rapi, Indah dan Hijau).
BEREH bukan hanya soal menyapu lantai. Ia adalah soal martabat. Nova dan Taqwallah saat itu seolah ingin mengatakan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak mungkin lahir dari kantor yang kumuh. Keelokan lingkungan adalah manifestasi dari keelokan cara berpikir. Mereka membawa “ruh” Corvée ke dalam birokrasi Aceh: bahwa setiap ASN, dari pejabat tinggi hingga staf paling bawah, harus punya rasa tanggung jawab untuk membenahi rumahnya sendiri sebelum melayani rakyat.
Kini, lingkaran itu seolah bertemu titik temunya. Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sedang menyiapkan “titah” baru sebagai tindak lanjut pidato Presiden di Sentul. Sebuah Surat Edaran akan segera meluncur. Isinya? Menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah untuk kembali ke semangat Corvée.
Setiap Selasa dan Jumat, sebelum pena menyentuh kertas dan rapat-rapat dimulai, para abdi negara diminta turun ke halaman. Setengah jam untuk berkeringat, memungut sampah, dan memastikan lingkungan mereka ASRI. Ini adalah bagian dari Gerakan Indonesia ASRI yang dicanangkan nasional.
Mungkin, kita memang butuh sedikit disiplin “militer” dalam menjaga kebersihan sipil kita. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa peradaban besar selalu dimulai dari halaman depan yang rapi. Aceh sudah pernah menanam benihnya lewat BEREH. Sekarang, seluruh negeri diminta untuk menyiramnya.
Sebab pada akhirnya, Corvée—atau kerja bakti, atau gotong royong—adalah pengakuan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ia adalah cinta yang paling sederhana: cinta yang diwujudkan lewat sebilah sapu dan kemauan untuk membungkuk memungut sampah.
Tentu, ada “sampah” di dunia kerja yang juga sangat utama kita bersihkan juga yaitu “sampah” KKN: korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini adalah tiga praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang melanggar hukum, etika, dan merugikan negara. KKN bukan hanya korupsi, melainkan kombinasi tindakan penyelewengan uang, persekongkolan tidak sah, dan favoritisme yang merusak integritas lembaga dan pembangunan. []

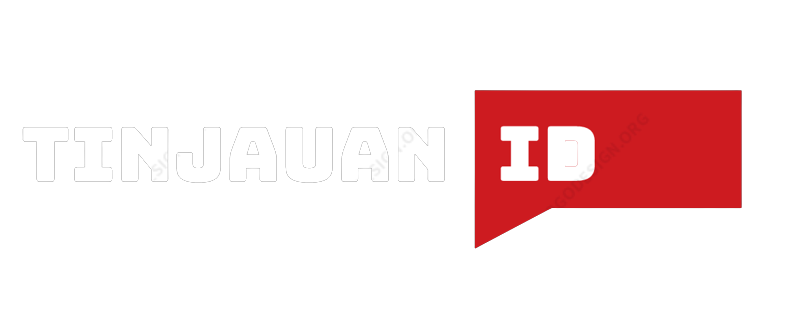














Discussion about this post