Dayah bukanlah produk otonomi khusus atau formalitas pelaksanaan syariat Islam di Aceh, melainkan akar sejarah yang jauh mendahului republik.
Oleh: Nurul Izzah Febilia
Mahasiswa Faculty of Education Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
Keberhasilan Tgk. H. Faisal Ali atau yang lebih dikenal sebagai Abu Sibreh memperjuangkan nomenklatur dayah dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2025 adalah tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam nasional.
Untuk pertama kalinya, istilah dayah berdiri sejajar dengan pesantren dalam regulasi negara. Langkah kecil ini menyimpan makna besar: pengakuan formal bahwa dayah adalah entitas pendidikan Islam dengan tradisi panjang, bukan sekadar variasi dari pondok pesantren Jawa.
Dayah di Aceh telah hadir ratusan tahun sebagai pusat pendidikan agama, penyebaran Islam, dan benteng budaya lokal. Pada masa kolonial, dayah bahkan berfungsi sebagai basis perlawanan. Kultur ini tergambar dalam petuah Aceh yang masih hidup hingga kini:
Ta jak sikula bah bek ipeunget le gob (menuntut ilmu di sekolah agar tidak dibohongi orang), dan
Ta jak beut bah bek ta peungeut gob (menuntut ilmu agama agar tidak membohongi orang lain)
Petuah ini menunjukkan keseimbangan, yaitu pendidikan formal atau modern ditempuh, tetapi pendidikan agama di dayah tetap dijaga. Bahkan hingga kini banyak keluarga yang tetap mengirim anaknya ke dayah meski tanpa pendidikan formal, atau mengintegrasikan keduanya.
Dayah bukanlah produk otonomi khusus atau formalitas pelaksanaan syariat Islam di Aceh, melainkan akar sejarah yang jauh mendahului republik. Karena itu, menyejajarkan dayah dengan pesantren adalah bentuk keadilan simbolik sekaligus pengakuan terhadap sejarah panjang peradaban Islam di Nusantara.
Selama ini, narasi pendidikan Islam Indonesia cenderung Jawa-sentris. Istilah “pesantren” dijadikan representasi tunggal, sementara “dayah” hanya disebut sekilas atau samar-samar.
Di sinilah peran Abu Sibreh menjadi signifikan. Sebagai anggota Majelis Masyayikh Kementerian Agama—lembaga yang mengatur standar pendidikan pesantren, ia berhasil memperjuangkan agar nomenklatur dayah masuk ke dalam kebijakan nasional. Terbitnya Permenag 12/2025 adalah bukti nyata politik rekognisi itu.
Bagi sebagian orang yang tidak memahami dampaknya, hal ini mungkin tampak sepele atau hal kecil. Pencantuman nomenklatur ini bukan hanya persoalan martabat identitas atau soal simbol belaka, juga bukan sekadar soal istilah administratif.
Pengakuan ini adalah capaian bersejarah. Ia memiliki bobot politik yang sangat penting. Dengan sejarah panjang ratusan tahunnya, dayah mendapatkan tempat setara dalam narasi pendidikan Islam nasional. Artinya, dayah tidak lagi berdiri di ruang abu-abu di bawah bayang-bayang pesantren Jawa, melainkan mulai mendapatkan pengakuan sebagai entitas pendidikan Islam dengan karakter dan sejarahnya sendiri.
Meski demikian, langkah ini tidak boleh berhenti di sini. Sejarah pendidikan Islam Nusantara masih kabur jika dayah hanya disebut selintas. Diperlukan pencatatan yang jernih, di mana Aceh ditempatkan sebagai titik nol Islam Nusantara sekaligus penopang peradabadan Islam dan dayah dikenalkan sebagai lembaga yang berbeda dari pesantren Jawa.
Karena itu, nomenklatur dayah harus dipastikan hadir bukan hanya di regulasi, tetapi juga dalam buku-buku sejarah, termasuk buku sejarah di sekolah formal.
Sebab, dayah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam paling awal di Asia Tenggara adalah peninggalan sejarah penting yang mencatat peran politik, sosial, sekaligus perjuangan melawan kolonialisme. Indonesia dan dunia internasional perlu mengenalnya sebagai entitas mandiri, bukan sekadar sub-bagian dari pesantren.
Politik rekognisi yang diperjuangkan Abu Sibreh adalah awal yang menggembirakan. Namun perjuangan belum selesai. Tantangannya kini adalah menempatkan dayah dalam peta besar pendidikan Islam Nusantara dan dunia. Dengan begitu, wajah Islam Nusantara akan tampil lebih utuh, inklusif, dan representatif sesuai dengan akar sejarahnya.
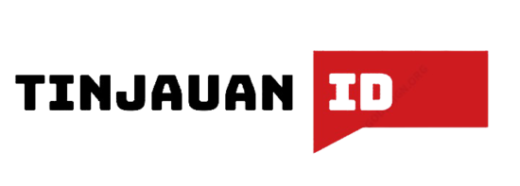
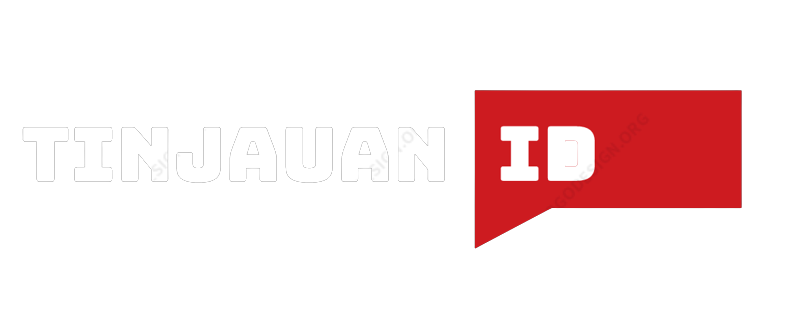













Discussion about this post