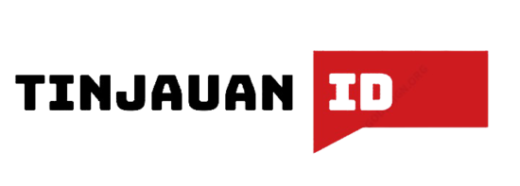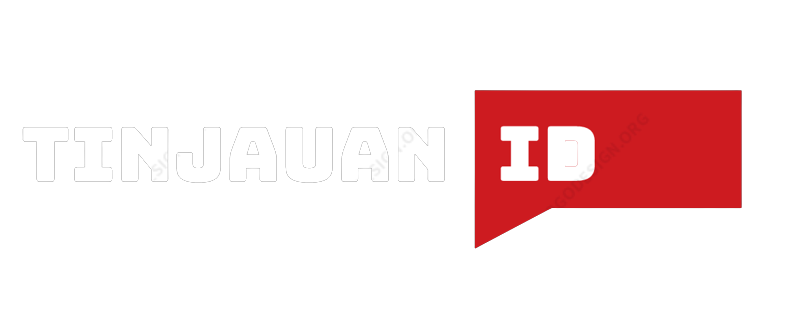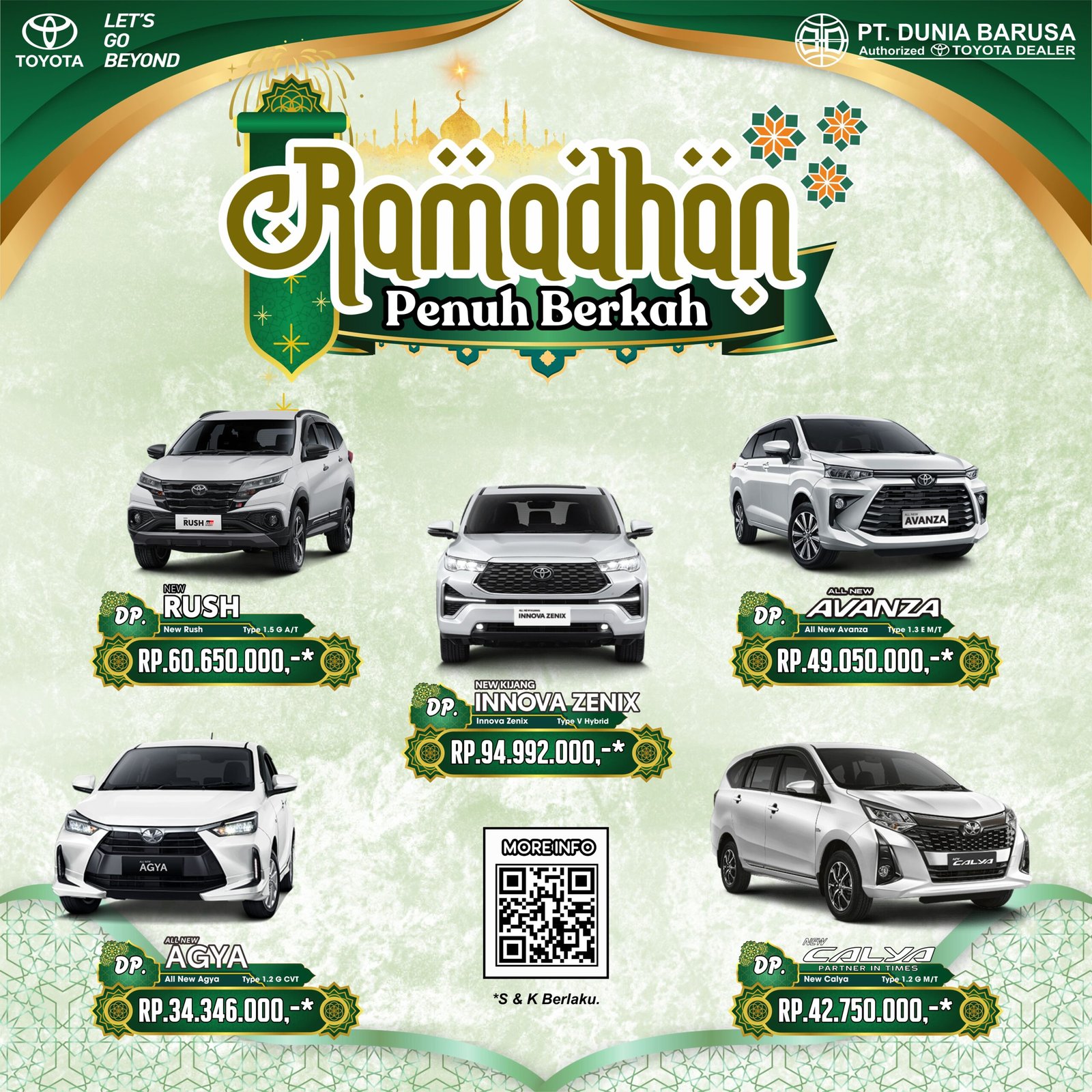Beberapa waktu lalu ada kejadian menarik yang terjadi di Cina. Badan Standar milik pemerintah Cina merilis sebuah temuan jika produk fashion bermerek Zara memiliki kualitas yang tak sesuai dengan standar kualitas produk tekstile/fashion yang ada di Cina. Pemerintah Cina mengklaim jika produk import bermerek Zara tersebut memiliki kualitas yang lebih rendah dari produk Cina sehingga pemerintah Cina tak membolehkan produk bermerek Zara itu untuk masuk dan beredar di wilayah Cina.
Ketika pertama kali mendengar perihal berita ini di salah satu stasiun televisi publik nasional, saya kala itu hanya bisa tersenyum sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepala. Pasalnya, setahu saya Zara itu bukanlah produk yang sembarangan. Di dunia ini, jika ditanya siapa milyuner dunia terkaya yang basis bisnisnya dari industri fashion, maka jawabannya adalah Amancio Ortega, sang pemilik Zara, seorang pengusaha terkaya asal Spanyol yang kekayaannya menduduki posisi 5 besar manusia terkaya dunia dengan total asset 37,5 Milyar dollar.
Jika berbicara tentang Zara, produk fashion manapun dari negara Paman Sam misalnya seperti Ralph lauren, Calvin Klein atau Nike sekalipun, kesemua itu tak ada apa-apanya dibanding kapitalisasi bisnis fashion milik Zara, perusahaan fashion asal Spanyol ini.
Dalam hal ini, Zara bukan menjadi titik tumpuan hal yang ingin saya bahas. Yang lebih menarik bagi saya dalam melihat kasus Zara di Cina ini adalah pertanyaan mengenai apa latar belakang yang melatari Cina untuk mengeluarkan rilis yang menyebut produk Zara berkualitas lebih rendah dari produk Cina. Jawabannya hanya satu, itu adalah wujud dari proteksi pemerintah Cina terhadap industri sandang/pakaian dalam negerinya. Saya nyaman menyebut ini sebagai “Politik Sandang (Politik Pakaian/Identitas yang dikenakan)” dari sebuah pemerintahan yang bernama Cina untuk memajukan industri dalam negeri yang berbasiskan nilai ekspor.
Cina tahu persis, kedigdayaan bisnis Zara merupakan satu hal yang mampu menggerogoti lini bisnis fashion yang mereka miliki. Tak ada satupun industri fashion di dunia ini yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Zara. Sedangkan di dunia ini, tak ada negara yang memiliki pasar industri tekstil/fashion sebesar Cina. lahirnya rilis yang menyebutkan produk Zara memiliki kualitas lebih buruk ini adalah titik temu dari dua kepentingan ekonomi, yang satu mewakili simbol kepitalisme korporasi global dan yang satu lagi mewakili simbol kapitalisme industri yang dibackup secara penuh oleh negara.
Hari ini adalah hari Batik, lalu apa hubungannya antara Zara, Cina dan Kita, sebagai Indonesia?
Titik temu dari semua ini adalah apa yang saya sebut tadi sebagai “Politik Sandang”. Di Indonesia, setelah adanya perjanjian ACFTA (Asean China Free Trade Area) beberapa tahun lalu, gempuran produk Cina ke wilayah Asean terutama Indonesia yang jumlah populasinya 50% dari total populasi Asean menjadi tak terbendung. Jumlah populasi Cina yang berkisar 1,4 Milyar jiwa mampu menekan wilayah Asean yang berpopulasi 500-an juta jiwa untuk menjadi sasaran empuk gempuran produk mereka.
Mengenai Batik, ada yang menarik di sini. Kini di Indonesia, di tengah euforia mengenai diakuinya oleh UNESCO batik sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia di tahun 2011, gaung industri batik semakin berkembang, Batik dikampanyekan sebagai simbol nasionalisme. Batik dijadikan pakaian utama yang harus dikenakan selalu saban minggu di semua instansi yang dibawahi oleh pemerintah. Dari pakaian seragam anak sekolah TK hingga kaum veteran yang sudah renta, upaya menjadikan batik sebagai pakaian merupakan sebuah keharusan.
Menariknya, kini, ditengah gembar-gembornya industri batik di tanah air, para pedangang dan pengrajin batik tradisional sedih bukan kepalang. Pasalnya, kini bisnis batik mereka sudah memiliki saingan baru yang lebih kuat. Di pasar-pasar dengan jumlah lintasan perdagangan yang besar, batik-batik impor buatan Cina kini semakin merajai. Para pedagang lebih tertarik menjual batik buatan Cina karena memiliki harga yang lebih murah dari pada batik hasil karya pengrajin dalam negeri. Kenyataan ini menciptakan ironi tersendiri jika di Indonesia, identitas yang coba dibangun sebagai penyatu keragaman nasional telah dijadikan komoditas industi yang amat menguntungkan oleh sebuah negara serba bisa bernama Cina.
Dalam melihat kasus ini, apa yang saya sebut sebagai Politik Sandang menarik untuk diamati. Kita bisa membandingkan bagaimana negara seperti Cina menempatkan batik dalam skema politik sandang mereka, ataupun juga bagaimana kita melihat Malaysia, negara yang pernah berkonflik dengan indonesia mengenai klaim batik oleh mereka menempatkan batik dalam kacamata politik sandang, selebih itu, yang terakhir adalah bagaimana Indonesia sebagai negara asal muasal batik menempatkan batik dalam kacamata politik sandang.
Bagi Cina, Batik adalah komoditas. Politik Sandang yang mereka terapkan semuanya berhulu pada kepentingan nasional untuk menciptakan surplus ekonomi dan mencapai nilai ekspor yang menjadi tonggak utama kemajuan ekonomi negaranya. Keberadaan ACFTA menjadikan Cina lebih mudah untuk menancapkan identitas politik sandang yang mereka miliki, dalam hal ini yaitu dengan cara menjadikan batik sebagai bagian dari komoditas ekonomi yang mampu menghasilkan pundi-pundi uang. Jika Zara yang terlihat begitu superior dan dianggap dapat menjadi ancaman sehingga mereka harus memutilasi keberlangsungan bisnis industri fashion ini di Cina, maka dalam kasus batik, batik dijadikan oleh pemerintah Cina sebagai sarana untuk mem-backup industri fashion yang menjadi tumpuan kemajuan Cina. bagi Cina, setiap hal yang bisa menguntungkan ekonomi dalam negeri menjadi hal yang harus diutamakan, termasuk dengan cara memproduksi dan memperdagangkan produk identitas milik negara lain semisal Batik, milik Indonesia.
Itu adalah bagaiman sebuah negara yang bernama Cina menjalankan politik Sandang yang berhubungan dengan batik. lalu bagaimana negara yang bernama Malaysia menjalankan politik Sandang terhadap batik milik Indonesia?
Untuk Malaysia, politik sandang yang dijalankan terhadap batik tak melulu bermotif ekonomi, tapi cenderung kultural atau tepatnya berujung demi kepentingan turisme. Dalam peta pariwisata dunia, Malaysia termasuk 10 besar negara dengan kunjungan wisatawan tertinggi di dunia. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi pendukung pendapatan negara di Malaysia. Di era globalisasi yang menghilakngkan sekat batas-batas teritori, pariwisata adalah sektor utama yang harus dikembangkan. Akan tetapi, untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan mampu menarik kunjungan yang tinggi, dibutuhkan persediaan kultur bentuk dan unsur kebudayaan yang beragam dan bernilai tinggi. Klaim batik oleh Malaysia ini adalah untuk mewujudkan hal itu, mewujudkan Malaysia yang menjadi tujuan utama wisata yang memiliki identitas kebudayaan yang kaya.
Jika Cina melihat batik sebagai bentuk dari politik sandang yang bermotif ekonomi, dan Malaysia melihat batik dalam skema pendukung kelengkapan senjata pariwisata di tengah arus globalisasi ekonomi, maka bagaimana Indonesia melihat batik sesungguhnya?
Di Indonesia ini, politik sandang akan batik jauh lebih buruk dari cara Malaysia dan Cina melihat dan memposisikan Batik!
Di Indonesia dalam hal politik sandang, batik dijadikan sarana untuk mematikan kekayaan ranah kebudayaan ragam produk sandang yang dimiliki oleh ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Indonesia, dalam hal politik sandang, Batik dijadikan oleh pemerintah sebagai sarana pembunuh identitas keragaman suku bangsa!
Dalam pandangan pemerinta Indonesia, politik sandang diterjemahkan sebagai implementasi keberadaan “single identity” akan produk budaya sandang/tenun yang benama batik. Batik di Indonesia dijadikan unsur untuk mengaburkan identitas budaya yang dimiliki oleh ratusan etnis yang memiliki ciri khas yang amat kaya. Upaya pemaksaan penggunaan batik di Indonesia mau tidak mau telah membunuh budaya tenun milik sub kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Pemaksaan akan batik ini menjadikan banyak lini kebudayaan tenun daerah yang menjadi mati. ketika orang Gayo dipaksa menggunakan batik, maka secara langsung mereka akan meminggirkan identitas tenun Karawang yang merupakan kebanggan yang mereka miliki. Ketika batik dipaksakan, maka masyarakat Melayu akan meminggirkan Songket mereka karena negara dengan kekuasaan penuh telah memaksakan mereka untuk mengenyampingkan identitas kebudayaan tenun mereka dan menggantikannya dengan batik yang khasnya milik suku Jawa.
Dalam hal politik sandang mengenai batik, Indonesia tertinggal jauh dari Cina dan Malaysia. Cina mampu menyulap batik yang notabene bukan identitas milik mereka menjadi lahan bisnis yang menguntungkan melalui skema perdagangan lintas regional, sedangkan Malaysia menjadikan batik sebagai pelengkap keragaman budaya mereka yang bertujuan untuk memperkuat negara agar mampu menjadi labih maju lagi dalam hal sektor wisata.
Sedangkan di Indonesia? Pemerintah Indonesia menjadikan batik sebagai mesin pembunuh kebudayaan. Pemerintah menjadikan batik sebagai single identitas kebangsaan yang pada akhirnya mematikan keragaman identitas tenun yang kaya raya milik ratusan identitas budaya lainnya yang da di Indonesia.
Lalu, melihat kenyataan seperti ini, lantas untuk apa kita merayakan hari batik? Untuk merayakan mesin pembunuh keragaman kebudayaan? Atau untuk memperkaya industri batik buatan Cina yang kini semakin menguasai pasar Indonesia?
Oleh: Muda Bentara
Peneliti di Saman Strategic Indonesia