Riyanto menganjurkan agar sosiologi hendaknya mulai berani mengakui bahwa kekerasan bisa menghasilkan “dampak-dampak sosial yang sifatnya produktif”. Kekerasan dalam konflik, dalam amatan Riyanto, tampaknya punya kemampuan mempercepat matangnya identitas.
Oleh: Bisma Yadhi Putra, peneliti sejarah.
Belum lama ini, waktu mencari-cari bacaan untuk menyusun tugas sebuah mata kuliah, saya menjumpai artikel mengesankan yang ditulis antropolog Geger Riyanto. Diterbitkan sebagai editorial sebuah jurnal, artikel itu seketika menjungkirbalikkan pemahaman saya atas kekerasan; bahwa kekerasan mungkin punya sisi positifnya, di samping daya destruktifnya.
Banyak ilmuwan sosial percaya bahwa konflik bisa membuka jalan terciptanya sistem atau kehidupan baru yang lebih baik, apalagi jika konflik itu tidak disertai kekerasan. Bahkan, ada yang meyakini konflik memang harus meledak dalam masyarakat yang gagal menemukan jalan lain untuk memajukan dirinya. Dari sinilah dibentuk pemahaman bahwa konflik bisa bersifat positif, sedangkan kekerasan mutlak negatif.
Banyak orang percaya tiada sedikit pun kebaikan dalam kekerasan. Kekerasan dianggap sebagai tindakan atau peristiwa yang cuma bisa mengoyak luka, mengembangbiakkan dendam, dan menyisakan tumpukan mayat. Kekerasan, dalam kajian-kajian sosiologi, umumnya juga dilihat sebagai peristiwa negatif sehingga melulu ditakuti kemunculannya. Dengan demikian, kekerasan harus dicegah sebab bertentangan dengan postulat “konflik adalah positif”.
Bahwa kekerasan harus dicegah, benar. Bahwa gelombang kekerasan harus dihentikan, tepat. Namun, anggapan bahwa kekerasan sama sekali tak punya sisi positif masih bisa dipertanyakan ulang. Dan inilah yang dilakukan Geger Riyanto dalam “Sosiologi yang ‘Tak Takut’ Kekerasan”, sebuah artikel yang terbit di salah satu edisi Masyarakat Jurnal Sosiologi tahun 2017.
Riyanto menganjurkan agar sosiologi hendaknya mulai berani mengakui bahwa kekerasan bisa menghasilkan “dampak-dampak sosial yang sifatnya produktif”. Usulan ini tentu sangat menantang lantaran sosiologi bukan hanya dikembangkan orang-orang yang menakuti kekerasan meledak dalam konflik sosial. Kenyataannya, sosiologi juga dimekarkan oleh para ahli pikir yang menentang konflik itu sendiri, apalagi kekerasan yang menyertainya.
Lantas, apa hal positif yang bisa dipicu kelahirannya oleh kekerasan?
Bertahun-tahun lalu, di sebuah film yang tak saya ingat lagi judulnya, ada sebuah percakapan menarik. Seorang perempuan di film itu mengatakan: “Identitas adalah struktur”. Kalimat ini begitu mengena sehingga saya langsung memvalidasinya lewat karya-karya ilmiah yang mengkaji persoalan identitas. Dan ternyata memang demikian adanya: identitas terdiri dari elemen-elemen yang saling terikat sehingga membentuk struktur. Elemen-elemen itu meliputi nama, suku, agama, tradisi, budaya, dan sebagainya.
Setiap masyarakat tentu memiliki identitas, atau biasa disebut identitas sosial. Agar identitas itu kuat, semua orang dalam sebuah masyarakat harus menjalani hidup sesuai dengan identitas yang diakui bersama. Tindakan sehari-hari setiap orang mesti mencerminkan identitas yang ada. Ketika semakin banyak orang menyerap elemen-elemen identitas sosial dalam perilakunya, semakin matang identitas sosial tersebut.
Sayangnya, pematangan identitas ini bisa berjalan cukup lambat. Tidak semua orang dalam masyarakat tertarik untuk betul-betul menjadi bagian dari seluruh elemen atau unsur identitas sosial. Dalam sebuah masyarakat Kristen, misalnya, banyak yang mengabaikan anjuran-anjuran pendeta untuk beriman dan meningkatkan solidaritas dengan orang-orang seagama. Pengabaian ini membuat penyelesaian identitas masyarakat tersebut lama prosesnya.
Kekerasan dalam konflik, dalam amatan Riyanto, tampaknya punya kemampuan mempercepat matangnya identitas. Situasi ini tampak dalam kasus-kasus konflik keagamaan. Sebelum kekerasan meletus, banyak orang muda kurang peduli dengan identitas yang dimiliki masyarakatnya. Apakah mereka terhubung atau tidak terhubung secara mendalam dengan identitas sosial yang ada, itu tidak penting. Namun, begitu masyarakatnya ditindas oleh masyarakat penganut agama lain, para remaja maupun pemuda yang semula kurang peduli dengan misi agama mulai bergegas menyatakan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari misi tersebut. Kekerasan untuk membalas penindasan kelompok lain dilakukan dalam semangat melindungi agama.
Alhasil, solidaritas keagamaan yang tadinya lemah, kini menguat lantaran semua orang bersemangat melakukan kekerasan demi melindungi agamanya dari kezaliman pihak lain. Identitas masyarakat itu pun jadi matang karena sekarang semua orang telah menempatkan agama sebagai bagian tak terpisahkan dari pikiran serta tindakannya. Kekerasan yang dilakukan pihak lain bisa membuat masyarakat yang tadinya kurang solid menjadi hidup dalam persatuan.
Kekerasan yang dilakukan orang Aceh terhadap orang-orang Jawa dalam periode konflik 1999 hingga 2004 juga bisa dilihat sebagai kasus pematangan elemen anti-Jawa dalam identitas keacehan. Semasa DOM (1989-1998), prajurit militer Indonesia banyak melakukan kekerasan terhadap penduduk Aceh. Dampaknya: anak-anak menjadi yatim, para perempuan menjadi janda, para ayah kehilangan anak kandung. Kekerasan itu memicu pengentalan sikap anti-Indonesia yang umumnya didefinisikan secara seragam dengan anti-Jawa. Sikap ini menjadi elemen penting dalam identitas korban kekerasan. Dalam identitas ini, setiap orang memahami dirinya sebagai individu yang ditindas dengan kekerasan sehingga perlu melancarkan kekerasan tandingan.
Dan, itulah yang terjadi ketika kelompok pemberontak punya kesempatan untuk memperkuat dirinya setelah Soeharto jatuh. Di masa transisi dari Aceh Merdeka menuju Gerakan Aceh Merdeka, para korban kekerasan yang telah mengafirmasi dirinya sebagai “musuh Jawa” lantas bergabung dalam pemberontakan. Anak-anak muda yang ayahnya dibunuh tentara bangkit melancarkan kekerasan terhadap siapa pun yang ditafsirkan sebagai musuh. Para transmigran Jawa ditempatkan dalam daftar musuh yang mesti diserbu. Alhasil, orang-orang Jawa pun diusir, dipotong lehernya, dibakar rumahnya, dirampas hartanya. Kekerasan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan performa identitas diri sebagai pejuang anti-Jawa.
Di sisi sebaliknya, gelombang kekerasan terhadap orang Jawa turut menciptakan pula dampak positif terhadap identitas mereka. Sejak tiba di Aceh sebagai transmigran, semua orang Jawa dituntut menyetarakan diri dengan orang Aceh. Orang-orang Jawa memikul beban untuk menyesuaikan ulang identitas mereka dengan identitas keacehan agar selaras dengan tradisi, budaya, hingga karakteristik islami masyarakat Aceh. Elemen-elemen identitas keacehan mesti diserap. Dengan demikian, para pendatang Jawa berada dalam proses penyusunan ulang identitas mereka.
Penyelesaian identitas itu tak berlangsung cepat karena orang Jawa menempati permukiman yang terasing dari orang Aceh. Interaksi yang intens dengan orang Aceh hanya terjadi dalam pernikahan atau hubungan dagang. Orang-orang Jawa yang terlibat dengan orang Aceh dalam dua hubungan itu mampu menyelaraskan identitasnya dengan identitas orang Aceh. Hanya saja, tak semua orang Jawa memiliki hubungan dekat dengan orang Aceh. Alhasil, asimilasi pun tidak cepat berhasil lantaran banyak orang Jawa masih mengekspresikan bagian-bagian identitasnya yang memicu kemarahan orang Aceh.
Ketika orang-orang Jawa mulai tertekan oleh kekerasan yang dilakukan GAM, mereka segera mempercepat penyerapan “Aceh” ke dalam identitasnya. Dalam waktu cepat, ditinggalkanlah kebiasaan-kebiasanan yang bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Aceh, contohnya pegelaran kuda lumping semalam suntuk sambil mabuk-mabukan. Pembentukan identitas baru yang tadinya cukup lambat menjadi cepat karena didorong oleh kekerasan. Kekerasan membuat orang Jawa cepat-cepat mengikis jarak identitas “Aceh” dan “Jawa”.
Sayangnya, saat penyusunan ulang identitas itu berhasil diselesaikan, gelombang kekerasan sudah terlanjur besar dan sulit dihentikan. Adaptasi yang baru saja berhasil itu tak banyak berguna bagi orang Jawa ketika pelaku kekerasan sudah berada pada tahap hanya ingin meluapkan kebencian secara total. Pada tahap ini, penjelasan “kami sudah keacehan” tak akan didengar. Betapa pun corak-corak keacehan bisa ditunjukkan secara nyata oleh orang Jawa, sebagian besar pemberontak Aceh tak memedulikan itu lagi.
Bagi orang Aceh sendiri, elemen “anti-Jawa” yang melekat dalam identitas mereka tak sepenuhnya lenyap ketika konflik berakhir. Bahkan hingga dua dekade setelah konflik, elemen itu masih terpatri dalam benak banyak orang Aceh. Sesekali ketika ada momentum yang ampuh menyulut ulang kebencian pada Jawa, elemen identitas itu ditampilkan kembali. Suara-suara anti-Jawa didengungkan ulang di ruang publik.
Barangkali, masih banyak kasus bisa diutarakan demi membuktikan tesis Riyanto bahwa kekerasan memang bisa “merampungkan identitas sosial tertentu”. Oleh karenanya, sudah semestinya kajian-kajian sosiologi tak lagi melihat kekerasan semata-mata sebagai peristiwa menakutkan. Sebagaimana Riyanto katakan: “Kekerasan boleh kita curigai merupakan tindakan yang memungkinkan pelaku kehidupan sosial mereproduksi identitas” dan oleh karenanya penelitian sosiologi memikul tanggung jawab untuk “memahami dinamika sosial kekerasan tanpa ‘takut’ dengan kekerasan itu sendiri”.
Hanya saja, ada satu hal yang mesti disikapi secara hati-hati. Meskipun kekerasan bisa mematangkan identitas secara cepat, ia tidak boleh dijadikan satu-satunya jalan untuk tujuan tersebut. Ketika identitas sosial yang tadinya matang berkat dorongan kekerasan kini mulai melemah atau mengalami kemunduran, sosiologi tak boleh menganjurkan kekerasan baru untuk merevitalisasi identitas sosial yang tengah layu itu.

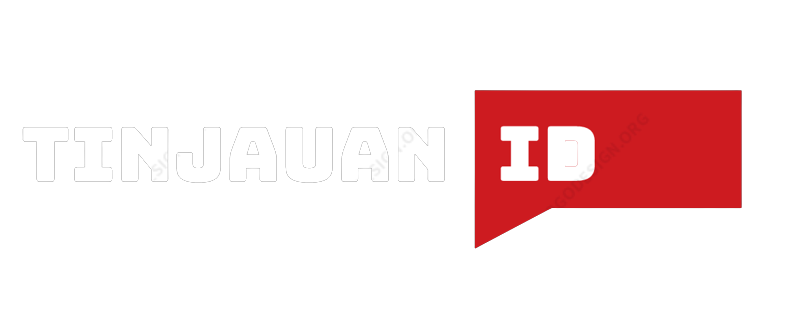












Discussion about this post