Alih-alih membangun sistem, Pemko Banda Aceh memilih jalan pintas dengan slogan “gratis untuk masyarakat”. Klaim sebagai kota pertama dengan layanan gratis memang terdengar manis di ruang publik, tetapi tanpa perencanaan matang, program ini justru bisa kontra produktif.
Oleh: Asrul Sidiq*
Sanitasi adalah isu yang sering luput dari perhatian publik. Kita lebih sering membicarakan jalan, gedung, atau fasilitas umum lain, tetapi jarang menyinggung apa yang terjadi di bawah tanah: septic tank dan lumpur tinja. Padahal, tanpa pengelolaan yang baik, limbah domestik bisa mencemari tanah dan air, menimbulkan penyakit, dan merusak kualitas hidup masyarakat. Karena itulah Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) menjadi bagian penting dari pembangunan kota yang sehat.
Belakangan, Pemerintah Kota Banda Aceh membuat gebrakan dengan mengumumkan diri sebagai kota pertama di Indonesia yang menerapkan layanan sedot tinja gratis. Program ini dilaksanakan melalui Perumdam (PDAM) Tirta Daroy. Sebelumnya, DLHK3 Banda Aceh mengelola layanan sedot tinja berbayar milik Pemko.
Program sedot tinja untuk masyarakat oleh PDAM ini diklaim mengadopsi sistem sukses di Kota Solo, kota yang lebih dulu punya program L2T2. Bedanya, jika di Solo masyarakat membayar biaya layanan dengan cara mencicil lewat tagihan PDAM, di Banda Aceh programnya gratis untuk masyarakat.
Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, layanan gratis hanya berlaku bagi pelanggan aktif PDAM yang tidak memiliki tunggakan tagihan. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar.
Pertama, soal pembiayaan yang berkelanjutan. Dari mana dana program sedot tinja gratis ini berasal? Apakah dari Corporate Social Responsibility (CSR) PDAM, dari anggaran daerah (APBK), atau dari pos lain? Jika dari CSR, mengapa prioritas tidak dipakai untuk membenahi layanan air bersih PDAM yang masih bermasalah? Jika dari APBK, timbul persoalan keadilan, karena dana publik seluruh warga Banda Aceh justru hanya dinikmati pelanggan PDAM.
Kedua, kapasitas pelayanan. Menurut kanal resmi PDAM, sudah ada ratusan warga yang mendaftar layanan ini. Estimasi waktu tunggu mencapai tiga hingga empat minggu. Akan tetapi, saat kita mendaftar layanan ini, tidak ada kejelasan berapa jumlah pasti pendaftar saat ini, bagaimana posisi antrean, atau kapan layanan akan diberikan. Bagaimana jika nanti antrian pendaftar sudah ribuan? Padahal, program yang membawa nama “Terjadwal” seharusnya benar-benar menghadirkan kepastian jadwal.
Ketiga, masalah keberlanjutan. Layanan gratis tanpa mekanisme pembiayaan yang jelas rentan menimbulkan moral hazard. Masyarakat bisa menjadi enggan menanggung biaya sanitasi, sementara PDAM terbebani kewajiban baru. Alih-alih menjadi solusi, program justru bisa menambah masalah.
Situasi ini makin pelik jika kita ingat bahwa pelayanan air bersih oleh PDAM sendiri masih menyisakan banyak kekurangan, mulai dari kontinuitas pasokan hingga kualitas air. Menambah beban baru tanpa perhitungan matang hanya akan memperbesar masalah. Jangan sampai solusi dari masalah pelayanan air bersih adalah layanan sedot tinja gratis yang mekanisme keberlanjutannya masih dipertanyakan?
Membangun Sistem, Bukan Slogan
Jika dibandingkan dengan perencanaan di beberapa kota lain, pendekatan Banda Aceh terlihat berbeda. Beberapa kota membangun L2T2 dengan sistem yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan. Ada empat elemen utama yang bisa dicatat.
Pertama, pembayaran yang ringan. Biaya sedot tinja tidak ditagihkan sekaligus, melainkan dicicil melalui tagihan PDAM. Warga hanya membayar sedikit setiap bulan, sehingga tidak merasa berat. Skema ini membuat layanan lebih inklusif karena pembayaran besar dalam satu waktu bisa menjadi penghalang.
Dengan tarif berjenjang yang dicicil lewat rekening air, warga terdorong berpartisipasi aktif, sementara pemerintah memiliki mekanisme pembiayaan jelas dan lingkungan tetap terlindungi. Meski begitu, sistem pembayaran ini rentan mendapat resistensi jika kualitas layanan sanitasi dan air bersih PDAM masih sering bermasalah.
Kedua, penyedotan terjadwal. Setiap septic tank dijadwalkan penyedotan rutin, umumnya setiap dua hingga lima tahun sekali. Dengan cara ini, masyarakat tidak menunggu sampai septic tank penuh dan mencemari lingkungan.
Ketiga, pemantauan septic tank. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan kondisi septic tank agar tetap sesuai standar kesehatan. Hal ini penting karena septic tank yang tidak kedap atau tidak pernah dikuras bisa mencemari sumber air tanah.
Keempat, pemerintah menggandeng swasta untuk memaksimalkan layanan sedot tinja yang sudah ada. Dengan armada pemerintah yang terbatas, kolaborasi ini menjaga kapasitas layanan tetap stabil meski permintaan tinggi. Selain membuka peluang usaha bagi swasta lokal, keterlibatan mereka memastikan lumpur tinja dibuang ke instalasi pengolahan resmi sesuai standar, sehingga pelayanan berlangsung lebih cepat, tertib, dan berkelanjutan.
Jalan Pintas yang Berisiko
Alih-alih membangun sistem, Pemko Banda Aceh memilih jalan pintas dengan slogan “gratis untuk masyarakat”. Klaim sebagai kota pertama dengan layanan gratis memang terdengar manis di ruang publik, tetapi tanpa perencanaan matang, program ini justru bisa kontra produktif.
Pertama, karena tidak ada mekanisme pembiayaan jangka panjang, layanan berpotensi berhenti di tengah jalan ketika dana tidak lagi tersedia. Kedua, tidak ada kepastian jadwal yang membuat warga benar-benar tahu kapan septic tank mereka akan disedot. Ketiga, program tidak mencakup warga non-pelanggan PDAM, padahal mereka juga berhak atas layanan sanitasi yang layak.
Harapannya program sedot tinja di Banda Aceh dapat berkembang menjadi layanan sanitasi yang adil dan berkelanjutan. Jika layanan gratis ini hanya tahap awal, pemerintah perlu menjelaskan sistem dan rencana ke depannya; tanpa itu, program bisa merusak keberlanjutan. Salah satu opsi adalah menyiapkan skema subsidi dan insentif yang tepat sasaran, sehingga bantuan tidak diberikan secara serampangan, melainkan adil dan berorientasi jangka panjang.
Sanitasi dan air bersih adalah hak dasar. Masyarakat berhak atas kepastian, bukan sekadar slogan. Jika Banda Aceh ingin benar-benar menjadi pelopor, maka yang harus dibangun bukanlah klaim, melainkan sistem yang kuat, adil, dan berkelanjutan.
*Penulis adalah Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Syiah Kuala.

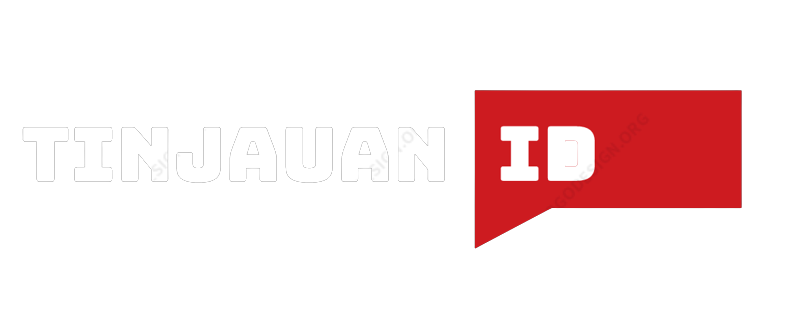













Discussion about this post