Di tengah gemerlap IPM, wajah Banda Aceh kalau boleh jujur, sehari-hari tidak selalu seindah hitungan statistik.
Oleh: Akhsanul Khalis*
Pemerintah kota Banda Aceh tentu punya alasan untuk berbangga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya naik ke tiga besar nasional, karena indikator rata-rata pendidikan lebih tinggi, angka harapan hidup membaik, dan konsumsi rumah tangga relatif stabil. Capaian ini hadir seperti secercah harapan di tengah stagnasi pembangunan Aceh yang lebih luas. Entah ini kabar baik !
Nah, disini ada semacam celah bahwa prestasi IPM Banda Aceh jika ditafsirkan dan dimanfaatkan secara politis, tentu seolah-olah semua warga merasakan kesejahteraan yang sama. Menjadi gambaran utuh kesejahteraan warga kota. Angka memang memberi kesan mampu merangkum denyut kehidupan. Kita tidak anti statistik, tentu itu metode pengetahuan.
Pertanyaannya: untuk siapa ia bekerja? Jika data lebih sering dipajang sebagai etalase prestasi dan lalu berhenti sebagai hiasan pidato, sementara warga yang hidup di pinggiran tetap jauh dari jangkauan kesejahteraan. Maka data itu kehilangan basis keadilan sebagai pijakan kebijakan.
Ketidakadilan Spasial
Lebih jauh, kita bisa membaca situasi ini melalui lensa urban bias David Harvey. Harvey menyebut kota sering dijadikan pusat akumulasi pembangunan, sementara wilayah desa dipinggirkan. Banda Aceh dengan IPM nyaris sempurna adalah contoh bias itu. Jika kita menelisik Banda Aceh sebagai kota, struktur ekonominya menunjukkan perbedaan jauh dengan daerah lainnya di Aceh. Sebagai Pusat pemerintahan menjadikannya “surga” bagi ASN, menjadikan lapangan kerja di sektor formal yang relatif stabil. Alhasil, banyak keluarga menggantungkan nafkah pada gaji aparatur.
Sangat wajar statistiknya melonjak, semua fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terkonsentrasi di pusat kota. Tetapi desa-desa (wilayah peyangga) tetap tersisih. Hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat kota, desa-desa masih berjuang untuk air bersih, layanan kesehatan dasar, atau pekerjaan yang layak. Ketimpangan ini nyata, tetapi tidak tercermin dalam angka IPM Banda Aceh yang begitu gemerlap. Dalam logika Harvey, ketidakadilan spasial inilah yang membuat pembangunan terasa timpang: pusat yang tumbuh, pinggiran yang stagnan.
Fetisisme Statistik
Statistik seperti IPM saat ini dianggap punya makna absolut sebagai alat ukur untuk memberikan gambaran makro tentang pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Padahal itu menjadi pisau bermata dua: mengaburkan realitas sosial. Maka penting selain problem ketidakadilan spasial, problem yang sama juga disinggung dalam How to Lie with Statistics, Darrell Huff: angka bisa membius, memberi ilusi kemajuan, padahal realitas di lapangan jauh lebih rumit.
Statistik rata-rata menutupi cerita mereka yang minoritas, keterbatasan akses. Seperti kata Joel Best, Damned Lies and Statistics: angka statistik sering dipakai pemerintah untuk “menceritakan keberhasilan” (numbers as rhetorical device). Angka ini tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar, hanya menunjukkan average, bukan distribution. Rata-rata menutupi ekstrem: segelintir warga hidup nyaman, banyak yang lain tetap rentan.
Di tengah gemerlap IPM, wajah Banda Aceh kalau boleh jujur, sehari-hari tidak selalu seindah hitungan statistik. Bagi masyarakat awam yang masa bodoh soal kebenaran versi statistik itu. Penting bagaimana fenomena yang perlu dilihat secara kualitatif: masyarakat yang terpinggirkan, yang kadang kala diabaikan dari angka. The Cult of Statistical Significance karya Deirdre McCloskey dan Steve Ziliak mengingatkan tentang: kultus signifikansi. Seringkali data kuantitatif statistik dipisahkan berdasarkan hitungan signifikan atau tidak signifikan.
Sehingga dengan standar capaian IPM, hitungan sederhananya, misalkan warga Banda Aceh 90 persen nya bekerja, otomatis ada bentuk pengabaian dari 10 persen yang menganggur. Arti angka 10 persen itu mungkin tampak kecil di tabel, namun di lapangan justru menjelma wajah-wajah kalangan anak muda yang putus asa mencari kerja, kerap menemukan kenyataan pahit.
Banda Aceh boleh bangga warganya mayoritas cukup terdidik, namun bukan berarti ketimpangan tidak terjadi. Dengan gelar tidak otomatis membuka pintu kerja. Rata-rata mereka harus berhadapan dengan kontrak magang, upah rendah, sementara banyak terjebak dalam kualitas kontrak informal yang tidak jelas. Banda Aceh, dengan konsentrasi universitas, memang berhasil mencetak generasi terdidik, tetapi banyak diantaranya hanya berputar-putar dalam ketidakpastian kerja, layak dijuluki pekerja rentan.
Pernah seorang kenalan, bercerita lirih, tak berani ke rumah sakit karena tak punya BPJS. Ilmunya tinggi, bergelar magister, pikirannya tajam, berstatus dosen pada salah satu kampus, tetapi hidupnya jauh dari kepastian. Jaminan kerja yang tidak jelas, honorarium yang baru turun enam bulan sekali, dan tubuh yang semakin sering sakit-sakitan. Kondisinya, ditinggalkan begitu saja oleh sistem yang mestinya melindungi. Ia terpaksa berkutat dalam lingkaran kerja seperti itu, karena tidak ada pilihan kerja yang lain. Ini cerita nyata, meski tak tercatat dalam laporan resmi.
Kisah ini tentu saja bukan datang dari dosen itu, banyak pekerja lainnya punya kisah yang sama. Setiap harinya berhadapan dengan ketidakpastian. Fenomena ini sering luput dari sorotan. Kini kita paham, bahwa yang “tidak signifikan” dalam statistik, justru bisa paling signifikan dalam kehidupan. Di sinilah letak apa yang bisa kita sebut fetisisme angka. Istilah yang sama dengan fetisisme komoditas: bagaimana sebuah barang menyembunyikan relasi produksi (terpisah dari sosial) di balik kemasan yang tampak mewah.
IPM, dalam kacamata serupa, mengingatkan kita pada kritik terhadap statistik kapitalistik: angka sering memberi ilusi keteraturan, padahal di baliknya ada relasi kelas yang timpang. Pengangguran muda, kerja informal, desa pinggiran yang tertinggal. Kita terpukau pada angka, seolah-olah terpisah dengan representasi parsial. Sama seperti Produk Domestik Bruto (PDB) yang bisa naik meski buruh tetap miskin, IPM pun bisa melambung meski banyak warga hidup dalam ketidakpastian.
Struktur ini adalah bentuk reproduksi kelas. Aparatur negara menikmati stabilitas, sementara kelas pekerja muda bergulat dengan ketidakpastian. Kita lupa bahwa IPM lahir sebagai kompromi: pelengkap PDB, bukan penggantinya. Namun ketika angka ini disulap menjadi prestasi justru menjadi alat ideologis: menampilkan kemajuan seakan sudah merata, padahal tidak.
Pada akhirnya, kritik terhadap IPM selalu mengingatkan kita bahwa Indikator yang disusun terlalu teknokratis, kuantitatif kerap membuat pembangunan tampak seolah bebas nilai, netral, dan tanpa konflik kelas. Misalkan disaat grafik IPM yang menanjak, di dalamnya tersembunyi relasi produksi, praktik eksploitasi dan alienasi dan ketimpangan yang nyata.
Toh, mau nantinya persentasenya IPM tinggi atau rendah sekalipun. Hukum besi kapitalistik, tetap berlaku. Akan termuat lagi kisah-kisah nyata tentang siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang justru tertinggal. Angka itu sering kali menutupi pertanyaan paling mendasar: siapa yang menguasai sumber daya, dan siapa yang hidup dari surplus kerja orang lain.
*Penulis adalah dosen dan peneliti bidang politik dan kebijakan publik di Lembaga ESGE Study Center.
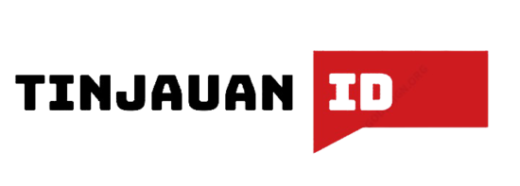
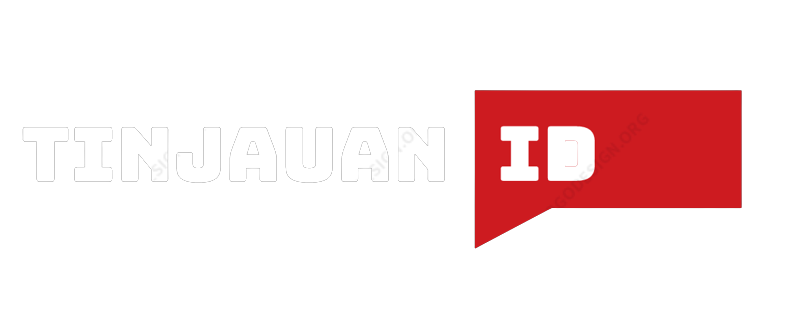

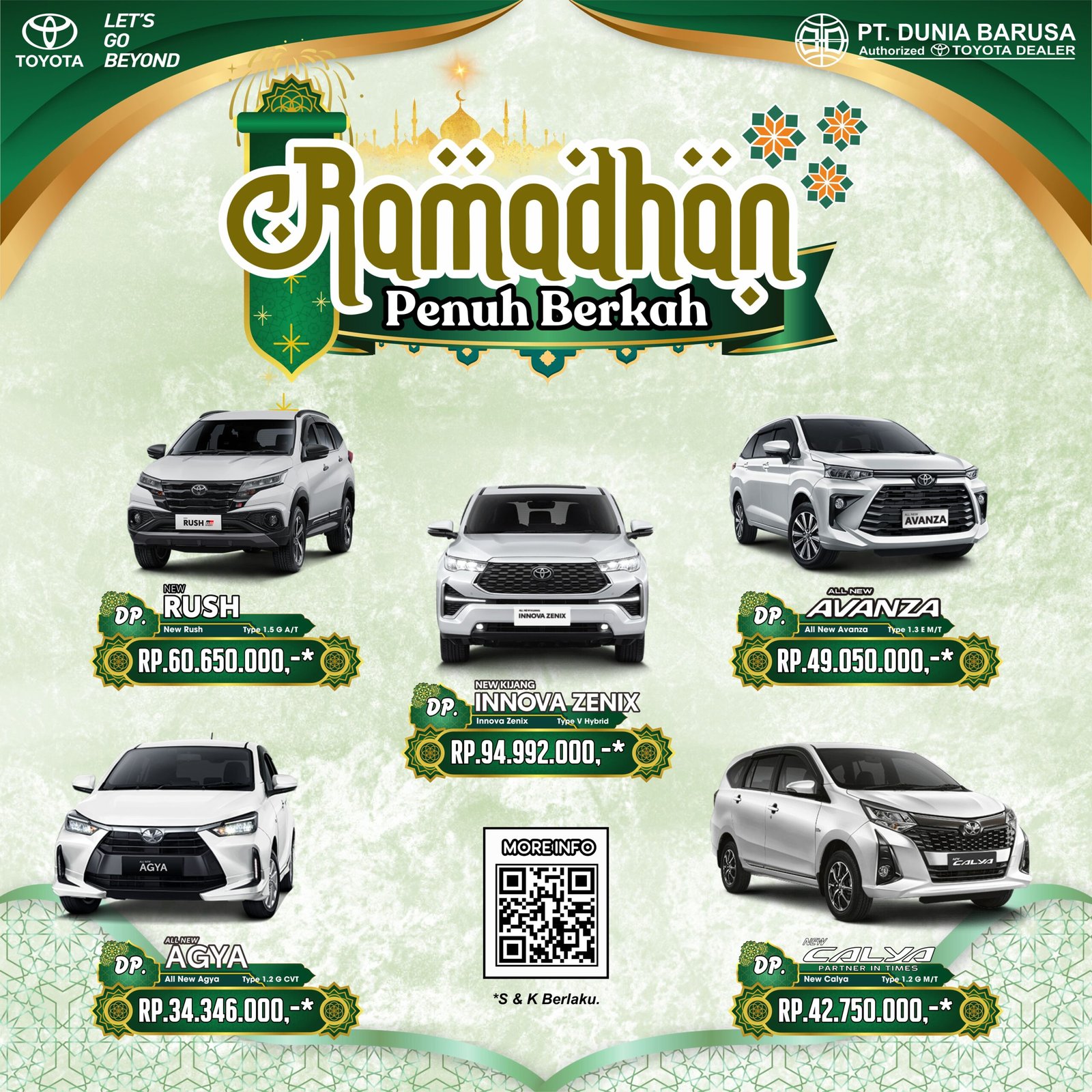












Discussion about this post