Di lingkungan asrama Sekolah Sukma Bangsa Pidie, para guru asrama dipanggil Abi. Bukan semata gelar formal, melainkan panggilan penuh makna sebagai ayah, pelindung, pendengar, sekaligus teman berbagi, mereka mendidik dengan cinta.
SIGLI – Sore itu, setelah salat Asar, Abi Rezi duduk santai di mushalla, bersebelahan dengan gedung asrama. Ia dikerumuni beberapa siswa yang bercerita tentang hidup mereka.
Ada yang berbicara pelan soal ayah yang tak lagi tinggal serumah, ada yang mengenang ibu yang harus bekerja jauh di luar kota. Abi Rezi mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali menanggapi dengan anggukan dan senyum simpul.
Sementara itu, Abi Jol melangkah tenang menyusuri lorong-lorong asrama. Ia memeriksa setiap kamar, memastikan semua anak bersiap untuk berjamaah.
Di sekolah ini, salat bukan sekadar kewajiban, tapi latihan kedisiplinan. Yang absen tanpa keterangan akan menerima teguran ringan, tentu bukan sebagai hukuman, tapi bentuk kasih sayang.
Di lingkungan asrama Sekolah Sukma Bangsa Pidie, para guru asrama dipanggil Abi. Bukan semata gelar formal, melainkan panggilan penuh makna: ayah, pelindung, pendengar, sekaligus teman berbagi, mereka mendidik dengan cinta.
Dan bagi puluhan anak laki-laki yang tinggal di asrama itu, Abi Jol dan Abi Rezi adalah sosok yang menjaga mereka setiap hari, siang dan malam, tanpa lelah dan tanpa pamrih.

Dari Siswa Menjadi Abi
Zulkarnain (24) dan Fakhrur Rezi (23) dulunya adalah siswa Sukma. Mereka tumbuh dan dibentuk dalam ekosistem pendidikan yang bukan hanya mengajarkan akademik, tapi juga nilai hidup, tanggung jawab, dan empati. Hari ini, mereka memilih kembali dan mengabdi, bukan sebagai guru kelas, tapi sebagai Abi—sapaan untuk pendamping asrama yang berarti ayah.
“Kami dipanggil Abi bukan karena umur, tapi karena peran,” jelas Abi Rezi. “Bagi anak-anak di sini, Abi adalah sosok yang bisa diajak cerita, marah, bercanda, bahkan menangis,” terang Fakhrur Rezi kepada Tinjauan, Rabu, (16/7/2025), di Sigli.
Mereka tinggal di dalam asrama, hidup bersama para siswa, tanpa jadwal pulang kantor. Hanya sesekali pulang ke kampung jika ada keperluan penting. Mereka menjadi penjaga malam, teman diskusi sore, dan pelipur lara bagi anak-anak yang jauh dari keluarga.
Siswa datang dari Berbagai Pelosok
Sukma Bangsa bukan sekolah biasa. Setiap anak yang menempatinya membawa cerita panjang—tentang kampung yang jauh dari kota, tentang keluarga yang tercerai, atau tentang masa kecil yang tidak selalu ceria.
Mereka datang dari lintas pelosok Aceh, dari desa-desa di Pidie hingga dataran tinggi Gayo, dari pesisir barat Aceh Selatan hingga lembah Tamiang. Setiap mereka membawa logat yang berbeda, doa yang berbeda, dan masa lalu yang tak selalu ringan.
“Ada anak yang tidak pernah bicara selama dua minggu pertama di asrama. Ternyata, di rumah dia biasa dimarahi terus, jadi dia pikir semua orang dewasa sama,” cerita Abi Rezi. “Kami pelan-pelan bangun kepercayaan. Duduk, dengar, dan ajak ngobrol sambil cuci baju.”
Satu hal yang menyatukan anak-anak itu, mereka datang bukan karena dipilih, tapi tahu sekolah ini adalah tempat belajar yang nyaman. Sekolah yang mengajar kejujuran dan toleransi antar sesamanya.
Meskipun sebagian siswa di Sukma ada yang menerima beasiswa penuh, mereka tidak membayar uang sekolah, makan, bahkan perlengkapan pribadi.
Sekolah ini dibangun pasca-tsunami, untuk membuka harapan bagi anak-anak Aceh yang kehilangan, yang terpinggirkan, yang butuh ruang untuk tumbuh.
“Kami tahu mereka tidak semuanya datang dari rumah yang aman dan nyaman,” ujar Abi Jol. “Tapi kami ingin pastikan, saat mereka di sini, mereka merasa punya keluarga. Punya rumah.”
Abi, Bukan Sekadar Penjaga
Di banyak sekolah, guru asrama mungkin hanya bertugas memastikan siswa tidur tepat waktu atau mengawasi saat makan. Tapi di Sukma Bangsa, peran Abi lebih dari itu.
Mereka adalah tempat pulang bagi anak-anak yang jauh dari rumah. Tempat curhat saat nilai menurun. Tempat bersandar saat ingatan tentang orang tua terasa menyesakkan.
Abi Jol dan Abi Rezi tidak sekadar menjaga. Mereka hadir bersama siswa. Mereka bangun paling awal dan tidur paling akhir. Mereka mencuci handuk anak-anak yang lupa angkat jemuran. Mereka membimbing salat dan diskusi malam. Mereka juga yang memeluk siswa yang tiba-tiba menangis tanpa sebab.
“Pernah ada anak yang bilang: “Abi, saya gak pernah ngerasain makan bareng ayah saya. Tapi kalau makan bareng Abi, saya ngerasa lengkap,” kata Abi Rezi.
Ia diam sebentar sebelum melanjutkan, “Kami tidak bisa menggantikan ayah mereka, tapi setidaknya kami bisa hadir,” ujarnya.
Mengasuh dengan Hati, Bukan Sekadar Tugas
Abi Jol dan Abi Rezi tak mengenal libur akhir pekan. Kalaupun pulang ke rumah, hanya jika ada hal penting. Selebihnya, mereka ada dalam segala arti kata.
Di usia muda, 23 dan 24 tahun, mereka memilih jalan yang tidak semua orang berani ambil: mengabdi dalam sunyi, menjadi ayah bagi puluhan anak yang tidak mereka lahirkan. Tapi mungkin di situlah letak makna pendidikan yang sejati.
Para guru hadir bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk menjaga. Bukan hanya memberi ilmu, tapi juga kasih sayang.
“Dulu kami diasuh oleh orang-orang yang ikhlas. Sekarang giliran kami menjaga mereka yang sedang tumbuh,” ujar Abi Jol, sambil menatap halaman asrama yang mulai sunyi menjelang malam.
Malam itu, ketika langit Pidie mulai menghitam, lampu-lampu asrama menyala satu per satu. Di dalamnya, dua Abi muda sedang memeriksa satu per satu kamar, memastikan setiap anak sudah mengenakan sarung dan bersiap tidur.
Dunia di luar mungkin sibuk mengejar target dan angka, tapi di sini, di sekolah kecil yang dibangun di tanah pasca-tsunami, dua pemuda sedang menjaga harapan para siswa, untuk memberikan mereka peluang meraih masa depan yang lebih baik.

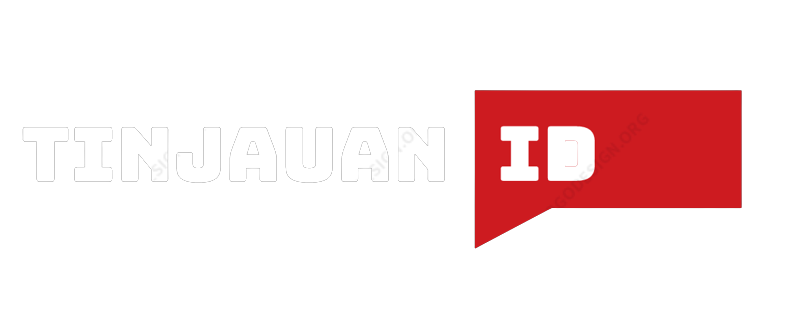














Discussion about this post