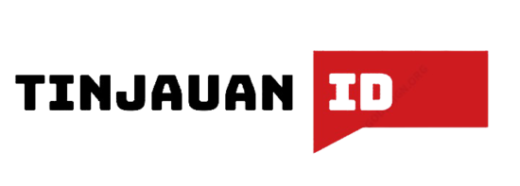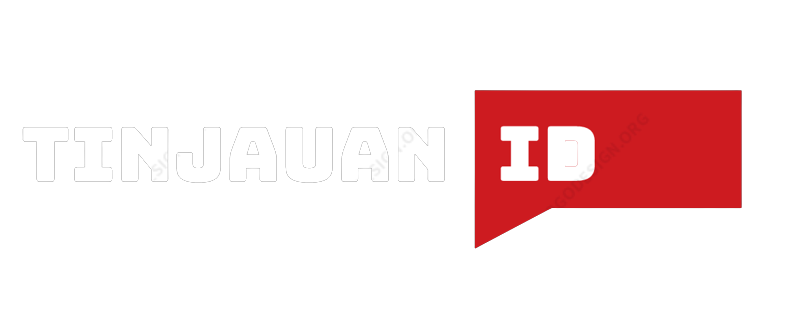Buku yang ditulis oleh Elisabeth Kramer, peneliti Cornell University Amerika Serikat ini menyajikan kepada kita berbagai kisah dilema antikorupsi. Kelebihan buku ini terletak pada kemampuan berceritanya tanpa menghilangkan ketelitian dalam memahami politik Indonesia secara umum. Kramer dengan terampil memberikan pelajaran yang bisa kita petik untuk demokrasi Indonesia.
Indonesia telah mengalami proses reformasi demokrasi dan transisi yang signifikan dari pemerintahan otoriter dalam dua dekade terakhir. Setelah berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru selama 32 tahun pada tahun 1998, Indonesia memulai jalur demokratisasi. Negara ini mereformasi sistem politiknya, memprofesionalkan militer dan peradilannya, serta menjamin pemilu yang bebas dan bersih setiap lima tahun. Sepuluh tahun kemudian, Indonesia terkenal sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia dan salah satu contoh keberhasilan transisi demokrasi di Asia.
Terlepas dari pencapaian tersebut, masih ada pertanyaan: Apakah kualitas demokrasi Indonesia mencerminkan pujian yang diperoleh dari luar negeri?
Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia dalam politik dalam negeri, dan salah satu tantangan yang dapat mengancam ketahanan demokrasinya, adalah masalah korupsi dan politik uang. Korupsi telah menjadi masalah umum yang dihadapi negara ini sejak Orde Baru. Memang benar, Indonesia telah mengalami reformasi politik yang signifikan yang menjamin adanya check and balances, penegakan hukum, serta undang-undang dan badan antikorupsi yang kuat. Indonesia juga telah mereformasi sistem politiknya untuk menjamin pemilu yang kompetitif. Namun sistem politik yang kompetitif ini juga mengakibatkan proses pemilu yang memakan banyak biaya (high cost) yang tentu saja berujung pada permasalahan umum lainnya yaitu politik uang, atau distribusi uang dalam jumlah besar kepada pemilih – dengan berbagai strategi – sebelum pemilu.
Buku Elisabeth Kramer, The Candidate’s Dilemma: Anticorruptionism and Money Politics in Indonesia Election Campaign (Cornell University Press, 2022), menawarkan analisis yang berguna tentang bagaimana politisi Indonesia menangani dua masalah yaitu korupsi dan politik uang dalam kampanye pemilu. Menghadirkan tiga kisah politisi antikorupsi Indonesia pada pemilu 2014, Kramer menunjukkan dilema politik yang dihadapi setiap politisi Indonesia: sembari berpegang pada prinsip antikorupsi, seorang kandidat berkompetisi dalam kampanye berbiaya tinggi yang ditandai dengan politik uang, yang seringkali memaksa mereka untuk berkorban. retorika antikorupsi mereka di depan altar politik elektoral.
Kramer menguraikan mengapa dan bagaimana dilema antikorupsi ini terjadi dalam kampanye pemilu di Indonesia. Pada Bab 1, Kramer menjelaskan lanskap politik elektoral di Indonesia setelah Orde Baru. Meskipun Indonesia berhasil mereformasi sistem pemilu setelah tahun 1998, khususnya dengan mendorong pemilu yang kompetitif dan sistem multi-partai, hal ini tidak cukup mengubah norma dan perilaku kampanye, khususnya yang berkaitan dengan mobilisasi sumber daya dan keterlibatan pragmatis antara kandidat dan pemilih. Untuk memenangkan pemilu, partai dan kandidat harus meyakinkan pemilih untuk memilih dengan menawarkan sesuatu yang nyata demi keuntungan mereka sendiri. Hal ini berdampak pada maraknya praktik jual beli suara di tanah air, yang menunjukkan warisan Orde Baru dalam politik elektoral di Indonesia.
Maraknya praktik jual beli suara dalam pemilu mendorong beberapa partai berkampanye dengan narasi antikorupsi, yang oleh Kramer disebut sebagai ‘antikorupsi’. Pada Bab 2, Kramer menelusuri asal muasal antikorupsi hingga reformasi politik pasca Orde Baru, di mana para aktivis politik berkampanye untuk mengakhiri KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang lazim terjadi pada masa Orde Baru.
Akibat dari reformasi antikorupsi yang setengah hati di era reformasi adalah dilema yang dihadapi para kandidat dalam memberantas korupsi dan politik uang dalam pemilu yang mahal dan sangat kompetitif. Dalam tiga bab tersisa, Kramer menyajikan tiga kisah aktivis antikorupsi yang beralih menjadi politisi di Indonesia yang menghadapi dilema ini dan mengatasi dilema tersebut. Kisah pertama tentang Ambo, seorang politikus antikorupsi yang gigih dari Sulawesi Selatan, menunjukkan kisah ‘sukses’ yang jarang terjadi, yaitu seorang kandidat yang menganut paham antikorupsi meskipun terdapat persaingan kompetitif dan jalan yang sulit untuk mendapatkan kursinya sendiri. Pemilu memang melibatkan politik uang. Namun terlepas dari segala rintangan, Ambo mampu mengamankan kursi tersebut tanpa membeli suara. Pencapaian ini bukannya tanpa bayaran. Dia harus meyakinkan pemilih dan menggunakan sumber daya pribadinya untuk pemilu, yang mengakibatkan berkurangnya mayoritas suara di distriknya sendiri.
Dua cerita lainnya kurang optimis. Ayu, seorang aktivis kelas menengah asal Jakarta yang memperjuangkan kursi di Jawa Timur, terpaksa ‘tunduk pada tekanan’ untuk menggunakan politik uang dalam kampanyenya. Dalam kasus ini, Ayu tidak hanya tunduk pada tekanan politik uang, namun juga gagal mendapatkan kursi meski memiliki hubungan dekat dengan Ketua Umum Partai tersebut. Kisah Ayu menunjukkan dilema yang terlihat jelas bagi para politisi dalam menghadapi politik uang, yang berujung pada kekecewaan ketika sang kandidat kalah dalam pemilu. Kisah lain tentang Bontor, aktivis antikorupsi asal Sumatera Utara, menunjukkan strategi pragmatis untuk mempertahankan komitmen antikorupsi dengan memadukan keistimewaan etnis dan agama. Bontor secara pragmatis menggunakan statusnya sebagai sesepuh Batak dan budaya ‘memberi hadiah’ sebagai cara lain untuk mendapatkan suara. Strategi pragmatis ini menggambarkan persinggungan antara budaya dan korupsi dalam kampanye di Indonesia yang juga memperkuat dilema antikorupsi.
Buku Kramer pada akhirnya menyajikan kepada kita berbagai kisah dilema antikorupsi. Kelebihan buku ini terletak pada kemampuan berceritanya tanpa menghilangkan ketelitian dalam memahami politik Indonesia secara umum. Kramer dengan terampil memberikan pelajaran yang bisa kita petik untuk demokrasi Indonesia. Agar demokrasi menjadi tangguh dan kuat, maka penting untuk mengatasi masalah korupsi, politik uang, dan kampanye pemilu yang memakan banyak biaya. Buku Kramer memberikan kita peringatan akan semakin merosotnya demokrasi di Indonesia jika permasalahan politik uang tidak dapat diatasi.
Namun ada juga pertanyaan lain: bisakah para kandidat benar-benar menyelesaikan dilema antikorupsi ini? Kramer berpendapat di Bab 6 bahwa pengurangan biaya pemilu dan keterlibatan pemilih diperlukan untuk mengatasi dilema antikorupsi. Ini merupakan usulan yang penting, namun dilemanya bukan sekedar memilih politik uang dibandingkan strategi kampanye lainnya. Menurut ilmuwan politik Burhanuddin Muhtadi, politik uang selalu melibatkan strategi dan personel yang kompleks di tingkat akar rumput, sehingga menghambat keterlibatan pemilih. Kisah Bontor menunjukkan bahwa proses pemilu yang mahal menyebabkan para kandidat terpaksa menggunakan praktik budaya yang sering melanggengkan tuntutan politik uang.
Oleh karena itu, mengatasi dilema antikorupsi memerlukan analisis di luar kampanye pemilu. Dalam hal ini, menghubungkan keterlibatan pemilih dengan aktivisme antikorupsi yang lebih luas setelah pemilu akan memperkuat argumen Kramer. Oleh karena itu, penilaian yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara politik uang dan antikorupsi juga memungkinkan analisis lebih lanjut mengenai masa depan demokrasi Indonesia secara umum, seperti yang dijelaskan dengan fasih oleh Kramer di bagian akhir buku ini.
Meskipun demikian, buku ini tetap menjadi salah satu buku penting bagi mahasiswa politik Indonesia.
Tulisan ini disadur dari laman LSE Book Review yang ditulis oleh Ahmad Rizky M. Umar.