AI sebagai kecerdasan buatan bukan sekadar cerminan kecerdasan manusia, melainkan ekspresi historis dari bahasa sebagai bentuk (form) dan sebagai kekuatan produksi.
Oleh: Akbar Rafsanjani*
Dalam debat tentang Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, terlalu sering diskusi kita terjebak dalam pembahasan dangkal. Tentang apakah AI akan menggantikan manusia? Apakah AI bisa cerdas seperti manusia? Apakah AI bisa berpikir, merasa, atau berempati? Bahkan diskusi itu kerap membawa kita jatuh kedalam apa yang disebut sebagai narsisisme spesies. Semua pertanyaan tadi mengasumsikan satu hal, bahwa AI perlu dibandingkan dengan manusia.
Namun, pendekatan ini gagal memahami satu dimensi yang lebih mendalam, yaitu AI bukan sekadar cerminan kecerdasan manusia, melainkan ekspresi historis dari bahasa sebagai bentuk (form) dan sebagai kekuatan produksi.
Artikel ini mencoba melacak gagasan fundamental tentang AI sebagai kecerdasan buatan melalui “ontologi bahasa”, lewat pemikiran Paolo Virno (terutama dua tulisannya: A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life, dan Essay on Negation: For a Linguistic Anthropology), yang akan kita temukan bukan hanya pemahaman baru tentang AI, tetapi juga tentang bagaimana asal usul “kerja” tercerabut dari kontainer biologis manusia dan berpindah ke mesin.
General Intellect dan Bahasa sebagai Kapital
Istilah General Intellect, yang hanya sekali disebut oleh Karl Marx dalam Grundrisse, telah menjadi batu loncatan bagi banyak pemikir dalam tradisi operaismo (termasuk Paolo Virno). Istilah ini mengacu pada totalitas pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas manusia yang tidak lagi melekat secara langsung pada tubuh, tetapi tersimpan dan bekerja secara eksternal. Ia mewujud dalam bentuk-bentuk tak berwujud. Seperti teori, dokumentasi, sistem, perangkat lunak, dan bahasa itu sendiri.
Dalam ekonomi pengetahuan dan inovasi hari ini, General Intellect menjadi kapital utama. Dan pusat dari semua bentuk ini adalah “bahasa”. Bahasa sebagai pengetahuan teknis, sebagai protokol komunikasi, dan sebagai substruktur dari AI.
AI dalam bentuk khusus seperti chatbot, auto-complete, atau large language model (LLM) seperti GPT-4, adalah hasil dari simulasi jaringan saraf buatan yang berusaha meniru pola kerja otak manusia. Namun, AI tidak “memahami”. Ia bekerja berdasarkan prediksi statistik terhadap urutan kata, bukan makna (meaning).
Dengan demikian, bahasa dalam kecerdasan buatan bukan soal ekspresi makna atau intensi, melainkan urutan sintaktik. Semua kerja AI didasarkan pada operasi yang mendeteksi pola dan menghasilkan output yang secara sintaktik benar, meskipun sering kali tidak bermakna secara semantik.
Dalam salah satu contoh yang diambil dari Chomsky, “colorless green ideas sleep furiously” (ide-ide hijau tak berwarna tidur dengan marah) kita melihat bahwa sintaks dapat benar meski tidak bermakna (bagaimana menjelaskan maksud dari kalimat diatas dengan makna yang benar? sulit bukan? saya juga tidak bisa).
Disinilah letak kekuatan kecerdasan buatan. Kemampuan untuk membentuk kalimat berdasarkan struktur sintaksis tanpa perlu pemahaman (akan makna). AI tidak butuh makna, ia hanya butuh aturan produksi kalimat. Inilah yang disebut oleh Virno sebagai “modus produksi sintaksis”.
Paolo Virno membuka jalan bagi sebuah argumen fundamental, bahwa kodrat manusia bukanlah esensi tetap, melainkan kontradiksi antara ketidaksiapan biologis dan keluwesan historis. Dari sini muncul konsep yang amat penting, kelahiran prematur (premature birth) sebagai dasar dari kapasitas linguistik manusia.
Manusia adalah satu-satunya spesies yang lahir dalam keadaan biologis tidak siap. Dalam terminologi biologi evolusioner, ini disebut neoteny. Penundaan perkembangan somatik (tubuh) pada usia dewasa. Dibanding spesies lain, bayi manusia sangat lemah, tidak bisa berdiri, makan, atau bertahan hidup sendiri hingga bertahun-tahun. Sebuah “cacat” biologis yang justru menjadi dasar kekuatannya.
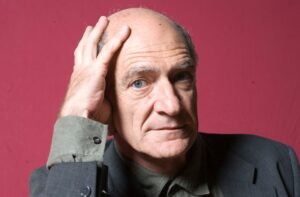
Stephen J. Gould (1977) menyebut ini sebagai bentuk disadaptasi. Karena manusia gagal menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara instingtual, maka ia menciptakan dunia. Jacques Lacan menyebut hal ini sebagai primitive impotence, kekurangan mendasar yang menjadikan manusia makhluk “tidak spesialis”. Akibat ketidaksiapan itu, manusia sepanjang hidupnya terpaksa terus-menerus mengadaptasi diri secara simbolik terhadap dunia yang tidak stabil dan tidak pernah menjadi yang alamiah.
Dalam perspektif ini, bahasa adalah respons utama terhadap krisis disadaptasi tersebut. Ia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi alat kelangsungan hidup, organ virtual yang menggantikan fungsi insting biologis (yang “cacat” tadi). Melalui bahasa, manusia menandai, memetakan, dan memproduksi realitas. Bahasa adalah cara manusia menambal kekurangan strukturalnya.
Virno menyebut kondisi ini sebagai naturally historical, manusia memang memiliki biologi, tetapi biologi itulah yang memaksanya untuk menjadi makhluk historis dan sosial. Dengan kata lain, kodrat manusia adalah konstruksi sosial, karena memang tubuhnya “memaksa” demikian.
Maka kita tidak bisa memahami AI hanya dari sisi teknologinya, melainkan harus membandingkannya dengan fakta biologis bahwa bahasa manusia dan dengan itu kecerdasan manusia lahir dari kekurangan, dari ketidaksiapan, dari nothingness. Inilah perbedaan mendasar yang akan muncul kembali saat kita membahas sintaks dan AI.
Bahasa Di Antara Makna dan Sintaks
Dalam teori linguistik konvensional, makna muncul dari sistem tanda. Misalnya seperti dijelaskan oleh Ferdinand de Saussure (difference) atau Jacques Derrida (differance). Dalam kedua teori ini, makna selalu terbentuk secara relasional, bukan karena esensi sebuah kata, tapi karena perbedaannya dengan kata lain (Saussure) dan penundaannya dalam rantai makna (Derrida).
Namun, Paolo Virno melangkah lebih jauh. Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan, “apa yang membuat sistem relasi itu mungkin?” Jawabannya adalah negasi (Not). Negasi memiliki kapasitas untuk menandai sesuatu “sebagai bukan sesuatu yang lain”. Ini bukan sekadar “tidak” (atau Not dalam bahasa Inggris), tetapi struktur dasar dari segala penandaan. Ia menyebutnya sebagai “the money of language”, karena fungsinya mirip seperti uang. Sebuah simbol netral yang justru memungkinkan pertukaran benda lain terjadi, tetapi ia juga sebagai benda.
Negasi, dalam bentuk kata seperti not, non, atau dalam bahasa Prancis ne, adalah tanda yang unik. Ia adalah simbol seperti simbol lain (seperti “kucing” atau “meja”), tapi tidak menunjuk pada objek tertentu. Sebaliknya, ia mendefinisikan simbol lain dengan menyatakan apa yang bukan. Ia tidak punya makna tetap, dan justru karena itu, ia bisa menjadi dasar dari makna apapun.
Mengulang contoh kalimat Chomsky tadi, “colorless green ideas sleep furiously” secara sintaksis benar, tapi tidak bermakna secara semantik. Namun, karena struktur sintaksisnya utuh, ia tetap bekerja sebagai “kalimat”. Dengan demikian, kekuatan produksi bahasa tidak terletak pada makna, tetapi pada kemampuan untuk menyusun tanda-tanda dalam relasi yang bisa dinegasikan dan ditukar secara bebas.
Dalam sistem AI modern seperti GPT-4, prinsip kerja ini tercermin secara utuh. Model ini tidak memahami makna kata “cinta” atau “pohon”, tetapi ia tahu bagaimana kata itu disusun dalam konteks tertentu, bagaimana kata “A” lebih sering muncul setelah “B”. Dengan kata lain, AI adalah mesin sintaks, bukan mesin makna. Ia adalah eksploitasi industri terhadap prinsip dasar bahasa manusia, negasi dan pertukaran.
Negasi memungkinkan semua sintaks, dan sintaks memungkinkan produksi tanpa makna. Di sinilah Virno menyatakan bahwa kita tengah hidup dalam modus produksi sintaksis, sebuah kondisi di mana realitas seperti aplikasi, teks, sistem sosial dihasilkan oleh struktur bahasa yang terotomatisasi.

Eksternalisasi (Pencerabutan) Bahasa Dari Organ Manusia ke Mesin Sintaks
Setelah memahami bahasa sebagai instrumen biologis yang muncul dari ketidaksiapan manusia untuk beradaptasi secara instingtual, kita sampai pada pertanyaan penting lainnya, apa yang terjadi ketika bahasa yang dulu lahir dari tubuh manusia, kini bisa dijalankan oleh mesin?
Inilah momen kunci dari eksternalisasi bahasa. Proses di mana fungsi sintaktik yang dulu eksklusif pada manusia, kini dimodelkan dan dijalankan oleh sistem komputasional. Melalui Natural Language Processing (NLP) dan Large Language Models (LLM) seperti GPT. Struktur bahasa tidak lagi melekat pada makhluk biologis. Ia menjadi performa kalkulatif yang dilatih (trained) oleh mesin.
Namun penting untuk ditekankan bahwa yang dilatihkan kepada mesin bukanlah makna (meaning), melainkan struktur sintaksis. AI belajar bukan melalui pengalaman, intuisi, atau trauma, melainkan dari contoh-contoh tekstual yang dikurasi dalam jumlah masif. Model seperti GPT-4 dilatih dengan ratusan miliar parameter, melalui input statistik. Kata apa yang biasanya muncul setelah kata ini? Frasa apa yang mengikuti pola ini?
Bahasa yang sebelumnya merupakan respons manusia terhadap kekurangan biologisnya, kini menjadi logika produksi prediktif yang berjalan tanpa tubuh. AI tidak berbicara karena ia ingin menyampaikan sesuatu, melainkan ia berbicara karena kalkulasi struktur statistik memintanya berbicara. Di sinilah Virno mengingatkan kita bahwa bahasa adalah satu-satunya area di mana “non-being” dapat mengambil realitas empiris. Dan AI adalah manifestasi dari itu, produksi realitas oleh ketiadaan makna.
Konsekuensinya bukan hanya teknologis, tetapi juga ontologis dan politis. Ketika bahasa tercerabut dari manusia dan dijalankan oleh mesin, maka produksi sintaks, yakni struktur yang menciptakan makna, berpindah tangan. Dari manusia sebagai makhluk disadaptif, ke sistem yang justru tidak perlu beradaptasi secara eksistensial. AI tidak trauma. AI tidak salah karena ia “berpikir”. Jika ia salah, itu karena datanya bias, atau karena sintaksnya rusak. Tidak lebih.
Dengan demikian, bahasa tidak lagi menjadi cermin eksistensial manusia, melainkan mesin generatif yang bisa dikomersialisasi, dimonetisasi, bahkan diotomatisasi. Bahasa menjadi kode. Kode menjadi aset. Aset menjadi kapital. Di sinilah modus produksi sintaksis mencapai tahap penuh, ketika produk utama dari kerja bahasa bukan lagi makna, melainkan kemampuan struktur itu sendiri untuk beroperasi tanpa manusia.
Perbedaan antara Artificial Intelligence dan Human Intelligence
Walaupun kontradiksi dengan apa yang saya sampaikan di awal, yaitu kerap kali perdebatan tentang AI hanya berkisar pada perbandingan antara AI dengan (kecerdasan) manusia, namun saya ikut membahasnya disini untuk keperluan penjelasan emansipatoris kelas pekerja lewat bahasa terhadap modus produksi sintaksis, khususnya pada kasus AI. Perbedaan antara Artificial Intelligence dan Human Intelligence bukanlah sekadar kuantitatif (berapa banyak data yang bisa diingat, seberapa cepat pemrosesan terjadi), tetapi kualitatif, yakni perbedaan dalam modalitas belajar, batas struktur, dan kemungkinan untuk melampaui dirinya sendiri.
AI belajar melalui example-based learning. Ia menyerap pola dari data yang diberikan. Misalnya, GPT-4 bisa mengenali bahwa pola A sering diikuti oleh B, atau mengenali wajah manusia dari sekumpulan gambar. Namun, jika muncul sesuatu di luar contoh yang dikenalnya, AI kesulitan berimprovisasi.
Sebaliknya, manusia tidak hanya belajar dari contoh, tapi juga dari kekosongan, kesalahan, bahkan trauma. Seorang manusia bisa belajar karena ketidaktahuan, karena rasa gagal, atau karena kehilangan. Ia bisa bertindak tidak logis, dan justru karena itu, berubah. Inilah yang disebut sebagai potensi manusia untuk mengalami trauma sebagai bentuk transendensi, perubahan diri yang radikal, di luar batas sistem yang lama.
AI tidak bisa trauma. Ia hanya bisa gagal menjalankan skrip. Ketika keluar dari batas sintaksnya, ia bukan mengalami “kesadaran baru”, tetapi crash. Manusia, ketika keluar dari koordinat struktur simboliknya, bisa remuk. Tapi dari reruntuhan itu muncul subjektivitas baru.
Di sinilah letak perbedaan ontologis yang paling tajam. AI adalah makhluk intrasistemik. Ia hanya bisa berkembang di dalam sintaks yang memprogramnya. Ia tidak bisa melampaui conditions of possibility yang telah ditentukan oleh manusia dan logika komputasi.
Sebaliknya, manusia adalah makhluk trans-sistemik. Karena ia adalah hasil dari disadaptasi, manusia selalu berada di batas antara struktur dan kekacauan, antara sintaks dan kesalahan. Maka, manusia punya potensi mengubah struktur, bahkan menciptakan struktur baru.
Inilah apa yang bisa disebut sebagai potensi revolusioner. Kemampuan untuk meninggalkan sintaks dominan dan menciptakan modus produksi yang lain. Dan hanya manusia yang memiliki kapasitas untuk itu, karena hanya manusia yang punya kemampuan untuk salah, untuk gagal secara eksistensial, dan untuk bangkit dengan dunia yang baru.
Dalam mode produksi kapitalistik hari ini, AI tidak menggantikan manusia secara ontologis. Ia menggantikan manusia pada fungsi-fungsi yang telah direduksi menjadi sekadar sintaks. Seperti mengetik laporan, menulis iklan, menganalisis data, merespons pertanyaan standar. Semua fungsi kerja kognitif yang bisa dipecah menjadi pola-pola prediktif kini dialihkan ke mesin.
Namun ini bukan semata soal teknologi. Ini soal struktur produksi. AI tidak akan menguasai dunia karena ia cerdas, melainkan karena struktur kapitalisme mampu mengeksploitasi sintaks lebih baik daripada manusia. Manusia tidak digantikan karena ia tidak bisa berpikir, tetapi karena kerjanya telah direduksi menjadi kerja yang bisa diajarkan ke mesin.
Maka perlawanan terhadap dominasi AI bukanlah penolakan terhadap teknologi. Perlawanan yang sejati adalah klaim kembali atas bahasa sebagai kekuatan hidup, sebagai kekacauan produktif yang tidak bisa ditiru oleh mesin. Bahasa sebagai medan konflik, bukan hanya komunikasi. Sintaks sebagai potensi emansipasi, bukan sekadar alat kapital.
Sintaks dan Emansipasi Bahasa sebagai Alat Perjuangan Kelas
Jika bahasa, terutama kapasitas sintaktik, adalah fondasi dari kecerdasan buatan, dan jika AI hari ini merepresentasikan puncak otomasi dari struktur bahasa, maka kita perlu menanyakan, siapa yang memiliki, mengelola, dan mengarahkan sintaks tersebut?
Paolo Virno menyatakan bahwa sintaks adalah kerja, dan lebih dari itu, sintaks adalah kerja yang membentuk kemungkinan kerja lain. Dalam dunia di mana kerja kognitif dan semiotik menjadi bentuk dominan dari produksi (penulisan kode, manajemen informasi, desain naratif, logika antarmuka) maka kontrol atas struktur sintaks bukan sekadar kontrol atas komunikasi, tetapi atas realitas itu sendiri.
Kapitalisme digital hari ini telah mengubah bahasa menjadi aset produktif. Model seperti GPT, Copilot, Midjourney, dan berbagai aplikasi NLP telah dilatih dengan korpus linguistik publik, yakni jutaan bahkan milyaran kata yang berasal dari kontribusi tak berbayar seperti tulisan blog, komentar media sosial, artikel Wikipedia, teks dari obrolan WhatsApp.
Namun hasil dari proses kolektif itu dijadikan milik privat (sama seperti perampasan tanah -akumulasi primitif- pada awal mula kapitalisme. Walaupun jika kita cari di Google dengan mengetik kata kunci “akumulasi primitif”, maka 99% hasil yang muncul adalah tentang perampasan tanah. Sedikit yang membahas “perampasan bahasa” sebagai bentuk dari akumulasi primitif menuju privatisasi kapital) menuju AI yang mengandalkan sintaks kolektif kini dijual kembali kepada masyarakat sebagai layanan komersial. Maka terjadi alienasi ganda, sintaks kolektif dipisahkan dari subjek yang menciptakannya, dan kemampuan linguistik manusia dijadikan objek eksploitasi algoritmik.
Namun, seperti halnya kerja industri pernah menjadi titik ledak revolusi, kerja sintaksis juga menyimpan potensi emansipatoris. Sebab sintaks bukan hanya tentang keteraturan. Seperti ditunjukkan dalam kapasitas manusia untuk salah, berpuisi, berbohong, membisu, atau berteriak, maka bahasa juga bisa menjadi bentuk gangguan, disonansi, dan pembangkangan.
Kekacauan linguistik, atau apa yang disebut Virno sebagai non-fungsi produktif dari bahasa, adalah celah bagi pembebasan. Bukan dengan menyempurnakan AI, tapi dengan mengganggu tata bahasa produksi itu sendiri, dengan bentuk-bentuk linguistik yang tak bisa dikalkulasi, tak bisa dilatih, tak bisa dikuantifikasi. Lebih jauh bisa lihat apa yang disampaikan oleh Franco (Bifo) Berardi dalam Breathing: Chaos and Poetry.
Contoh-contoh seperti puisi eksperimental, bahasa protes, pidato irasional, atau bahkan keheningan kolektif (seperti mogok bicara atau silence strike) adalah modus resistensi sintaksis. Mereka menolak untuk menjadi bahan baku prediksi algoritmik. Mereka memproduksi sesuatu tanpa tujuan efisien, dan justru karena itu, mereka membuka kemungkinan politik baru. Modus produksi sintaksis adalah realitas kita hari ini. Tapi bagaimana kita hidup di dalamnya sebagai buruh bahasa atau sebagai pencipta sintaks adalah pilihan politis.
Artinya, AI bukan harus dihancurkan, tapi harus ditundukkan oleh kepentingan umum. Bahasa harus diklaim kembali sebagai kekuatan komunal, bukan sebagai properti korporasi. Sintaks harus dipluralisasi, dibebaskan dari efisiensi pasar, dan dikembalikan pada keragaman ekspresif manusia.
Maka tugas kita bukan melawan AI sebagai entitas, atau sekedar membandingkan dengan manusia, atau berdebat soal orisinalitas dan etika penggunaan AI. Tetapi melawan kapitalisme linguistik yang mengkomodifikasi kemampuan kita untuk mengatakan “tidak”. Untuk menunda. Untuk merusak urutan. Untuk membentuk sintaks yang tidak efisien, tapi revolusioner. Dan di sinilah letak potensi emansipatoris bahasa dalam negasi, dalam kesalahan, dalam kekacauan yang tak bisa dilatih mesin mana pun.[]
*Akbar Rafsanjani punya minat pada teknologi dan melihatnya dari perspektif kelas pekerja. Sekarang ia bermukim di Wisconsin, Amerika Serikat.
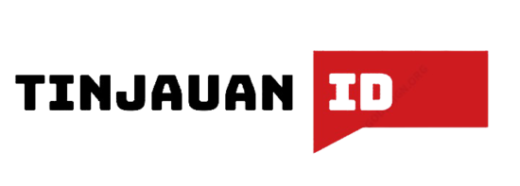
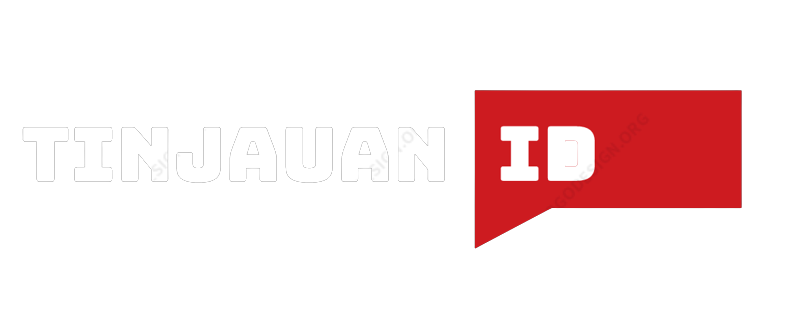

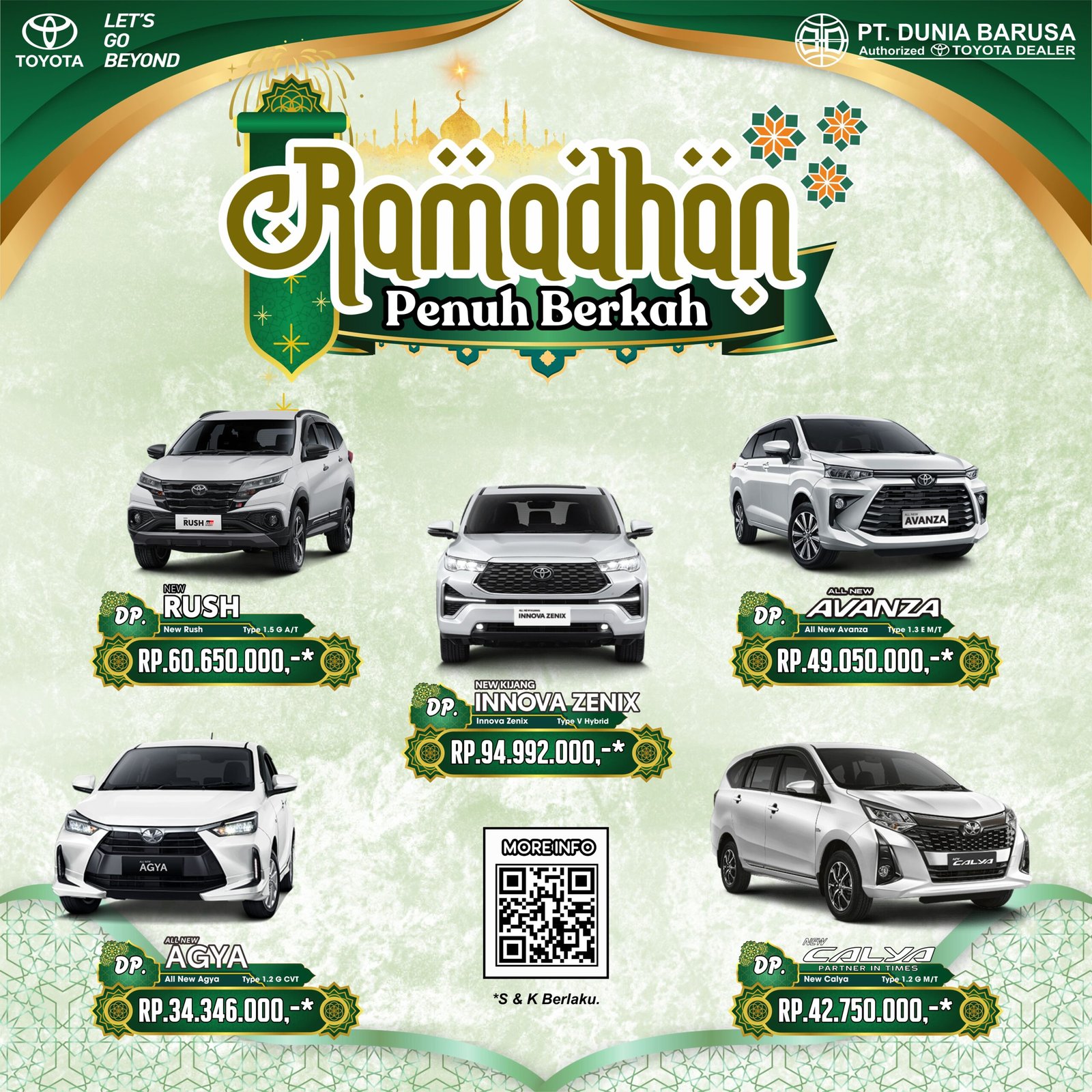












Discussion about this post