Dari pengaruh budaya India dan Arab hingga mitos tolak bala, tradisi boh gaca terus hidup dalam denyut budaya masyarakat Aceh.
Oleh: Sayid Muchsin
Di balik merah merona jemari pengantin perempuan Aceh, tersimpan jejak peradaban ribuan tahun. Di tanah Rencong, pewarna kuku bukan hanya soal kecantikan, tapi juga makna dan keyakinan.
Boh gaca; tradisi menghias tangan dengan inai, bukan sekadar perias tubuh, melainkan simbol doa, harapan, dan perlindungan. Dari pengaruh budaya India dan Arab hingga mitos tolak bala, tradisi boh gaca terus hidup dalam denyut budaya masyarakat Aceh.
Aceh bukan sekadar wilayah di ujung barat Indonesia. Letaknya yang strategis di utara Pulau Sumatera menjadikannya simpul penting dalam jalur pelayaran internasional.
Di utara berbatasan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman, di barat dengan Samudera Hindia, di timur dengan Selat Malaka, dan di selatan dengan Sumatera Utara.
Sejak masa lalu, Aceh menjadi pintu masuk berbagai pengaruh budaya—mulai dari India, Arab, Tiongkok, hingga Eropa.
Bahkan sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Aceh telah berdiri sebagai Kesultanan Islam yang berdaulat. Sebagai penerus Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam mencapai masa keemasannya pada abad ke-16 hingga ke-17, dengan kekuatan militer, kecemerlangan ilmu pengetahuan, serta kemakmuran hasil alam, terutama rempah-rempah.
Perkawinan: Perpaduan Tradisi Islam dan India
Adat perkawinan di Aceh mencerminkan dua pengaruh besar: tradisi keislaman dan tradisi India. Pengaruh Islam sangat kuat, sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Aceh: “Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut”—adat dan hukum Islam ibarat zat dan sifat yang menyatu.
Dalam adat perkawinan, terdapat tahapan penting seperti jak keumalôn (mencari tahu latar belakang calon mempelai perempuan), jak ba ranub (melamar secara resmi melalui musyawarah adat), hingga jak ba tanda (tunangan dan penetapan hari pernikahan). Setiap tahap sarat nilai kekeluargaan dan kearifan lokal.
Namun, di balik kuatnya corak Islam, tradisi India juga memberi warna. Pengaruh ini tidak terlepas dari kedekatan geografis Aceh dengan anak benua India.
Selain itu, kehadiran diaspora India yang telah lama menetap di Aceh turut memperkaya ragam budayanya. Dua unsur khas dari pengaruh ini adalah peusijuk (tepung tawar sebagai simbol doa) dan boh gaca—tradisi menghias tangan dengan inai atau pacar.
Boh gaca dalam adat Aceh bukan sekadar hiasan. Ia adalah bagian sakral dari prosesi pernikahan. Calon pengantin perempuan akan diberi inai di tangan dan kuku. Sebelum itu, ia terlebih dahulu di-peusijuk dan didoakan oleh orang tua serta tokoh adat.
Warna merah dari inai melambangkan kebahagiaan, keberkahan, dan perlindungan spiritual.
Proses pemakaian biasanya dilakukan selama tiga malam berturut-turut, karena angka ganjil diyakini membawa keberuntungan. Semakin merah warna inai, semakin besar pula harapan akan rumah tangga yang penuh kebahagiaan.
Konon, tradisi ini telah berusia ribuan tahun. Sebagian orang tua Aceh meyakini bahwa yang pertama kali memakai inai adalah Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim AS. Dalam budaya Arab, India, dan Mesir, pemakaian inai juga menjadi bagian dari penyambutan hari besar keagamaan atau peristiwa penting.
Dalam Islam sendiri, pemakaian inai oleh perempuan tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda:
“Jika kamu seorang wanita, seharusnya kamu ubah kukumu dengan henna.”
(HR. Nasai dan Abu Daud)
Hadis ini menunjukkan bahwa pemakaian inai bukan hanya dibenarkan, tetapi juga merupakan bagian dari syiar keindahan dan kerapian dalam Islam.
Tradisi Sejenis di Nusantara
Tradisi menghias tangan dengan inai ternyata tidak eksklusif milik Aceh. Di berbagai penjuru Nusantara, praktik serupa hidup dan berkembang dengan istilah serta kekhasan masing-masing:
• Bainai di Minangkabau
• Mapacci di Bugis, Sulawesi Selatan
• Berinnai di Riau
• Berpacar di Palembang
• Malem Pacar di Betawi
• Pasang Pacar di Lampung
Meskipun berbeda nama dan tata cara, seluruh tradisi ini memiliki fungsi serupa: sebagai simbol kecantikan, restu, dan perlindungan menjelang pernikahan.
Kesamaan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh budaya India dan Islam dalam membentuk wajah budaya pernikahan di Nusantara.
Yang menarik, tradisi boh gaca di Aceh tidak hanya terkait dengan pernikahan. Di beberapa daerah, inai juga digunakan sebagai ritual tolak bala, terutama saat muncul wabah seperti Tha’un atau penyakit menular lainnya.
Dalam konteks ini, inai hanya digunakan pada tiga jari—ibu jari, jari tengah (raja), dan kelingking. Tidak hanya perempuan, laki-laki dari berbagai usia juga ikut melakukannya. Tradisi ini diyakini sebagai bentuk perlindungan spiritual, penolak bala, dan ikhtiar menjaga keselamatan keluarga.
Di tengah arus modernitas dan tren global, tradisi boh gaca tetap bertahan. Namun, tantangannya semakin besar. Kini, penggunaan henna dalam pernikahan kadang lebih bersifat kosmetik daripada spiritual. Pewarna sintetis pun mulai menggantikan daun pacar alami.
Meski demikian, banyak keluarga dan komunitas adat yang masih menjaga makna aslinya. Upacara peusijuk, pemilihan malam ganjil, serta doa-doa adat tetap dilestarikan—terutama di perdesaan dan keluarga yang menjunjung tinggi adat istiadat.
Boh gaca bukan hanya pewarna kuku. Ia adalah simbol cinta, harapan, restu, dan perlindungan. Boh gaca mengisahkan cerita tentang perjalanan budaya dari India dan Timur Tengah ke tanah Rencong, lalu menyatu dalam tradisi adat Aceh.
Selama masih ada yang mengoleskan inai di tangan anak gadis menjelang akad nikah, selama itu pula warisan budaya ini tetap hidup, tak hanya di tangan, tapi juga di hati orang Aceh.

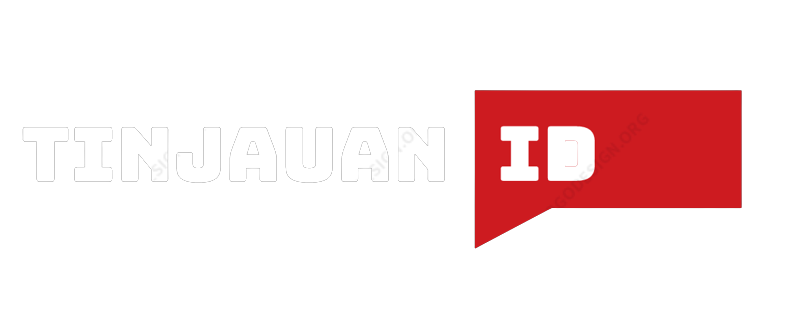














Discussion about this post