Jika Aceh berani mengaktifkan kembali tradisi Seuneubok itu dalam kebijakan lebih membumi, pendekatan ini menuntut partisipasi aktif komunitas warga lokal: mulai dari perencanaan kawasan hutan lindung, pembagian manfaat (benefit-sharing), hingga pengawasan.
Oleh: Akhsanul Khalis*
Teringat di pagi yang merekah itu, lima belas tahun lalu, tahun 2010. Lewat jalur utara, dari desa Lambadeuk, Kecamatan Peukan Bada. Saya bersama rombongan pendaki lainnya menapaki jalur pendakian menuju puncak Goh Leumo.
Sepanjang jalan setapak itu di kiri kanan tampak bekas kebun warga—pinang tua, melinjo serta sisa pagar bambu sudah lapuk yang dibiarkan begitu saja. Suasana jalurnya juga tidak jauh berbeda apabila kita pergi ke pantai Lhok Mata Ie, titik nol ujung Pulau Sumatera yang dikenal panorama indah berpasir putih.
Biasanya sebelum memasuki rimba, kita sudah diingatkan dengan tulisan pada papan besar: “Hutan Lindung Dilarang Memasuki, lengkap dengan Undang-Undang” Dulu rasanya ketika membaca itu, sekilas kita diajak untuk menjaga lingkungan, seperti kawasan yang menurut hukum, seharusnya steril dari jejak aktivitas pembukaan lahan. Tentu himbauan itu sangat didukung sepenuh hati tanpa perlu berpikir kritis.
Kini berbeda, hal itu baru muncul ketika perspektif tentang makna konservasi sudah mulai diperluas. Kenyataan tak semurni atas nama menjaga lingkungan. Kita tidak bisa menelan itu mentah-mentah. Apakah benar konservasi sebatas regulasi kemudian memisahkan akses warga lokal terhadap ekologis sekaligus ekonominya ?
Jebakan Ekofasisme
Papan peringatan itu seperti menegur kenyataan yang saya lihat sepanjang jalur. Ada kebun, ada jejak kerja tangan manusia, ada sejarah keluarga yang menggantungkan hidup pada lahan di kaki bukit. Atas nama konservasi, di mata negara, mereka seolah tak pernah ada.
Ketika negara dengan mudahnya mengkategorikan kawasan menjadi “lindung” atau “produksi”, warga lokal perlahan tersingkir.
Lebih ironis lagi, pada saat masyarakat dilarang menggarap hutan yang mereka rawat turun-temurun, izin HPH dan konsesi perkebunan justru diberikan kepada konglomerasi. Standar ganda itu menampakkan wajah paling gamblang ketidakadilan ruang.
Kenyataan ini, mulai ramai dibicarakan di Mukim Lampuuk. Dalam hal ini, kita sepakat dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui tim pembahas Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) baru saja menyetujui perubahan status sebagian hutan lindung di kawasan itu menjadi Hak Penggunaan Lainnya (HPL).
Berita ini mungkin hanya terdengar sebagai keputusan teknis tata ruang. Namun bagi warga yang sejak lama memanen palawija dan memetik cengkeh di lerengnya, keputusan itu menyangkut satu pertanyaan mendasar: tentang kehidupan.
Kita perlu belajar tentang kesalahan paradigma konservasi. Dimana konservasi tanpa mempertimbangkan aspek kemanusian, misalkan yang terjadi di Taman Nasional Pulau Komodo.
Ketika itu pemerintah NTT ingin ekosistem Komodo lebih liar tanpa kehadiran manusia. Kebijakannya adalah menyingkirkan warga yang sejak ratusan tahun hidup berdampingan dengan predator purba itu.
Pemindahan paksa dan pembatasan ruang hidup atas nama “perlindungan alam” justru melupakan fakta bahwa lanskap Komodo adalah hasil interaksi panjang manusia dan satwa liar—bahkan sebelum negara Indonesia hadir.
Konservasi yang meniadakan sejarah dan hak komunitas lokal layak dilabeli dengan istilah ekofasisme: alam disakralkan, manusia dikorbankan, dan kekuasaan negara menjadi dalih tunggal untuk mengatur siapa berhak tinggal di tanah leluhur.
Sosial Konservasi
Perubahan status hutan di Lampuuk mestinya tidak semata dibaca sebagai ancaman bagi konservasi, melainkan peluang untuk menata ulang hubungan negara dengan rakyatnya.
Pemerintah dapat menetapkan batas konservasi yang ketat sambil mengakui hak kelola masyarakat yang sudah ratusan tahun menjaga kawasan. Inilah cara menyalurkan semangat hutan rakyat ke dalam kebijakan ruang: melindungi alam sekaligus memberdayakan manusia.
Aceh sebenarnya memiliki warisan pengelolaan lahan atau hutan rakyat yang jauh lebih tua sebelum keberadaan birokrasi modern: seuneubok. Sejak masa kerajaan, masyarakat membuka hutan secara kolektif, lalu membagi hak garap dengan musyawarah.
Seuneubok bukan sekadar teknik bercocok tanam, tetapi cara membangun solidaritas dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak ada sertifikat, tetapi ada kejelasan hak; tidak ada peta zonasi, tetapi ada kesepakatan yang dihormati.
Jika Aceh berani mengaktifkan kembali tradisi Seuneubok itu dalam kebijakan lebih membumi, pendekatan ini menuntut partisipasi aktif komunitas warga lokal: mulai dari perencanaan kawasan hutan lindung, pembagian manfaat (benefit-sharing), hingga pengawasan. Pemerintah dan LSM bukan satu-satunya aktor; masyarakat adalah mitra sejajar guna memastikan bahwa politik pangan benar-benar berpihak.
Tradisi itu mengajarkan bahwa apa yang disebut dengan reforma agraria bukanlah gagasan baru, justru relate dan telah hidup ratusan tahun di Aceh. Pertanyaan masalah saat ini adalah siapa yang menguasai tanah?
Data ekonomi menegaskan urgensinya. Sektor pertanian dan kehutanan masih menyumbang hampir sepertiga PDRB Aceh dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.
Jadi ketika berbicara konteks ketahanan pangan yang digulirkan pemerintah bukan hanya soal stok beras di gudang, tetapi bagaimana keberlanjutan akses masyarakat terhadap lahan yang mereka kelola. Tanpa itu, swasembada hanyalah “omon-omon”.
Paul McMahon dalam Feeding Frenzy: The New Politics of Food mengingatkan bahwa pangan di era global kerap menjadi arena spekulasi dan geopolitik. Negara yang abai pada hak petaninya akan bergantung pada impor dan korporasi besar. Aceh pun tak kebal. Jika lahan subur terus diberikan kepada investor besar, kita akan kehilangan benteng pertama ketahanan pangan, sekaligus merusak tatanan sosial yang telah lama menjaga hutan.
Sebenarnya Aceh sudah memiliki modal sosial tentang kolektivitas: gotong royong dan adat mukim yang menekankan kebersamaan. Sayangnya, kebijakan pangan nasional seringkali terjebak pada target produksi dan program swasembada yang top–down, inilah disebut upaya governmentality. Alhasil, ketahanan pangan akhirnya dimaknai sebagai persoalan logistik negara, bukan kedaulatan masyarakat desa.
Reforma agraria di Aceh, karena itu, bukan hanya kebijakan teknis melainkan pilihan moral. Negara perlu mengakui hak masyarakat adat, memberi kepastian hukum bagi kebun rakyat, dan menjaga keseimbangan ekologis. Qanun tata ruang seharusnya menjadi pintu keadilan, bukan kemudian justru jadi lahan basah bagi privatisasi bagi pemodal.
Banyak kisah kemandirian warga desa yang lahir dari kebun dan lumbungnya. Misalkan tentang seorang bapak yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan, suatu hari ia bercerita tentang mendadak perlu biaya kuliah anak, ia tak menunggu belas kasihan—cukup masuk ke kebun di pinggir hutan, memetik kemiri, dan menjualnya ke pasar.
Dari situ uang kuliah terbayar, tanpa utang, tanpa menunggu bantuan pemerintah. Inilah ketahanan pangan yang sesungguhnya: beras tersimpan di lumbung, sayur tumbuh di halaman, kebun dikelola bersama tanpa rasa takut digusur. Mereka tidak menuntut kekayaan, hanya kepastian bahwa anak bisa sekolah, kesehatan terjamin, dan tanah tetap menjadi sumber pencarian.
Contoh inspiratif datang dari Marinaleda, sebuah distrik di Provinsi Andalusia, Spanyol. Kota itu membuktikan bahwa tanah komunal, kendali ditangan komunitas dapat menciptakan kesejahteraan tanpa harus masuk investasi konglomerasi dan negara. Setiap keluarga bekerja di lahan bersama, pengangguran nyaris nol, dan hasil panen cukup untuk hidup layak.
Pendakian ke Goh Leumo yang dulu saya lakukan kini terasa seperti metafora. Di pintu rimba, papan peringatan pemerintah masih berdiri tegak, tetapi di baliknya, jejak kebun warga terus berbicara. Seuneubok menandai bahwa pengelolaan kolektif bukan romantisme belaka masa silam, melainkan jalan menuju masa depan.
*Penulis adalah Peneliti Politik dan Kebijakan Publik, Lembaga ESGE Study Center.
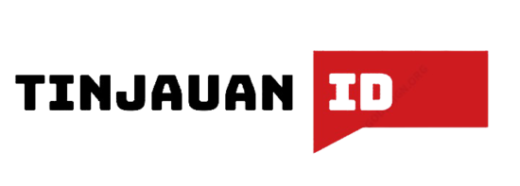
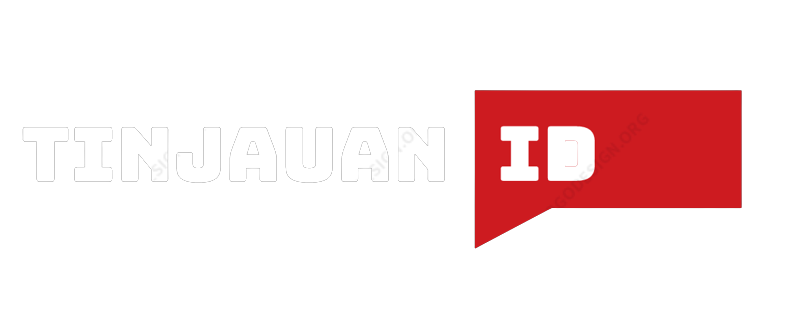

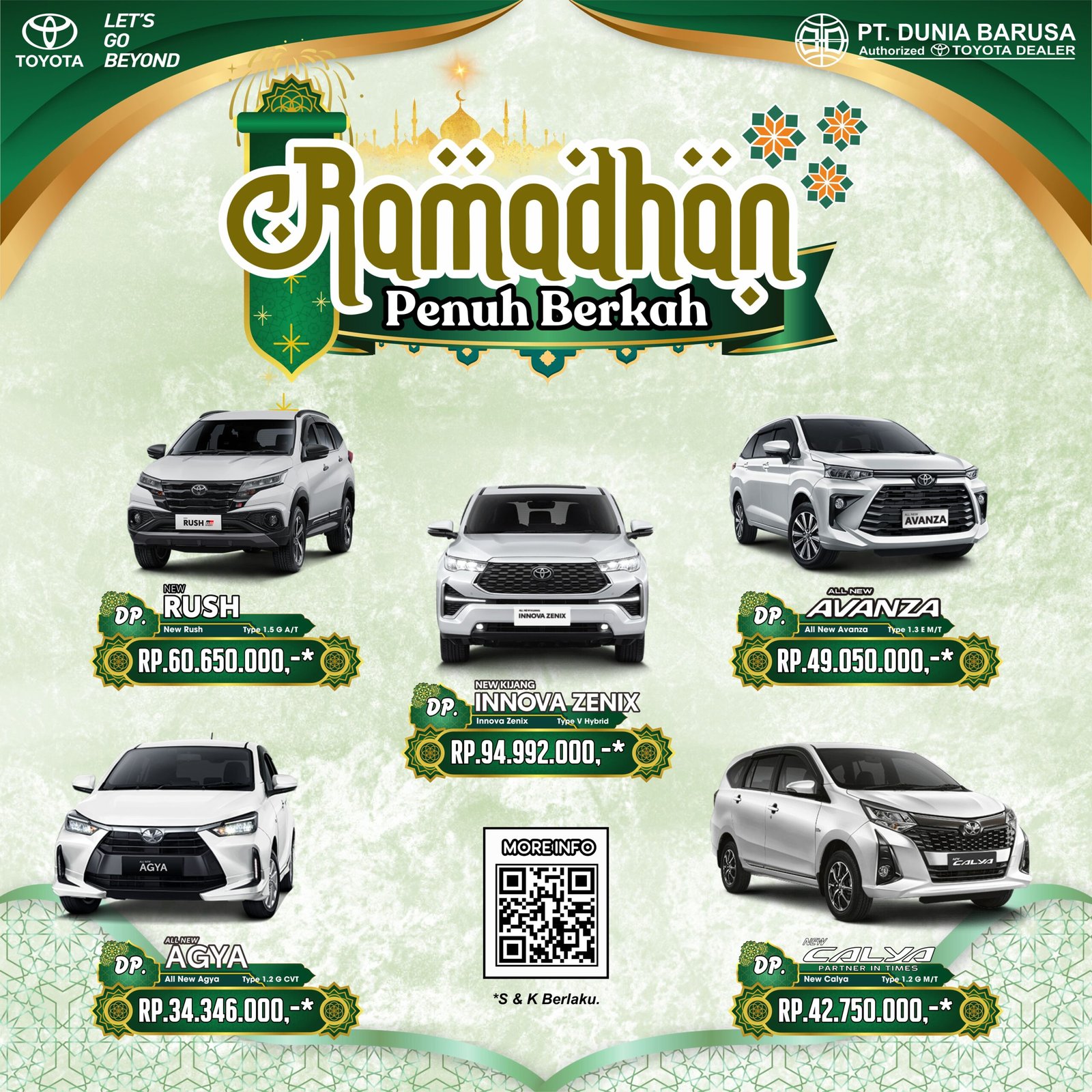












Discussion about this post